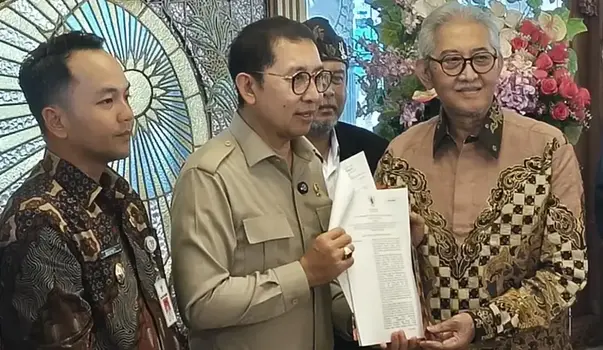Jakarta, TheStanceID - Aneh tapi nyata. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur soal peradilan, belum mengatur prinsip equality of arms (Kesetaraan dalam Proses Peradilan) untuk seluruh warga negaranya.
Padahal, prinsip tersebut sangat krusial diatur karena memungkinkan semua pihak memiliki kesempatan dan perlakuan yang seimbang dalam proses peradilan.
Peneliti Indonesia Legal Resources Center (ILRC) Siti Aminah Tardi menegaskan KUHAP bukan hanya penting bagi “orang yang bersalah” tapi untuk seluruh warga negara karena setiap orang bisa saja berada dalam posisi hukum sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, atau pelapor.
“Sebenarnya KUHAP itu menjadi alat negara untuk menggunakan kekuasaannya, terhadap warga negara. Karena itu prinsip fair trial atau prinsip peradilan yang adil sangat penting,” ujarnya dalam diskusi digelar INFID bertajuk “RKUHAP: Situasi dan Tantangan bagi Perempuan, Anak, Disabilitas, Masyarakat Adat, dan Kelompok Pengaturan Khusus”, Rabu (6/8/2025).
Ia menegaskan bahwa sangat penting dalam membahas RKUHAP, lantaran akan menjamin hak kita sebagai warga negara untuk setara dalam menghadapi kekuasaan atau alat-alat kuasa yang dipakai negara untuk menjerat warga secara hukum.
Karena itu, perlu prinsip equality yang bertujuan menciptakan ruang atau proses penciptaan keadilan yang setara untuk semua pihak. Istilahnya: equality of arms atau kesetaraan posisi dalam proses peradilan pidana, yang harus dijamin dalam RKUHAP.
Prinsip ini mencakup hak-hak mendasar seperti akses terhadap informasi, kesempatan setara dalam menghadirkan dan memeriksa bukti, hak melakukan pemeriksaan silang (cross examination), dan hak atas pendampingan serta bantuan hukum.
Marak Ketimpangan dalam Proses Peradilan
 Dalam praktiknya kata Siti Aminah, masih terjadi ketimpangan khususnya antara jaksa penuntut umum dan pihak tersangka atau kuasa hukumnya.
Dalam praktiknya kata Siti Aminah, masih terjadi ketimpangan khususnya antara jaksa penuntut umum dan pihak tersangka atau kuasa hukumnya.
Misalnya: tak mudah mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahkan, dalam beberapa kasus dokumen tersebut baru bisa diakses saat persidangan sudah dimulai, dan itu pun harus melalui perdebatan terlebih dahulu di ruang sidang.
Kondisi tersebut kata dia menunjukkan belum terjaminnya kesetaraan akses informasi. Padahal prinsip equality of arms adalah fondasi dari proses peradilan yang adil dan seharusnya dijamin secara eksplisit dalam pembaruan KUHAP.
Selain itu, menurutnya RKUHAP juga menyisakan berbagai persoalan mendasar, terutama terkait prinsip interest of justice dan pengakuan terhadap hak-hak korban.
Pemberian bantuan dan pendampingan hukum diatur berdasarkan ancaman pidana: 5 tahun atau lebih, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Menurut KUHAP sekarang, bantuan hukum hanya wajib diberikan jika ancaman pidananya minimal 5 tahun.
“Bagaimana dengan kelompok rentan atau minoritas yang terjerat kasus dengan ancaman pidana rendah? Apakah mereka tidak berhak atas bantuan hukum hanya karena ancaman hukumannya tidak memenuhi batas minimal?” ujarnya.
Ia menilai pendekatan ancaman pidana yang digunakan dalam RKUHAP berpotensi menutup akses keadilan bagi kelompok rentan.
Lebih jauh, Siti Aminah menekankan pentingnya pembaruan definisi korban dalam RKUHAP. Saat ini, RKUHAP disebut masih menggunakan definisi korban dalam pengertian sempit.
Perbarui Definisi Korban

Mengacu pada deklarasi prinsip dasar hak korban yang diadopsi PBB sejak 1985, korban bukanlah hanya individu, tapi juga bisa bersifat kolektif seperti masyarakat hukum adat, badan hukum, keluarga dan para pihak yang terdampak secara tidak langsung.
Saat ini, hak keluarga korban, hak anak atau tanggungan korban, ataupun mereka yang membantu korban tidak diakui secara hukum. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah mengakomodasi hak-hak tersebut.
Ia mencontohkan, dalam kasus pembunuhan nonseksual atau tindak pidana berat lainnya, keluarga korban masih belum dijamin haknya untuk memperoleh informasi, dukungan, atau bantuan hukum.
“Jika kita tidak memperluas pengertian korban, maka masyarakat hukum adat, keluarga korban, dan kelompok rentan lainnya akan terus tertinggal dari sistem keadilan,” paparnya.
Ia menegaskan, RKUHAP belum sepenuhnya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
Meski sejumlah hak telah dicantumkan dalam draf RKUHAP, perlu perluasan cakupan definisi korban dan penjaminan empat hak utama mereka, yaitu: akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, hak atas restitusi, kompensasi, serta bantuan.
Dalam klaster keadilan dan perlakuan yang adil, penggunaan victim impact statement (pernyataan dampak dari korban) dinilai sebagai bentuk partisipasi penting dalam proses hukum.
Namun sayangnya, mekanisme ini belum diakomodasi dalam RKUHAP, sehingga keputusan penting dalam proses pidana masih sangat bergantung pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa mempertimbangkan langsung suara korban.
Penghapusan Jejak Digital Korban Kejahatan Seksual
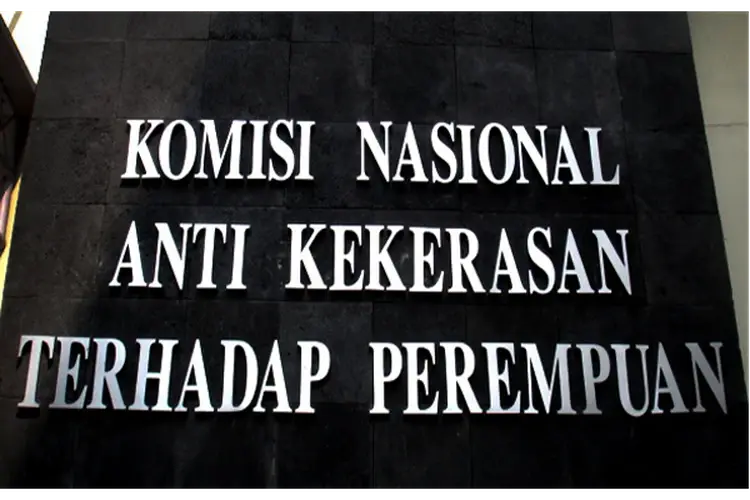
Masalah lainnya adalah absennya pengaturan mengenai penghapusan jejak digital bagi korban kejahatan seksual. Saat ini, hak tersebut baru diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang cakupannya masih terbatas.
Soal restitusi dan kompensasi juga masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Dalam RKUHAP, dana pemulihan korban diperkenalkan, namun belum jelas dari mana sumber pendanaannya dan bagaimana mekanismenya akan dijalankan.
Dana tersebut menurut Siti Aminah seharusnya tidak hanya berlaku untuk ahli waris sah, tetapi juga untuk keluarga korban sebagai hak kolektif, dan pelaksanaannya melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk mematuhi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Rekomendasi Umum Komite CEDAW, termasuk rekomendasi nomor 39/2022 tentang perlindungan perempuan dan anak perempuan adat.
Dalam rekomendasi itu, pelibatan hukum adat tidak boleh membatasi hak-hak perempuan dan harus dibangun di atas prinsip keadilan yang inklusif dan tidak melanggar HAM, baik melalui pendekatan negara maupun integrasi dengan praktik hukum lokal.
Ia menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil tidak menolak seluruh isi RKUHAP. Mereka justru mendukungan pembaruan hukum acara pidana, yang sudah lama dibicarakan sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik pada 1999.
Namun, proses pembaruan tidak boleh terburu-buru. Berbagai faktor baru—mulai dari lahirnya hukum pidana khusus, lembaga HAM, hingga perkembangan teknologi dan keputusan Mahkamah Konstitusi harus diintegrasikan secara hati-hati.
Oleh karenanya, prinsip equality of arms harus menjadi landasan utama pembaruan, yakni memastikan seluruh pihak baik korban maupun pelaku memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses keadilan.
Keadilan Bagi Perempuan

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Indonesia Khotimun Sutanti menegaskan perlunya revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lebih tegas dan berkeadilan bagi perempuan.
Pernyataan ini disampaikan LBH APIK Jakarta, melalui catatan kritis terhadap RKUHAP. LBH APIK adalah lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual.
Menurut Khotimun, titik awal kajian ini adalah memastikan apakah regulasi yang ada telah mengakomodasi pengalaman perempuan sebagai tersangka, terdakwa, maupun korban.
“Meski telah disebutkan hak perempuan, penyandang disabilitas, dan hak asasi manusia, kami belum menemukan rumusan yang konkret dan dapat dijalankan, terutama karena mandatnya tidak jelas, misalnya pada Pasal 138,” ujarnya.
Berikut ini bunyi ayat-ayat dalam Pasal 138 RKUHAP yang tidak disertai aturan tentang institusi pelaksana penyediaan hak tersebut:
Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.
Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak, yaitu mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan; mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender; mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.
Rawannya Aturan Soal Penangkapan

Selain itu juga ketentuan penangkapan selama 7×24 jam yang dinilai berisiko tinggi memicu kekerasan terhadap perempuan. Hal itu tertuang tiga ayat pada Pasal 90 RKUHAP:
Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang
Dalam hal tertentu, penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari
Kelebihan waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa Penahanan
“Waktu penahanan yang lama membuat perempuan sangat rentan, apalagi jika pertimbangan penegak hukum subyektif. Siapa yang sebenarnya dilindungi oleh aturan ini?” tegasnya.
LBH APIK juga menggarisbawahi sejumlah prinsip dasar yang harus menjadi pegangan penyusun undang-undang, di antaranya proses hukum bebas diskriminasi dan pemahaman terhadap kompleksitas latar belakang perempuan.
Demikian juga, soal kepastian rumusan hukum yang eksplisit, posisi bebas dari intimidasi dan stereotip, serta akses mekanisme pengaduan yang berpihak pada korban.
Baca Juga: RKUHAP Belum Lindungi Keadilan Masyarakat Adat
Dalam pemetaan yang disampaikan ke Komisi III, LBH APIK memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyidik wajib merujuk perempuan ke layanan dukungan dan memastikan kehadiran pendamping atau penasihat hukum dalam gelar perkara.
Selain itu upaya paksa, diharuskan disertai evaluasi masa penangkapan, penggeledahan oleh petugas perempuan, serta penahanan yang mempertimbangkan kondisi khusus seperti kehamilan atau menyusui.
Kemudian perlu perluasan definisi kelompok rentan dan memastikan hak perempuan diatur di setiap tahap proses peradilan. Terakhir yaitu mekanisme praperadilan, di mana perlu menyediakan kejelasan status laporan serta mekanisme keberatan yang efektif jika proses hukum mandek.
Khotimun menegaskan, masukan ini tidak boleh berhenti pada forum formal, tetapi harus benar-benar diakomodasi dalam revisi peraturan perundang-undangan.“Proses hukum harus berpihak pada perempuan dan melindungi mereka secara nyata.” (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.