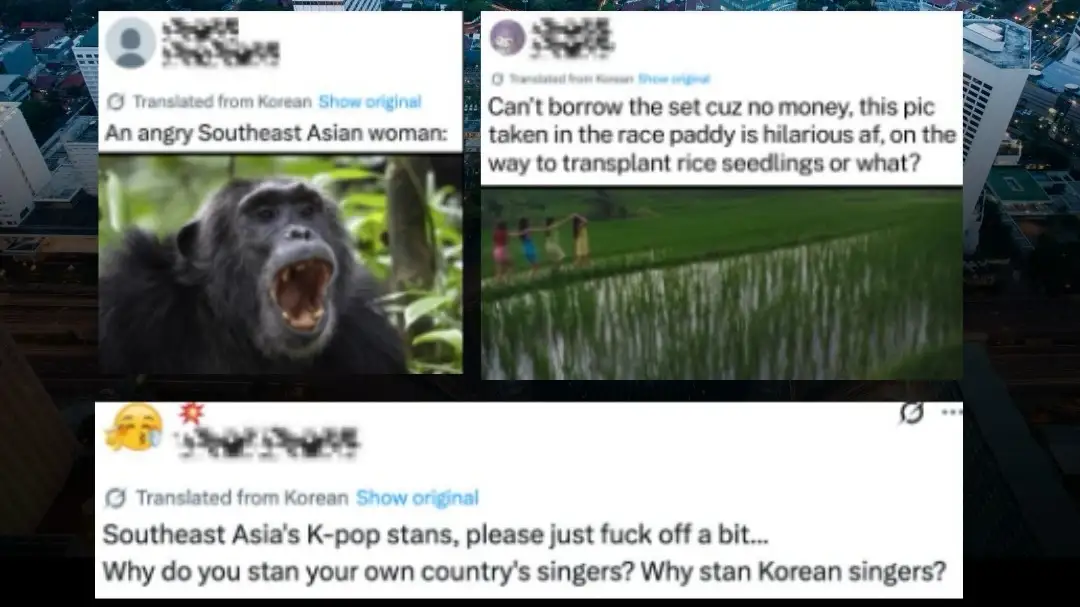Oleh Edwin Partogi Pasaribu, aktivis Kontras yang menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 dan Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024. Pernah bergabung di Tim Investigasi lapangan Penembakan Intan Jaya (2002) dan viral setelah berperan penting menjaga saksi kunci kasus Fredy Sambo, dia kini aktif menjadi praktisi hukum di Public Virtue Research Institute dan Dewan Pakar TheStance.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam pertimbangan menyatakan:
“mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” adalah syarat yang harus dipenuhi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.
Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang expressis verbis (terang), yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain (halaman 180 Putusan MK 114).
Namun pertimbangan MK juga menyisakan problem, karena MK tetap mengakui adanya jabatan lain yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20/2023.
Padahal, jabatan lain bagi anggota Polri dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki limitasi.
Ini berbeda dari UU TNI Nomor 3/2025 (sebelumnya UU Nomor 34/2004) yang membatasi bahwa anggota TNI hanya boleh menjabat di 14 jabatan sipil tertentu.
MK menyatakan norma di pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagai frasa yang terang. Sayangnya MK tidak mengritisi frasa "jabatan di luar kepolisian" adalah "jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dalam penjelasan ayat 3 itu.
Seharusnya frasa tersebut juga dimaknai sebagai norma baru. Sebagaimana MK dalam Putusan No. 005/PUU-III/2005 telah memberi rambu-rambu bahwa penjelasan dalam UU tidak boleh merupakan norma baru.
MK Kurang Optimal

Dalam posisi ini, MK dapat dinilai tidak menjalankan fungsinya secara optimal melindungi konstitusional warga negara secara efektif dan menjaga agar UU tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara utuh.
Argumentasi demikian kerap dimunculkan bila ada tudingan ke MK terkait putusannya yang dinilai ultra petita (memutus melebihi apa yang dimohonkan).
Putusan MK ini sebenarnya tidak serta menghapus atau melarang polisi pada jabatan sipil namun hanya terbatas menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”.
Artinya dengan dihapusnya frasa tersebut dari penjelasan Pasal 28 ayat (3), maka tidak ada konsekuensi harus “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” bagi polisi yang mendapat penugasan bukan dari Kapolri.
Sebagai contoh: jabatan pimpinan tinggi (JPT) utama (kepala lembaga pemerintahan non kementerian) seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunjuk bukan oleh Kepala Polri (Kapolri) melalui penugasan, melainkan oleh Presiden (data pemerintah di halaman 158, Putusan MK 114) meski mereka masih terkait tugas kepolisian.
Merujuk hal ini, putusan MK 114 itu dapat dinilai menguntungkan perwira tinggi (Pati) Polri yang tidak harus mengundurkan diri ketika mendapat tugas dari Presiden sebagai JPT utama dan JPT madya (jabatan struktural eselon 1 di pemerintah pusat).
Perpol Tak Punya Legitimasi

Terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10/2025, jelas tak memiliki legitimasi karena UU 2/2002 tak memberi mandat Kapolri menerbitkan Perpol. Perpol ini dapat dibaca sebagai penegasan Polri tentang instansi apa saja yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.
Namun, bila merujuk Pasal 149 PP 11/2017, nama Jabatan, kompetensi, dan persyaratan jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota TNI/Polri ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan persetujuan Menteri.
Di sisi lain, meskipun UU 20/2023 membuka ruang ASN menjabat di TNI dan Kepolisian, rasanya pasal tersebut hanya dekoratif. Faktanya, tak ada PNS yang menjadi jabatan pimpinan tinggi di kedua instansi tersebut.
Penempatan tentara/polisi aktif di jabatan sipil jelas berpotensi inkonstitusional. Lebih dari soal pengaturan dalam UU yang kerap digunakan sebagai alat legitimasi TNI/Polri duduki jabatan sipil.
Hal lain yang mencemaskan, sekalipun Dwifungsi ABRI secara formal dihapus, praktik pengisian jabatan sipil oleh TNI/Polri sebenarnya menunjukkan dwifungsi terselubung.
Militer/polisi masuk kembali dalam pemerintahan sipil, ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Dwifungsi Polri harus dihindari, bukan malah dinormalisasi karena dampak serius praktik dwifungsi Polri akan berekses pada banyak hal.
Dwifungsi Polri mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dan aparat keamanan.
Ketika polisi aktif menduduki jabatan sipil, pengambilan keputusan publik tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali sipil, melainkan bercampur dengan logika keamanan dan komando.
Dwifungsi Bertentangan dengan Demokrasi

Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi konstitusional yang menegaskan aparat bersenjata tunduk pada otoritas sipil, bukan sebaliknya.
Negara hukum mensyaratkan pembatasan kekuasaan dan kepastian hukum.
Dwifungsi Polri malah menciptakan kewenangan ganda (penegak hukum sekaligus pengelola kebijakan), membuka konflik kepentingan, menempatkan aparat koersif di posisi pembuat keputusan administratif.
Akibatnya, hukum berpotensi dipakai sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai norma yang membatasi kekuasaan. Polisi yang menjabat jabatan sipil tidak lagi berada dalam posisi netral.
Mereka berpotensi terikat pada kepentingan politik dan birokrasi, berpotensi menggunakan kewenangan kepolisian untuk melindungi kepentingan institusinya. Hal ini tentu merusak profesionalisme Polri dan melemahkan kepercayaan publik.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan harus saling mengawasi.
Dwifungsi Polri malah memperluas kekuasaan eksekutif tanpa kontrol memadai, melemahkan peran pengawasan eksternal serta menciptakan self-oversight ketika polisi mengawasi kebijakan yang ia ikut rancang.
Kehadiran polisi di jabatan sipil menormalkan penggunaan pendekatan koersif dalam urusan administrasi dan kebijakan publik. Kebijakan publik berpotensi makin represif, berorientasi pengamanan, bukan pelayanan, dan minim partisipasi masyarakat.
Ini berbahaya bagi ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
Dwifungsi menciptakan perlakuan istimewa bagi polisi aktif dibanding ASN tentu merusak prinsip meritokrasi. Menciptakan kasta jabatan berbasis kekuatan koersif. Dan melemahkan profesionalisme birokrasi sipil.
Baca Juga: Polemik "Dwifungsi Polisi" & Putusan MK (1): Polisi Tak Sepenuhnya Salah
Di tengah proses institusional reformasi kepolisian yang berlangsung, dwifungsi Polri menandai kemunduran agenda reformasi.
Praktik ini menghidupkan kembali pola kekuasaan lama, mengaburkan pemisahan fungsi sipil–keamanan, menciptakan dwifungsi versi baru dengan legitimasi administratif.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Hal normatif dalam mekanisme negara hukum adalah peraturan perundang-undangan. Langkah yang dapat dilakukan adalah revisi UU Polri.
Revisi ini diperlukan untuk mempertegas pembatasan eksplisit jabatan sipil. DPR harus menjalankan fungsi checks and balances secara nyata. Di sisi lain, Presiden wajib menjaga supremasi sipil sebagai mandat konstitusi.
Presiden harus menolak penempatan Polri aktif di jabatan sipil umum, menghentikan praktik “penugasan politis” dan menegaskan kembali doktrin Polri di bawah kendali sipil, bukan sebaliknya.
Dalam konteks internal, Polri harus melakukan reformasi sistem karier perwira tinggi. Di antaranya dengan cara menghentikan “parkir jabatan” di kementerian/lembaga, membatasi jumlah Pati dan menyesuaikan dengan struktur organisasi.
Demikian juga dengan mendorong early retirement atau golden handshake. Menegaskan karier di luar Polri wajib pensiun atau mengundurkan diri. Sehingga tidak ada loyalitas ganda.
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil bukan isu teknis, melainkan soal arah demokrasi. Jika dibiarkan, praktik ini akan menjadi norma baru yang menggerus negara hukum.
Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus dijaga melalui batas kekuasaan yang tegas dan konstitusional.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance