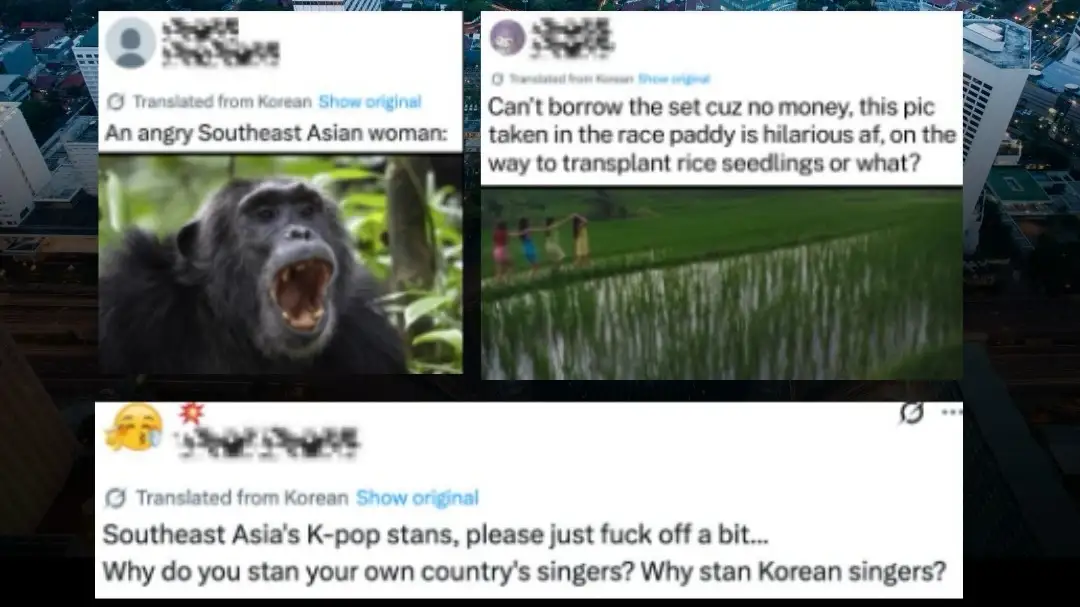Oleh Edwin Partogi Pasaribu, aktivis Kontras yang menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 dan Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024. Pernah bergabung di Tim Investigasi lapangan Penembakan Intan Jaya (2002) dan viral setelah berperan penting menjaga saksi kunci kasus Fredy Sambo, dia kini aktif menjadi praktisi hukum di Public Virtue Research Institute dan Dewan Pakar TheStance.
Penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10/2025 tentang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di luar struktur organisasi kepolisian memunculkan polemik di ruang publik.
Peraturan ini dipersoalkan karena dinilai bertentangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 serta berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan reformasi kepolisian.
Putusan MK tersebut pada intinya menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Frasa tersebut dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Baik Undang Undang Dasar (UUD) Pasal 30 ayat (4) maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 telah menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Menegaskan peran itu, TAP MPR VII/2000 memberi rambu jelas, yakni membolehkan polisi menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Kebolehan ini adalah eufemisme dari pelarangan karena mensyaratkan pengunduran diri dan atau pensiun sebelumnya. Artinya tak ada ruang untuk rangkap status bila ingin menjabat di jabatan sipil lainnya.
Pertanyaannya: mengapa hal ini jadi polemik?
Memahami Akar Persoalan

Sekalipun Tap MPR itu telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Tap MPR No I/2003, semangat yang terkandung merefleksikan semangat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Karena itu, substansi UU 2/2002 harus dimaknai sesuai dengan itu.
Problem muncul karena regulasi selanjutnya tak sejalan. Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
Namun, penjelasannya menyatakan “Yang dimaksud dengan 'jabatan di luar kepolisian' adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”
Penjelasan pada Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 jelas bermasalah. Norma yang sudah jelas dalam batang tubuh menjadi karet. Penjelasan itu malah membuat tafsir baru dari norma yang ada di batang tubuh.
Bahkan penjelasan ini dijadikan dasar membuat peraturan lebih lanjut, dengan norma baru. Patut diduga penjelasan pasal 28 ayat (3) ini memiliki motif terselubung "mengakali norma pada batang tubuh" sehingga memicu ketidakpastian hukum.
Namun, tidak hanya pada UU 2/2002 yang bermasalah, UU lainnya malah menegaskan kebolehan polisi (dan Tentara Nasional Indonesia/TNI) menduduki jabatan sipil, baik dengan melepaskan jabatan, atau pensiun, atau tanpa beralih status sama sekali.
Hal ini dapat kita lihat pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5/2014 yang kemudian diganti oleh UU Nomor 20/2023, yang memberi lampu hijau jabatan ASN tertentu diisi anggota TNI/Polri, baik jabatan manajerial maupun jabatan fungsional.
Pengaturan lebih lanjut atas ketentuan ini juga dapat dibaca pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan masih berlaku dan PP Nomor 17/2020.
Ketidakjelian Pemerintah & DPR
 Dengan membaca perjalanan produk regulasi tersebut di atas, maka pelaku utama dari problem ketidakpatuhan konstitusional yang melahirkan polemik polisi pada jabatan sipil sebenarnya adalah pembuat UU itu sendiri yaitu pemerintah dan DPR.
Dengan membaca perjalanan produk regulasi tersebut di atas, maka pelaku utama dari problem ketidakpatuhan konstitusional yang melahirkan polemik polisi pada jabatan sipil sebenarnya adalah pembuat UU itu sendiri yaitu pemerintah dan DPR.
Namun polemik penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri memang tidak muncul secara tiba-tiba--yang berujung "akal-akalan norma regulasi", melainkan merupakan akumulasi dari beberapa faktor struktural dan politik.
Pertama, Regulasi yang tidak konsisten dan ketiadaan limitasi yang tegas. Kerangka hukum yang mengatur penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian menunjukkan inkonsistensi dan ambiguitas.
Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2/2002 pada prinsipnya membatasi jabatan sipil bagi polisi aktif, tapi pasal penjelasan membuat norma baru yang membuka ruang penafsiran luas soal jenis jabatan, sifat penugasan, durasi, serta mekanisme pengawasan.
Ketiadaan limitasi ini menciptakan celah normatif yang rawan disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta profesionalisme Polri.
Kedua, kepentingan pragmatis kementerian/lembaga atas nama “pengamanan” atau “perlindungan”. Kementerian/lembaga memanfaatkan polisi aktif untuk pengamanan institusional, perlindungan pejabat, atau penguatan kewenangan secara informal.
Pendekatan pragmatis ini mengaburkan batas antara fungsi sipil dan fungsi kepolisian, serta berpotensi menormalisasi penggunaan aparat kepolisian sebagai instrumen kekuasaan administratif, bukan sebagai penegak hukum yang independen.
Ketiga, kepentingan internal Polri terkait distribusi jabatan perwira tinggi. Penempatan polisi aktif di luar institusi tak dapat dilepaskan dari dinamika internal Polri, khususnya terkait manajemen karier dan distribusi jabatan bagi perwira tinggi.
Penugasan di kementerian/lembaga jadi mekanisme alternatif untuk menampung kelebihan struktur jabatan, yang pada akhirnya menjadikan penugasan sipil sebagai solusi administratif, bukan kebutuhan fungsional yang berbasis mandat undang-undang.
Baca Juga: Membangkang Putusan MK, Kapolri Terbitkan Aturan Polisi Aktif Bisa Jabat di 17 Kementerian
Terakhir, faktor kemauan politik (political will) presiden. Dimensi politik turut berperan signifikan, terutama ketika presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memberikan preferensi terhadap penempatan polisi dalam jabatan di luar Polri.
Ketika kemauan politik ini tidak disertai dengan pembatasan hukum yang ketat, maka terjadi pergeseran relasi sipil–kepolisian yang berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan arah reformasi sektor keamanan.
Patut diingat, semua jabatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) Utama dan JPT madya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, bukan Keputusan Kepala Polri (Kapolri).
Persoalan selanjutnya: putusan MK pada 13 November lalu tak serta-merta menjernihkan polemik mengenai realitas regulasi "dwifungsi polisi" ini. (Bersambung)***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance