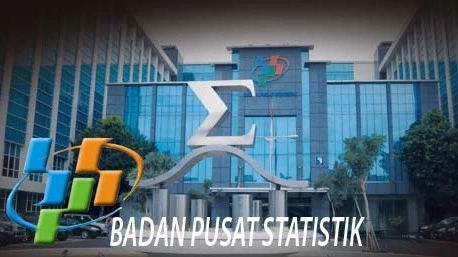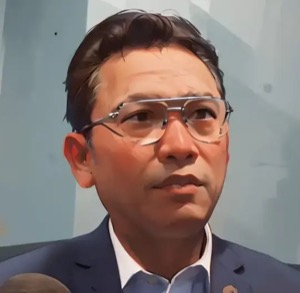
Oleh Edwin Partogi Pasaribu, aktivis Kontras yang menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 dan Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024. Dia pernah bergabung di Tim Investigasi lapangan Penembakan Intan Jaya (2002) dan viral setelah berperan penting menjaga saksi kunci kasus Fredy Sambo. Kini aktif menjadi praktisi hukum di Public Virtue Research Institute dan sebagai Dewan Pakar TheStance.
Parlemen tengah mengutak-atik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (RKUHAP). Di antara banyak pasal yang menjadi sorotan akademisi, mahasiswa maupun organisasi masyarakat sipil, salah satunya soal Saksi Mahkota.
Saksi Mahkota bukan istilah baru. Sejak lama Penuntut Umum kerap menggunakannya saat bukti minim, di mana di antara terdakwa menjadi saksi untuk menjerat terdakwa lain.
Tapi, praktik ini penuh kontroversi. Di satu sisi membantu pembuktian, di sisi lain rawan melanggar hak terdakwa.
Padahal, Indonesia sudah punya konsep justice collaborator (JC) yang disebut dengan Saksi Pelaku dalam Undang-Undang 31/2014 tentang Perubahan Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Saksi Pelaku adalah pelaku yang bekerja sama membantu mengungkap kejahatan besar, dari korupsi, narkotika, dan terorisme serta tindak pidana lainnya.
Dia sudah punya payung hukum yang jelas, dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dihargai atas perannya mengungkap perkara lebih terang. Sementara, saksi mahkota masih samar, hanya jadi alat bukti tambahan.
Terminologi Saksi Mahkota dalam RKUHAP ini terasa remake (daur ulang) yang mengadopsi pola lama. Kehadiran Pengaturan saksi mahkota dalam RUU KUHAP perlu ditinjau dari sisi harmonisasi dengan keberadaan Saksi Pelaku dalam UU 31/2014.
Apabila tidak diatur dengan baik, keberadaan dua konsep ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan dapat melemahkan perlindungan hukum bagi saksi pelaku.
Pertanyaan yang muncul dari soal ini: bagaimana konsep Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP? Apa perbedaan Saksi Mahkota dengan Saksi Pelaku dalam UU 31/2014? Apa dampak pengaturan Saksi Mahkota terhadap efektivitas perlindungan JC?
Tanpa Saksi, Sulit Ada Putusan
 Saksi memegang peran penting dalam pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi ditempatkan di urutan pertama sebagai alat bukti karena dianggap sebagai "alat bukti bicara" (speaking evidence) yang krusial.
Saksi memegang peran penting dalam pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi ditempatkan di urutan pertama sebagai alat bukti karena dianggap sebagai "alat bukti bicara" (speaking evidence) yang krusial.
Saksi dipandang sebagai pihak yang derajat keterlibatannya (selain terdakwa) paling besar dalam hal mendengar, melihat, dan mengalami suatu perkara pidana.
Bahkan, Ajit Joy, Country Manager United Nation Office of Drug and Crime Indonesia (2010), menegaskan keterangan saksi menentukan benar atau palsunya suatu perkara. Tanpa saksi, pengadilan sulit menjatuhkan putusan.
Karena itu, saksi menjadi kunci pemidanaan pelaku kejahatan sekaligus menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan masyarakat.
Hakim berbeda pandangan soal penerimaan saksi mahkota. Sebagian membolehkan asalkan berkas dakwaan dipisah (splitsing) dan didukung bukti lain. Namun banyak ahli, termasuk mantan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto, menolak penggunaannya.
Menurut di, saksi mahkota bertentangan dengan asas fair trial dan prinsip non self incrimination, yang melarang terdakwa menjerat diri sendiri. Prinsip ini ditegaskan di Pasal 66 dan 175 KUHAP serta Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005.
Kasus Marsinah, Nasrudin Zulkarnaen, dan Vina Cirebon menunjukkan praktik penggunaan saksi mahkota.
Satu-satunya pedoman yang ada hanyalah Surat Edaran Jaksa Agung No. B-69/E/02/1997. Surat edaran ini mensyaratkan pemisahan berkas perkara dan tetap harus melengkapi dengan alat bukti tambahan.
Dari sini terlihat, saksi mahkota masih menjadi praktik kontroversial. Tanpa dasar hukum yang kuat, penggunaannya rawan melanggar hak terdakwa dan prinsip peradilan yang adil.
Saksi Mahkota dalam RKUHAP: Pola Lama?

RKUHAP bukan produk baru. Drafnya sudah ada sejak 2004, bahkan sebelum UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir yang kemudian mengatur “saksi yang juga tersangka.” Namun frasa itu baru muncul di UU 31/2014 dengan nama 'Saksi Pelaku.'
Sejak awal, penyusunan RKUHAP banyak dipengaruhi praktik peradilan dan tarik-menarik kepentingan antar lembaga penegak hukum. Hukum acara pidana lebih dilihat sebagai aturan main antar kekuasaan, bukan perlindungan hak azasi manusia (HAM).
Posisi saksi dipandang penting hanya untuk pembuktian, tapi tidak perlindungannya.
Dalam draft final RKUHAP 3 Maret 2025 (sumber: ICJR), saksi mahkota didefinisikan sebagai tersangka atau terdakwa berperan ringan yang dijadikan saksi untuk mengungkap pelaku lain dalam perkara yang sama.
Atau, terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif agar mendapat keringanan pidana. Penunjukan saksi mahkota ada di tangan penuntut umum. Mekanisme ini seharusnya menjamin keadilan dan menghindari kesaksian paksa.
Pengaturan Saksi Mahkota dalam RKUHAP, antara lain; pertama, tahap penyidikan (Pasal 22 ayat 3). Penyidik dapat menetapkan tersangka menjadi Saksi Mahkota untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
Kedua, tahap penuntutan (Pasal 69). Penuntut umum dapat menawarkan saksi mahkota kepada tersangka berperan ringan, atau kepada terdakwa yang mengaku bersalah bila tidak ada perannya yang paling ringan
Ketiga, Kesepakatan (Pasal 70 ayat (1)). Negosiasi dilakukan antara tersangka, advokat dan penuntut umum. Kesepakatan meliputi keterangan yang akan diberi, syarat yang harus dipatuhi, pasal yang akan dituntut, serta imbalan dan jaminan dari penuntut umum.
Imbalan Penuntut Umum kepada saksi mahkota adalah: tak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, mengurangi ancaman pidana hingga 2/3 (dua pertiga), atau menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman kurang dari 7 (tujuh) tahun.
Baca Juga: Polemik Proses Rancangan KUHAP: Partisipasi Masyarakat Sudah Meaningful?
Keempat, jika negosiasi gagal, Penuntut Umum tidak boleh menggunakan keterangan Tersangka sebagai alat bukti di pengadilan (Pasal 70 ayat (1)).
Dari pengaturan tersebut, saksi mahkota dalam RKUHAP memberi ruang baru pada praktik lama. Namun, fokus utamanya masih pada pembuktian, bukan perlindungan saksi atau penghormatan HAM.
RKUHAP seharusnya membawa pembaruan hukum pidana. Tapi pasal Saksi Mahkota di pandangan penulis terasa seperti kemunduran. la mengulang pola lama yang lebih berpihak pada kebutuhan aparat, daripada perlindungan HAM.
Apalagi, kehadirannya bisa menyingkirkan peran LPSK dalam melindungi JC, karena penyidik dan jaksa lebih nyaman memakai saksi mahkota. Akibatnya, perlindungan jadi lemah dan potensi penyalahgunaan makin terbuka.
Menghidupkan saksi mahkota di RKUHAP sama saja mengulang kesalahan lama. Negara seharusnya memperkuat JC, bukan membangkitkan konsep yang lemah secara hukum. (bersambung)***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance