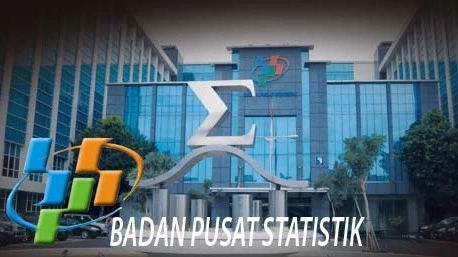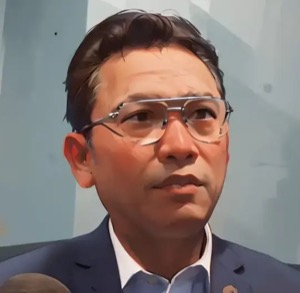
Oleh Edwin Partogi Pasaribu, aktivis Kontras yang menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 dan Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024. Dia pernah bergabung di Tim Investigasi lapangan Penembakan Intan Jaya (2002) dan viral setelah berperan penting menjaga saksi kunci kasus Fredy Sambo. Kini aktif menjadi praktisi hukum di Public Virtue Research Institute dan sebagai Dewan Pakar TheStance.
Sejak lama Penuntut Umum menggunakan Saksi Mahkota saat bukti minim, di mana terdakwa menjadi saksi untuk menjerat terdakwa lain. Tapi praktik ini penuh kontroversi. Di satu sisi membantu pembuktian, di sisi lain rawan melanggar hak terdakwa.
Padahal, Indonesia sudah punya konsep justice collaborator (JC) yang disebut dengan Saksi Pelaku dalam Undang-Undang 31/2014 tentang Perubahan Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Baca tulisan sebelumnya: Remake 'Saksi Mahkota' di RKUHAP: Rawan Disalahgunakan, Minim Perlindungan HAM
Dari sisi tujuan tak ada perbedaan antara Saksi Mahkota dan Saksi Pelaku, yaitu, untuk membantu pembuktian atas perbuatan pelaku lainnya. Namun, terkait penanganan khusus dan penghargaan Saksi Mahkota dapat kita bandingkan dengan Saksi Pelaku.
Pertama, saksi mahkota belum memiliki legitimasi hukum, bahkan praktiknya lebih banyak menimbulkan pro kontra.
Sementara itu, Saksi Pelaku telah memiliki tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 13/2006, UU Nomor 31/2014 dan UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Yang terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 24/2025 yang mengatur tentang mekanisme pemberian penanganan khusus dan penghargaan bagi Saksi Pelaku.
Ada juga Peraturan Bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2011.
Di tingkat kementerian terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7/2022 yang salah satunya mengatur pemberian hak narapidana kepada Saksi Pelaku.
Bahkan Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran MA Nomor 4/2011 telah memberi panduan bagi Hakim dalam menangani perkara yang melibatkan Saksi Pelaku.
Tak Terlepas dari Hukum Internasional
 Sebenarnya pengaturan Justice Collaborator (JC) dalam hukum nasional tak terlepas dari pengaruh aturan internasional ketika itu.
Sebenarnya pengaturan Justice Collaborator (JC) dalam hukum nasional tak terlepas dari pengaruh aturan internasional ketika itu.
Ketentuan JC termuat di United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000, yang diratifikasi di UU Nomor 5/2009.
Dan tiga tahun berselang, terdapat United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi), yang diratifikasi melalui UU Nomor 7/2006. Tak heran bila pengaturan JC pertama kali muncul dalam UU Nomor 13/2006.
Kedua, soal pelaku. Bila merujuk pada UU Nomor 31/2014, pengertian Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
Dari pengertian tersebut, Saksi Pelaku termasuk terpidana.
Relevan, karena ketika kejahatan dilakukan oleh lebih dari 1 pelaku, sangat memungkinkan mereka tidak diproses dalam waktu yang sama. Misal, pelaku lain masih dicari atau belum cukup bukti. Hal ini kerap terjadi pada perkara terorisme dan korupsi.
Ketiga, soal inisiatif. Inisiatif Saksi Mahkota sepenuhnya berada pada tangan penyidik dan atau penuntut umum. Ketentuan ini mengabaikan potensi pelaku menawarkan diri menjadi Saksi Mahkota.
Empirik, bahkan sebelum ada perkara, seorang pelaku bisa saja menginsafi perbuatannya, sehingga ia memilih jalan pedang sebagai pelapor kejahatan yang dilakukan. Contoh, Agus Condro, pelapor perkara cek pelawat yang melibatkan dirinya.
Selain itu inisiatif yang hanya berada di tangan Penyidik/Penuntut Umum, dapat berakibat pelaku yang kooperatif ketika penyidikan tidak mendapatkan penghargaan sebagai Saksi Mahkota.
Penyidik bisa saja merasa pengakuan pelaku itu sebagai ‘kewajiban’ atau keberhasilan teknik penyidikan semata, tanpa mengapresiasi sikap kooperatif pelaku.
Bila merujuk pada UU Nomor 31/2014, inisiatif selain dari pejabat yang berwenang bisa juga datang dari pelaku. Ini memberikan kesempatan aktif pelaku bersikap kooperatif kepada penegak hukum.
Problem Kategorisasi Saksi Mahkota
 Keempat, soal peran Saksi Mahkota dalam RKUHAP ini diklasifikasi dalam dua kategori, yakni pelaku dengan peran paling ringan atau pelaku lainnya yang mengaku.
Keempat, soal peran Saksi Mahkota dalam RKUHAP ini diklasifikasi dalam dua kategori, yakni pelaku dengan peran paling ringan atau pelaku lainnya yang mengaku.
Untuk menentukan siapa pelaku yang berperan paling ringan dari tindak pidana penyertaan (deelneming), Pasal 55 KUHP membagi pelaku penyertaan menjadi empat jenis:
Orang yang melakukan (pleger),
Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen),
Orang yang turut melakukan (medepleger),
Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker).
Selain itu peran penyertaan lainnya juga mencakup mereka yang sengaja membantu melakukan kejahatan, memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk kejahatan tersebut (Pasal 56 KUHP).
Pertanyaan yang harus dijawab siapa yang paling ringan perannya dari 4 jenis pelaku itu? Bila merujuk Pasal 56, peran paling ringan tentu pada pelaku perbantuan.
Berbeda dari UU 31/2014 dan SEMA 4/2014, Saksi Pelaku dikecualikan kepada pelaku utama. Dengan kata lain pelaku utama tidak bisa dapat status JC.
Dalam RKUHAP tidak ada penegasan pengecualian terhadap pelaku utama ini, sekalipun penulis berpandangan pelaku utama bisa saja menjadi JC, mengingat pelaku utama kejahatan bisa saja lebih dari satu orang.
Potensi Penyalahgunaan Saksi Mahkota Lebih Besar

Kelima, potensi penyalahgunaan lebih besar. RKUHAP harus memberi perhatian, agar status Saksi Mahkota tidak dipaksa lewat penyiksaan, hubungan transaksional atau konflik kepentingan.
Keterlibatan advokat dalam negosiasi dengan Penyidik/Penuntut Umum saja tidak cukup karena pada praktiknya penyidik kadang meminta tersangka menandatangani surat pernyataan “Bersedia diperiksa Tanpa Didamping Pengacara” atau menyiapkan pengacara ‘memuluskan’ acara pemeriksaan.
Status Saksi Mahkota dari penyiksaan, dapat kita lihat di antaranya pada perkara Marsinah dan kematian Vina Cirebon.
Status Saksi Mahkota bisa saja diperoleh dari hubungan transaksional. Dengan modus pelaku mendapatkan pasal dan tuntutan lebih ringan, oknum aparat mendapatkan keuntungan finansial.
Dugaan terhadap hubungan transaksional ini dapat kita lihat setidaknya pada penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sebagai preseden, pada tahun 2021, jumlah warga bina\an di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 252.384 orang. Menurut data Dirjen Pemasyarakatan, dari jumlah itu ada 27.543 Narapidana yang berstatus JC, sebagian besar (99%) adalah narapidana narkotika dan psikotropika.
Pertanyaan yang muncul, siapa pelaku utama yang dibongkar oleh JC tersebut? Atau mengapa memberikan status JC ketika pelaku berstatus terpidana? Kejaksaan menyumbang 2/3 (dua per tiga) status JC itu dan sisanya didominasi oleh kepolisian.
Konflik kepentingan pemberian status JC terbuka potensinya ketika pelaku adalah aparat penegakan hukum (APH). Atau, APH ‘memiliki target’ pelaku tertentu, sehingga pelaku lain diarahkan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku tersebut.
Tak heran publik mencurigai pemberian status Saksi Mahkota atau JC sebagai jadi ajang barter kepentingan.
Dipukul Rata ke Semua Tindak Pidana
 Keenam, tindak pidana. Tidak ada pembatasan tindak pidana Saksi Mahkota dalam RKUHAP. Sementara UU 31/2014 membatasi pemberian status itu kepada pelaku pada tindak pidana tertentu.
Keenam, tindak pidana. Tidak ada pembatasan tindak pidana Saksi Mahkota dalam RKUHAP. Sementara UU 31/2014 membatasi pemberian status itu kepada pelaku pada tindak pidana tertentu.
Pembatasan dimaksudkan untuk berfokus pada kejahatan yang bersifat serius atau kejahatan terorganisir. Pembatasan itu penting untuk mencegah status Saksi Mahkota diobral pada semua tindak pidana.
Namun bila ada pembatasan, hal yang dapat dipertimbangkan selain berdasarkan tindak pidana tertentu, bisa juga didasarkan oleh ancaman hukuman tertentu, misalnya ancaman pidana minimal 10 tahun.
Ketujuh, pengembalian aset kejahatan. RKUHAP tidak mengatur kewajiban pelaku mengembalikan aset dari kejahatan. UU 31/2014 sudah mengatur hal ini.
Kedelapan, perlindungan. Saksi Mahkota di RKUHAP tak memperoleh jaminan perlindungan. Padahal besar potensi Saksi Mahkota terancam keselamatan jiwanya karena dianggap pengkhianat. UU Nomor 31/2014 memberi perhatian besar soal ini.
Kesembilan, penanganan khusus. Tak ada penanganan khusus bagi Saksi Mahkota berupa pemisahan penahanan, pemisahan pemberkasan, hingga memberi kesaksian tanpa perlu berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap perannya.
Rincian penanganan khusus ini sudah ada di UU 31/2014.
Kesepuluh, pemenuhan hak narapidana. Tidak ada jaminan pemenuhan hak narapidana Saksi Mahkota ketika menjalani pidana. Berbeda dengan Saksi Pelaku, UU Nomor 31/2014 menugaskan LPSK memastikan hak narapidananya dipenuhi.
Baca Juga: Prinsip Keadilan Setara Dinilai Masih Absen dalam RKUHAP
Dari perbandingan tersebut di atas, Saksi Pelaku merupakan satu-satunya konsep yang memiliki legitimasi hukum yang kuat, baik dari aspek pengaturan, perlindungan, maupun mekanisme penghargaan.
Sebaliknya, Saksi Mahkota justru tampak tertinggal secara normatif karena belum memiliki dasar hukum yang eksplisit, serta cenderung menyisakan potensi pelanggaran terhadap asas fair trial dan perlindungan hak tersangka, terdakwa atau terpidana.
Jika tujuan kita adalah keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM, maka jalan terbaik adalah harmonisasi regulasi, memperjelas perlindungan saksi pelaku, dan memastikan peran LPSK tidak dipinggirkan.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) jangan jadi langkah mundur. KUHAP baru harus hadir untuk menjawab kebutuhan zaman: hukum yang modern, adil, dan berpihak pada perlindungan HAM.
Saksi Mahkota bukan solusi, melainkan masalah baru. Inilah saatnya DPR mendengar kritik publik dan memperbaiki arah pembaruan hukum acara pidana. Jangan biarkan RKUHAP jadi jejak sejarah yang disesali di kemudian hari.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance