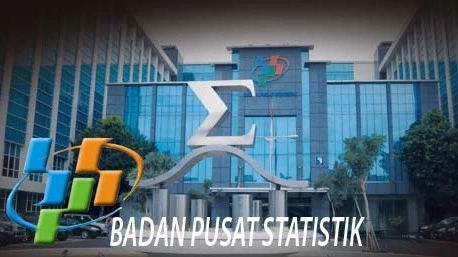Oleh Dr. Funco Tanipu, ST., M.A, dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo yang pernah menjadi penasihat di beberapa pemerintah daerah di Gorontalo. Sejak 2005, penulis produktif dan aktivis sosial ini aktif menjadi Direktur di The Gorontalo Institute.
Dalam masyarakat modern yang semakin rasional dan egaliter, gestur seperti merunduk, berjalan sambil ngesot, mencium tangan guru, atau memberikan bisyaroh (pemberian) seringkali dipandang sebagai bentuk feodalisme atau praktik usang yang tidak relevan.
Namun di balik praktik-praktik sederhana itu sesungguhnya tersembunyi warisan panjang peradaban, lapisan makna sosial-spiritual yang dalam, serta cara masyarakat Islam mengekspresikan penghormatan dan kesediaan belajar.
Untuk memahami maknanya secara adil, kita harus meninggalkan kacamata luar dan membaca praktik-praktik itu dari dalam — dari cara tradisi dimaknai oleh para pelakunya sendiri.
Pada 13 Oktober 2025, program “Xpose Uncensored” di Trans7 menayangkan segmen berjudul “Santri dan Fenomena Amplop” yang menyoroti kehidupan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Liputan tersebut menggambarkan santri “rela ngesot” demi menyerahkan amplop kepada kiai, menyebut kebiasaan mencium tangan sebagai “ritual feodal”, dan menyoroti praktik khidmat—seperti membantu guru atau membersihkan rumah—sebagai bentuk “pengabdian tidak setara.”
Tayangan itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan baik pengasuh pesantren, hingga para alumni.
Kritik utama diarahkan pada kerangka berpikir yang digunakan: gestur yang bagi pesantren dan majelis ilmu merupakan simbol cinta dan penghormatan justru dipandang sebagai simbol ketertundukan dan ketimpangan.
Peristiwa ini menggambarkan benturan dua cara pandang yang sulit bertemu: satu menggunakan kacamata modern yang sekuler dan egaliter, sementara yang lain memaknainya sebagai bagian dari tradisi spiritual yang hidup.
Akar Sejarah dan Bahasa Tubuh Penghormatan
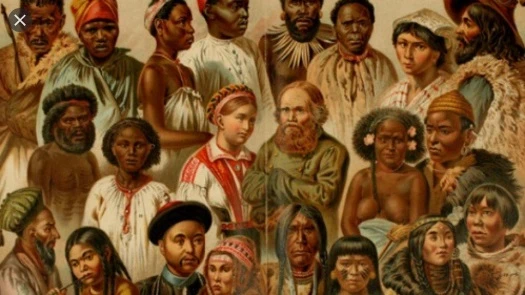
Untuk memahami perbedaan ini secara jernih, kita perlu keluar dari bias etnosentris dan melihat praktik-praktik tersebut melalui pengalaman, nilai, dan sistem makna pelakunya sendiri—pendekatan yang dalam antropologi disebut emic understanding.
Sebelum ke sana, penting untuk menelusuri akar sejarahnya.
Praktik merunduk, duduk rendah, atau bahkan ngesot memiliki akar sejarah jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara. Dalam budaya istana Hindu-Buddha, merunduk di hadapan raja atau guru spiritual merupakan bentuk kesopanan tertinggi.
Tubuh menjadi bahasa kesadaran sosial: yang belum mengetahui mendekat kepada yang berpengetahuan, yang rendah bergerak menuju yang tinggi.
Ketika Islam hadir, simbol-simbol itu tidak dihapus, tetapi diberi makna baru. Posisi raja bergeser menjadi guru agama, kekuasaan duniawi berganti otoritas ilmu.
Tubuh yang merendah bukan lagi bentuk kepatuhan politik, melainkan kesiapan batin untuk menerima pengetahuan.
Seperti dijelaskan oleh filsuf iluminasi Suhrawardī, “Cahaya yang lebih tinggi hanya akan mengalir kepada yang merendah. Semakin rendah, semakin besar ruang bagi cahaya untuk masuk.”
Dalam kerangka ini, kerendahan bukan kelemahan, melainkan kondisi awal bagi datangnya ilmu. Pemaknaan baru ini kemudian diwarisi oleh pesantren dan majelis ilmu hingga hari ini.
Relasi Pengetahuan dan Penghormatan

Sejarah memberi konteks, tetapi makna terdalam dari praktik ini ditemukan dalam relasi antara guru dan santri.
Dalam khazanah Islam klasik, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi sebagai perantara nilai-nilai ketuhanan: kasih sayang, kebijaksanaan, dan rahmat. Ibn ‘Arabī menyebut guru sebagai mazhar al-ḥaqq, manifestasi cahaya—melalui dirinya pengetahuan diturunkan.
Al-Ghazālī mengingatkan bahwa ilmu tidak akan masuk ke hati yang sombong; hanya hati yang tunduk yang dapat menjadi wadahnya.
Karena itu, gestur tubuh seperti mencium tangan, duduk rendah, atau ngesot bukanlah ritual kosong, melainkan cara untuk menyiapkan diri menerima ilmu.
Mullā Ṣadrā menambahkan, “Setiap perjalanan menuju kesempurnaan dimulai dari pengakuan akan kekurangan.”
Penghormatan bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju transformasi diri. Itulah sebabnya praktik ini tidak hanya hadir di pesantren, tetapi juga di berbagai majelis ilmu di kota dan desa, dari pengajian kampung hingga halaqah akademik.
Ngesot, Bisyaroh, dan Khidmat: Jalan Pembentukan Diri
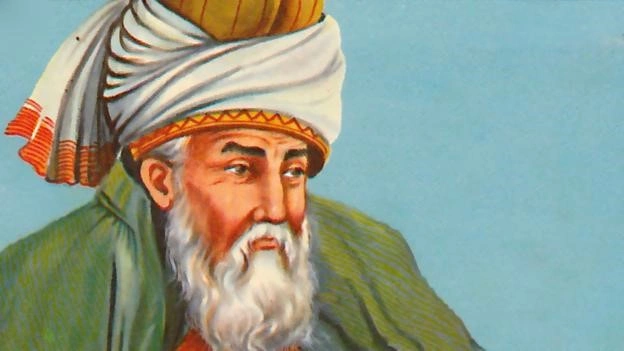
Dalam tradisi Islam, tubuh, harta, dan tindakan bukan sekadar alat duniawi, tetapi bagian dari proses pembentukan spiritual.
Ngesot adalah bahasa tubuh yang menunjukkan kerendahan hati. Bisyaroh adalah bentuk pemberian sebagai ungkapan syukur dan penghormatan. Khidmat adalah pelayanan yang dilakukan sebagai latihan kesabaran dan pengendalian diri.
Ibn ‘Arabī memandang pemberian sebagai peristiwa ilahi: manusia hanyalah saluran bagi Tuhan untuk memberi kepada diri-Nya sendiri.
Dengan memberi, santri melepaskan diri dari ilusi kepemilikan. Mullā Ṣadrā menyebut tindakan memberi sebagai gerak eksistensial menuju kelapangan nurani.
Khidmat juga berperan sebagai latihan spiritual. Al-Ghazālī menyebutnya riyāḍah—latihan untuk mengikis ego. Rūmī menulis bahwa menyapu tempat belajar dengan cinta lebih bernilai daripada menulis seribu bait puisi.
Dalam cara pandang ini, pelayanan bukan bentuk ketertindasan, melainkan latihan untuk mengendalikan diri dan mengutamakan sesuatu yang lebih tinggi dari kepentingan pribadi.
Praktik ini, dengan demikian, membentuk habitus spiritual: tubuh belajar tunduk, akal belajar menerima, hati belajar memberi.
Kritik Modernitas, Pembacaan Emik, dan Perspektif Poskolonial

Sebagian besar kesalahpahaman terhadap praktik-praktik tradisional seperti ngesot atau bisyaroh berakar pada sejarah Barat yang berbeda dari pengalaman Islam.
Di Eropa pra-Revolusi Prancis, gereja sering bersekutu dengan monarki absolut dalam sistem feodal yang menindas rakyat. Gestur penghormatan, pemberian, dan pelayanan sering kali merupakan bentuk pemaksaan politik.
Revolusi Prancis menolak semua simbol tersebut, dan trauma kolektif itu membekas dalam cara berpikir Barat: semua bentuk hierarki dicurigai sebagai penindasan.
Masalah muncul ketika pengalaman sejarah itu dijadikan ukuran universal. Simbol penghormatan dalam Islam yang berakar pada adab ilmu disamakan dengan simbol penindasan dalam sejarah Eropa.
Bisyaroh yang lahir dari cinta dianggap gratifikasi, sementara khidmat yang bertujuan menyucikan diri dibaca sebagai subordinasi.
Edward Said menyebut pola pikir ini sebagai orientalisme—cara Barat melihat Timur sebagai masa lalunya yang belum modern. Frantz Fanon menambahkan bahwa kolonialisme tidak hanya menjajah tanah, tetapi juga pikiran.
Di sinilah konsep epistemic violence dari Gayatri Chakravorty Spivak menjadi relevan. Kolonialisme pengetahuan tidak hanya menghapus narasi, tetapi juga membungkam cara masyarakat lokal memahami dirinya sendiri.
Ketika praktik seperti ngesot atau bisyaroh dilabeli sebagai “tidak rasional” atau “feodal”, yang terjadi sebenarnya adalah kekerasan epistemik: cara lokal mengekspresikan cinta dan adab dihapus karena tidak sesuai dengan kerangka berpikir modern.
Memahami Tradisi Islam Secara Kontekstual

Perspektif Talal Asad membantu kita melangkah lebih jauh. Dalam Genealogies of Religion, ia menjelaskan bahwa Islam harus dipahami sebagai tradisi diskursif—jaringan praktik, institusi, dan makna yang membentuk subjektivitas moral pelakunya.
Ritual dan gestur bukanlah bentuk kekuasaan kosong, tetapi bagian dari self-formation—cara membentuk diri melalui disiplin tubuh dan tindakan. Dengan kerangka ini, ngesot atau khidmat dipahami sebagai proses pembentukan etika yang diwujudkan secara nyata (embodied ethics).
Sementara itu, Mohammed Arkoun menekankan pentingnya membongkar “nalar tertutup” yang hanya menilai tradisi dari satu sudut pandang.
Dalam Critique of Islamic Reason, ia mendorong pembacaan yang kontekstual dan historis—yang mengakui pluralitas makna dan menolak dikotomi simplistik seperti modern vs tradisional.
Dengan cara pandang ini, praktik-praktik penghormatan dipahami bukan sebagai sisa masa lalu, tetapi sebagai ekspresi sah dari cara masyarakat memahami ilmu dan otoritas.
Perspektif antropolog Ismail Fajrie Alatas memperkuat gagasan ini.
Dalam What Is Religious Authority? ia menunjukkan bahwa kritik modernis seringkali gagal memahami kompleksitas relasi otoritas dalam Islam karena terlalu sibuk melihatnya dalam kerangka dominasi dan subordinasi.
Mereka lupa bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari tradisi tertentu yang juga tidak netral. Akibatnya, perdebatan menjadi buntu karena dua sistem epistemik yang berbeda tidak pernah benar-benar saling memahami.
Memahami tradisi dalam kerangka makna yang hidup di dalamnya—bukan dalam kategori luar—adalah jalan keluar dari kebuntuan ini.
Dalam kerangka ini, kita melihat bahwa ngesot, bisyaroh, dan khidmat bukanlah sisa feodalisme, melainkan bagian dari sistem makna yang berbeda.
Mereka menempatkan adab sebagai syarat pengetahuan, kerendahan hati sebagai jalan menuju kebijaksanaan, dan pelayanan sebagai metode pembentukan diri.
Walter Mignolo menyebutnya sebagai langkah menuju decoloniality: membongkar klaim universalitas pengetahuan modern dan memberi ruang bagi epistemologi lain untuk berbicara atas dirinya sendiri.
Baca Juga: Di Balik Polemik Tayangan Trans7, Nilai Etika Pesantren Akan Masuk Kurikulum Nasional
Praktik seperti ngesot, bisyaroh, dan khidmat tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sejarah panjang, berakar pada nilai-nilai Islam, dan berkembang sebagai cara masyarakat membentuk hubungan dengan ilmu, guru, dan dirinya sendiri.
Dalam dunia yang serba cepat dan sering menilai tanpa memahami, tradisi ini mengajarkan pelajaran penting: untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, manusia perlu belajar merendahkan diri terlebih dahulu.
Seperti air yang mengalir ke tempat rendah, ilmu dan kebijaksanaan tidak akan datang kepada hati yang dikuasai kesombongan.
Pesantren dan majelis ilmu bukanlah pabrik pencetak kekuasaan, tetapi ruang pembentukan jiwa—tempat manusia belajar bahwa kehormatan sejati bukan terletak pada berdiri di atas orang lain, tetapi pada kesediaan untuk merunduk di hadapan ilmu.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance