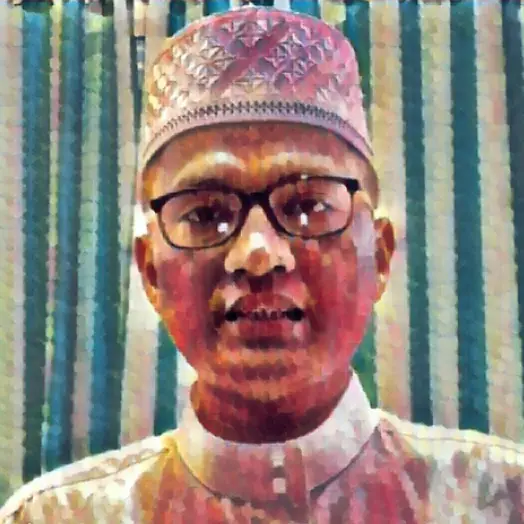
Oleh Farid Wajdi, peraih gelar Magister dalam bidang Tafsir dan Hadist dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hiadayatullah Jakarta. Pernah mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Lembaga Tahfiz dan Taklim Al-Qur'an (LTTQ), penulis buku “Yuk menghafal Alquran dengan Mudah dan Menyenangkan” tersebut kini aktif sebagai trainer penghafal Al-Qur'an.
Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa hari lalu mendapat sorotan luas.
Sebagai kepala negara dari bangsa besar, pidato tersebut diharapkan mampu menegaskan sikap tegas Indonesia terhadap salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini: genosida di Palestina.
Namun, alih-alih menegaskan sikap tegas, pidato itu justru menyisakan tanda tanya besar. Ada pengakuan tentang penderitaan rakyat Palestina, ada penegasan bahwa kejahatan kemanusiaan sedang berlangsung, bahkan ada seruan menuju perdamaian.
Tetapi, semua itu berhenti sebatas retorika. Tidak ada penyebutan jelas siapa pelaku utama genosida, tidak ada kritik keras terhadap kegagalan sistemik PBB, dan solusi yang ditawarkan justru berpotensi melegitimasi penjajahan.
Tulisan ini berusaha mengurai empat kelemahan mendasar dari pidato tersebut, sekaligus menunjukkan mengapa sikap seperti ini berbahaya: menyesatkan opini publik, mengaburkan akar masalah, dan gagal memberi arah yang benar bagi penyelesaian isu Palestina.
Mengakui Genosida, tapi Bungkam Terhadap Pelaku

Presiden Prabowo mengakui bahwa genosida sedang berlangsung di Palestina. Namun, ia tidak secara tegas menyebut siapa pelaku utamanya. Padahal, perkara ini sama sekali tidak kabur. Fakta sudah sangat terang benderang.
Pelaku utama bukan hanya figur politik seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, melainkan entitas penjajah Yahudi itu sendiri, dengan dukungan penuh Amerika Serikat (AS) sebagai sponsor militer, finansial, dan diplomatik.
Mengakui adanya genosida tanpa menunjuk pelaku berarti mengaburkan kebenaran. Bayangkan jika seorang hakim mengakui ada pembunuhan massal, tetapi enggan menyebut atau menghukum pelakunya.
Itu bukan keadilan, melainkan pengkhianatan terhadap korban. Sejarah kolonial Barat memberi banyak contoh serupa.
Negara-negara Eropa mengakui bahwa kolonialisme mereka membawa penderitaan, tetapi tidak ada satu pun pengadilan internasional yang benar-benar menghukum pelaku penjajahan, apalagi mengembalikan apa yang mereka rampas.
Sekadar mengakui, tanpa menyebut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban, hanyalah kamuflase yang membungkus kejahatan.
Jika Presiden Prabowo sungguh mengakui genosida sebagai the crime of crimes, maka konsistensi logisnya adalah menuntut akuntabilitas (accountability) atas kejahatan itu.
Pelaku harus ditunjuk, bukti harus diungkap, dan hukuman harus dituntut. Tanpa itu, seruan perdamaian hanyalah ilusi yang menyingkirkan keadilan.
Bungkam terhadap Kegagalan Sistemik PBB
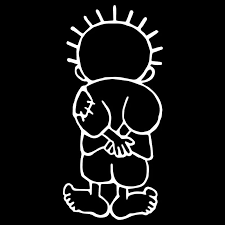
Kelemahan kedua, Presiden Prabowo tidak mengecam kegagalan PBB. Padahal, kegagalan ini bukan teknis, melainkan struktural.
PBB sejak awal dirancang sebagai alat kontrol dunia oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II. Hak veto yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan adalah bukti nyata bahwa keadilan bisa disandera oleh kepentingan politik segelintir negara.
Kenyataannya, setiap upaya menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan nyata terhadap entitas penjajah Yahudi selalu digagalkan oleh veto AS.
Artinya, PBB tidak gagal karena tidak mampu, tetapi gagal karena memang tidak didesain untuk menghukum sekutunya sendiri.
Dengan tidak mengecam hal ini, Presiden Prabowo kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan moral.
Seharusnya, seorang presiden dari negara mayoritas Muslim, yang sejak awal berdiri menentang kolonialisme, justru menegaskan kelemahan struktural PBB dan menyerukan reformasi mendasar.
Sebaliknya, diam terhadap masalah ini sama dengan membiarkan PBB terus menjadi panggung legalisasi kejahatan internasional.
Two-state Solution Berarti Melegitimasi Penjajahan
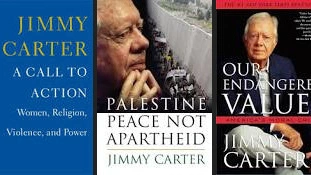
Solusi dua negara (two-state solution) kembali disebut Presiden Prabowo sebagai jalan keluar.
Tetapi, mari kita jujur: apa arti solusi ini di lapangan? Apakah ia sungguh akan menghadirkan kedaulatan Palestina? Ataukah hanya selubung politik untuk menutupi kegagalan?
Dalam visi Barat, negara Palestina versi two-state solution adalah negara tanpa kedaulatan sejati:
Tidak boleh memiliki militer sendiri (demilitarized).
Berada di bawah pengawasan dan kontrol keamanan “Israel”.
Selaras dengan norma politik, ekonomi, dan keamanan Barat.
Dengan kata lain, yang ditawarkan adalah “negara boneka” yang tunduk pada proyek kolonial zionis sejak 1948. Sebuah negara yang tidak mengakhiri penjajahan, tetapi justru mengokohkannya.
Jika Indonesia secara prinsip anti-penjajahan, maka mendukung two-state solution adalah kontradiksi besar. Sebab pengakuan atas “Negara Palestina” dalam kerangka ini berarti sekaligus mengakui legitimasi “Israel” sebagai negara penjajah.
Politik luar negeri Indonesia seharusnya tegak lurus: tidak ada kompromi terhadap kolonialisme.
Bertentangan dengan Syariah dan Amanah Umat

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, seharusnya Indonesia memiliki kompas moral yang jelas dalam isu Palestina: kompas Islam. Dalam syariah, tak ada konsep hidup berdampingan secara damai dengan penjajah.
Perintahnya tegas: penjajah harus diusir. Dengan demikian, solusi Islam bukanlah peacekeeping forces (pasukan penjaga perdamaian) yang justru akan ikut menjaga keberlangsungan penjajah.
Solusi Islam adalah mobilisasi kekuatan negeri-negeri Muslim untuk membela Palestina, membebaskan tanahnya, dan mengusir penjajah Yahudi sepenuhnya.
Inilah mandat sejarah yang diwariskan Umar bin Khattab ketika membebaskan Baitul Maqdis, dan Shalahuddin al-Ayyubi ketika mengusir tentara Salib.
Pidato Presiden Prabowo seharusnya berani menyerukan hal ini. Bukan sekadar retorika kemanusiaan universal, melainkan panggilan ideologis yang konsisten dengan identitas bangsa dan keyakinan mayoritas rakyatnya.
Tanpa itu, pidato hanya menjadi formalitas diplomatik yang kehilangan ruh perjuangan.
Pidato di PBB seharusnya menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan moral Indonesia di panggung internasional.
Namun, yang disampaikan Presiden Prabowo justru memperlihatkan sikap yang lemah: mengakui penderitaan tanpa menyebut pelaku, menyerukan perdamaian tanpa menuntut keadilan, dan menawarkan solusi yang justru melegitimasi penjajahan.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar pandai berbicara di forum dunia, tetapi berani menyampaikan kebenaran, sekalipun pahit.
Pemimpin yang berani menuding pelaku genosida, berani mengecam kegagalan struktural PBB, berani menolak solusi palsu dua negara, dan berani menyerukan mobilisasi dunia Islam untuk membebaskan Palestina.
Tanpa itu, pidato di PBB hanyalah seremoni diplomatik yang hampa.
Jika Presiden Prabowo mengakui ada genosida, sebut pelakunya. Jika bicara perdamaian, tegakkan pula keadilan. Jika mengaku anti-penjajahan, tolak semua solusi yang justru melegitimasi penjajahan.
Inilah konsistensi moral yang dituntut, bukan sekadar retorika di panggung dunia.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance







