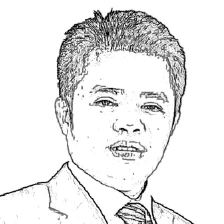
Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).
Krisis nilai tukar pasca-kesepakatan Bretton Woods tahun 1944 telah terjadi dalam tiga generasi krisis.
Dimulai dari krisis nilai tukar generasi pertama pada tahun 1980-an yang berpusat di negara-negara Amerika Latin, yaitu Chili, Brasil, Meksiko, dan Argentina. Negara-negara tersebut menganut regim nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Krisis nilai tukar generasi pertama bermula dari aliran hot money yang besar ke negara-negara Amerika Latin.
Lalu, terjadi tsunami aliran modal keluar jangka pendek (hot money) karena dipicu oleh kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada era Paul Volcker, ketua The Fed, sebagai respons terhadap inflasi ekstra tinggi di AS pada tahun 1979.
Saat itu, peningkatan suku bunga dolar AS juga diikuti oleh penurunan ekstrim harga komoditas. Hal ini menyebabkan negara-negara Amerika Latin tak mampu membayar utang yang menggelembung dari US$125 miliar ke US$800 miliar pada akhir 1979.
Selanjutnya, krisis nilai tukar generasi kedua tahun 1994 berpusat di Meksiko. Dimulai dari aliran modal masuk sangat besar setelah Meksiko bergabung dengan North Atlantic Free Trade Area (NAFTA).
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan efisiensi BUMN-nya sehingga menarik masuknya investor asing dalam jumlah besar.
Namun, langkah tersebut masih disertai masalah kredibilitas pemerintah Meksiko menjaga nilai tukar tetap, terutama karena tingginya defisit neraca transaksi berjalan.
Nilai tukar peso Meksiko akhirnya mengalami depresiasi ekstrim hingga 50%karena aliran keluar hot money yang sangat besar.
Kondisi ini memaksa pemerintah Meksiko mendevaluasi mata uangnya. Kepercayaan investor terhadap peso Meksiko hilang yang membuat pemerintahnya meminta bantuan International Monetary Fund (IMF) pada awal tahun 1995.
Krisis Generasi Ketiga Tahun 1997

Krisis generasi ketiga terjadi di negara-negara Asia pada tahun 1997 yang berpusat di Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Korea Selatan.
Krisis terjadi pada saat negara-negara Asia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, defisit anggaran kurang dari 3% Produk Domestik Bruto (PDB), dan surplus neraca transaksi berjalan.
Krisis nilai tukar generasi ketiga juga diawali aliran masuk hot money sangat besar ke negara-negara Asia karena investor asing tergiur pertumbuhan ekonomi tinggi. Tahap selanjutnya diikuti aliran modal keluar yang meruntuhkan rezim nilai tukar tetap.
Krisis Asia 1997 berbeda dari krisis generasi pertama dan kedua di Amerika Latin. Krisis Asia 1997 adalah krisis nilai tukar yang sangat luas karena menjalar ke negara-negara lain secara global.
Krisis ini ditandai oleh contagion effect, yaitu efek domino yang dimulai dari baht Thailand lalu menyebabkan krisis kepercayaan dan nilai tukar di negara-negara Asia lainnya.
Dani Rodrik (2019), ekonom Harvard's John F. Kennedy School of Government, AS menyebut krisis Asia 1997 disebabkan oleh hyper-globalisation dari investasi ke negara-negara Asia. Hal ini membuat harga saham di Asia, termasuk Indonesia naik 500%.
Lalu, apakah tren depresiasi rupiah per dolar AS saat ini dapat menyebabkan krisis nilai tukar, seperti krisis generasi pertama, kedua dan ketiga? Apa mitigasi risiko yang dapat dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI)?
Situasi Saat Ini Berbeda dari 1997

Sebagai perbandingan, pada saat krisis keuangan Asia 1997, pelemahan rupiah per dolar AS sangat cepat hingga mencapai 594% dalam setahun, yaitu dari Rp2.441 /US$ pada Juni 1997 menjadi Rp. 17.000 pada Juni 1998.
Sementara saat ini, rupiah per dolar AS hanya melemah 5,3% yaitu dari Rp16.120/US$ pada 14 Agustus 2025 menjadi Rp16.975/US$ pada 21 Januari 2025.
Pada saat yang sama, probabilitas terjadinya contagion effect dari negara lain sangat kecil, seperti krisis Asia 1997, dimulai dari speculative attack yang membuat mata uang baht Thailand terdepresiasi sebesar 20% hanya dalam sehari.
Peluang terjadinya krisis generasi keempat, seperti krisis generasi pertama, kedua dan ketiga sangat kecil.
Namun, pemerintah dan BI tetap harus menyiapkan langkah mitigasi risiko terhadap fenomena pembalikan arus modal dari pasar surat utang negara yang ditandai oleh penurunan kepemilikan investor asing dari 41% (2018) menjadi 13% (2025).
Hal ini tercermin pada net capital flow Indonesia yang negatif sejak kuartal pertama hingga ketiga 2025, yaitu outflow sebesar US$387 juta (kuartal I-2025), sebesar US$3,52 miliar (kuartal II-2025, dan US$8,07 miliar (kuartal III-2025).
Tidak banyak yang dapat dilakukan dalam jangka pendek.
Langkah pertama, mengurangi country risk premium melalui komunikasi kebijakan yang lebih teknokratik rasional dibanding retoris populis sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan kehati-hatian.
Langkah kedua, pemerintah harus mampu meyakinkan pelaku pasar dengan kebijakan moneter dan fiskal yang pruden. Menghindari kesan dominasi atau intervensi pemerintah terhadap BI dalam desain kebijakan makro ekonomi nasional.
Baca Juga: Menuju Status Negara Maju di Tengah Ketidakpastian Global
Langkah ketiga, menjelaskan secara transparan ke pelaku pasar mengenai kondisi fiskal, khususnya yang berkaitan dengan rasio defisit fiskal terhadap PDB yang telah mencapai 2,92%, mendekati batas aman 3% dan juga kondisi Debt Service Ratio (DSR) yang nilainya juga di atas batas aman sebesar 42,3%.
Langkah keempat, mendorong BI untuk tidak terburu-buru menurunkan BI rate dalam rangka menjaga selisih suku bunga riil Indonesia dengan AS dalam kondisi country risk premium Indonesia yang tinggi.
Bersamaan dengan itu, melakukan intervensi di pasar valuta asing secara terukur sehingga menghemat penggunaan devisa.
Langkah kelima, berdasarkan framework kebijakan impossible trinity atau policy trilemma, BI dapat memilih untuk fokus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah per dolar AS dan independensi BI dengan mengorbankan kebebasan arus modal.
Singkatnya, opsi pembatasan arus modal secara selektif dapat menjadi opsi kebijakan BI dalam jangka pendek.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.







