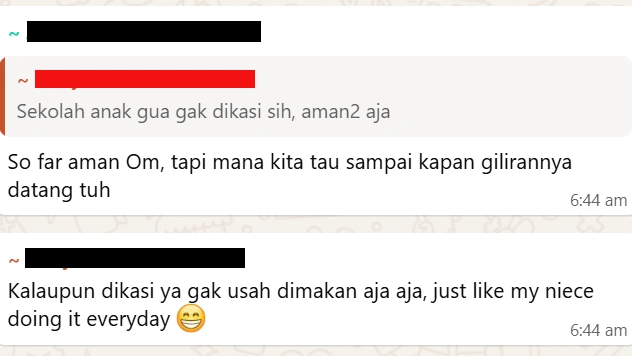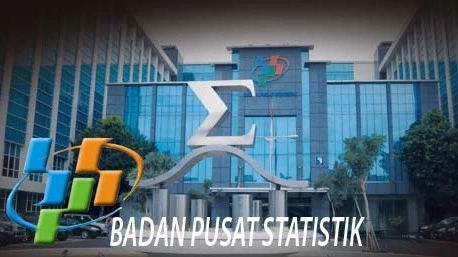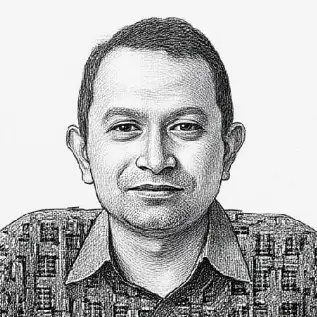
Oleh David Ardhian, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi peneliti di kini aktif mengelola lembaga Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sebagai Ketua Dewan Pakar.
Program makan sekolah di berbagai belahan dunia tidak hanya soal mengisi perut anak-anak dengan sepiring nasi atau sepotong lauk.
Sejarah panjangnya menunjukkan bahwa makanan di sekolah adalah cermin bagaimana sebuah bangsa memperlakukan generasinya, bagaimana negara memahami relasi antara pangan, pendidikan, dan masa depan.
Program makanan di sekolah selalu lebih dari kalori: ia adalah janji, instrumen moral, dan alat politik yang merefleksikan misi jangka panjang negara.
Di Inggris, embrio program makan sekolah muncul sejak abad ke-19, ketika industrialisasi menciptakan generasi buruh miskin dengan kondisi gizi buruk.
Mulanya program ini bersifat amal, dikelola gereja atau filantropi, namun segera negara menyadari bahwa persoalan kesehatan publik terlalu serius untuk diserahkan pada belas kasihan.
Undang-Undang Education (Provision of Meals) Act 1906 menandai lahirnya makan sekolah sebagai hak sosial.
Di Amerika Serikat, setelah Perang Dunia II, National School Lunch Act 1946 bukan hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga menyalurkan surplus pertanian domestik.
Jepang, setelah porak-poranda akibat perang, memanfaatkan program makan sekolah sebagai instrumen rekonstruksi bangsa sekaligus pendidikan nilai melalui shokuiku, bukan sekedar makan namun meletakkan landasan nilai dan budaya makan di Jepang sejak usia dini.
Ada Misi Besar di Balik Makan Gratis

Di belahan dunia lain, program berkembang dengan wajah berbeda.
Skandinavia mengambil jalur universalitas: Finlandia dan Swedia sejak 1940-an memutuskan semua anak, tanpa diskriminasi, berhak atas makan sekolah gratis, ekspresi kuat dari negara kesejahteraan.
India mengembangkan Mid-Day Meal Scheme sebagai jawaban atas kelaparan massal sekaligus strategi menarik anak miskin bersekolah.
Brasil mengambil langkah progresif: undang-undang mewajibkan 30% bahan pangan makan sekolah dibeli dari petani kecil, sehingga sekolah menjadi simpul kedaulatan pangan sekaligus pemberdayaan lokal.
Pola-pola tersebut konsisten dengan gagasan mission-oriented policy (Mazzucato, 2018), kebijakan publik yang dibangun dengan misi jelas, berpijak pada visi jangka panjang, bukan sekadar proyek teknokratis atau populis.
Inggris dan Amerika menempatkannya sebagai instrumen kesehatan publik dan stabilitas ekonomi pangan. Jepang menjadikannya nation-building dan pendidikan nilai.
Skandinavia menegaskannya sebagai ekspresi kesetaraan sosial universal. India menggunakannya untuk mengatasi kelaparan dan memperluas akses pendidikan. Brasil menautkannya dengan kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani.
Indonesia hari ini melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menampilkan wajah yang berlawanan.
Alih-alih menjadi proyek kebangsaan yang membangun anak sebagai pusat peradaban, MBG lahir sebagai proyek politik elektoral yang miskin orientasi.
MBG Indonesia: Naskah Akademik pun Tak Ada

Tidak ada dokumen utuh sebagai naskah akademis yang menegaskan program ini memiliki misi utama apa, apakah mengatasi kurang gizi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat petani lokal, atau menanamkan budaya makan sehat.
Semua kabur dalam jargon “bergizi gratis” yang mudah dijual secara politik, namun kosong secara konseptual.
Lebih tragis, implementasi MBG menimbulkan krisis kepercayaan publik. Hingga kini lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan akibat makanan program ini. Alih-alih menjadi simbol pelayanan negara, makanan berubah menjadi sumber trauma.
Meski menjadi tragedi, namun respons negara tetap minimalis. Sekadar evaluasi teknis, tanpa tinjauan serius terhadap korban. Anak-anak yang keracunan diperlakukan seolah kelinci percobaan, tumbal dari kegagalan perencanaan.
Tidak ada permintaan maaf memadai, tidak ada program pemulihan trauma, tidak ada edukasi mengapa makanan bergizi justru menimbulkan penyakit.
Kepala negara bahkan mereduksi tragedi ini dengan menyebut bahwa hanya 0,00017% makanan yang “beracun,” sehingga dianggap wajar. Reduksi anak-anak korban menjadi angka statistik adalah bentuk paling telanjang dari politik tanpa empati.
Program diteruskan, anak-anak yang keracunan ditinggalkan.
Lebih jauh, MBG melahirkan pola tata kelola yang sentralistik dan militeristik. Sentralisme membuat program berbiaya besar, tidak efisien, dan rentan gagal, bahkan membahayakan kesehatan anak.
Pola Pikir Militerisme dalam MBG
 Militerisme menghadirkan paksaan. Anak-anak dianggap sekadar obyek yang harus disuapi, tanpa ruang partisipasi, tanpa memperhatikan dunia psikologis dan selera mereka.
Militerisme menghadirkan paksaan. Anak-anak dianggap sekadar obyek yang harus disuapi, tanpa ruang partisipasi, tanpa memperhatikan dunia psikologis dan selera mereka.
Ilmu pengetahuan diabaikan; tidak ada riset, tidak ada uji coba sosial, tidak ada persiapan matang, tidak ada prioritas yang jelas. Semua berjalan terburu-buru demi pertunjukan politik yang bisa dipamerkan segera.
Ironisnya, inisiatif-inisiatif lokal yang selama ini sudah berjalan baik justru dipaksa bubar.
Sekolah-sekolah yang sudah memiliki dapur sehat berbasis partisipasi orang tua dan guru, seperti di sekolah Muhammadiyah Solo, harus menghentikan programnya karena MBG masuk sebagai “program nasional.”
Dapur yang selama ini dikelola dengan pemahaman nutrisi, partisipasi orang tua murid dan inovasi menu sehat kini digantikan dengan makanan massal dari vendor instan. Orang tua menjadi resah, takut anaknya keracunan.
Dari laporan jaringan guru, anak-anak mulai membawa rantang kosong untuk membuang makanan yang tidak mereka sukai. Guru resah, karena dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi keracunan.
Mereka harus berjibaku menerima kiriman makanan, mengelola pembagian, hingga mengumpulkan kembali wadah, bahkan harus menanggung kerugian bila ada kehilangan.
UMKM lokal hanya menjadi penonton, petani tidak terhubung dan pemerintah daerah terlibat dengan penuh keterpaksaan.
Lebih dalam, tata kelola MBG kacau balau. SPPG, penyedia lapangan, dituntut memasak hingga 3.000 paket per hari. Masak dimulai tengah malam, sehingga makanan tidak segar, berisiko terkontaminasi bakteri, dan menimbulkan keracunan.
Sentralisme MBG Picu Akuntabilitas Rendah
 Tak ada hubungan dengan petani lokal, justru terjadi persaingan pembelian di pasar. Bahkan mulai ada laporan petani didatangi langsung di kebun, dipaksa menjual hasil panen dengan harga ditekan, praktik pengadaan yang penuh nuansa militeristik.
Tak ada hubungan dengan petani lokal, justru terjadi persaingan pembelian di pasar. Bahkan mulai ada laporan petani didatangi langsung di kebun, dipaksa menjual hasil panen dengan harga ditekan, praktik pengadaan yang penuh nuansa militeristik.
Sentralisme dan militerisme melahirkan karakter program menjadi miskin akuntabilitas, anti partisipasi dan pelecehan sains. Ini "racun" tata telola yang paling berbahaya.
Produksi skala ribuan paket diperlakukan seolah pesta hajatan: tanpa teknologi, tanpa gudang, tanpa infrastruktur, tanpa tenaga ahli gizi, tanpa inovasi menu. Distribusi pun serba ngawur, penuh kerumitan, tanpa memperhitungkan keragaman konteks lokal.
Menu yang muncul pun aneh: dari makanan ultra-proses, burger, sandwich, bahkan ikan hiu (spesies langka) dengan dalih “kearifan lokal.”
Semua ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan refleksi dari keangkuhan penguasa, keterburuan karena rakus pujian dan kehampaan sains dalam perencanaan.
Di balik kekacauan itu, aroma rente begitu kental. Mulai dari kontrak vendor berbasis jejaring kekuasaan, dapur instan yang disulap tanpa standar, hingga pengadaan ompreng impor murah dari Tiongkok yang ditengarai mengandung minyak babi.
Bahkan pengawasan publik ditekan: guru dan sekolah diminta tidak mengekspos menu, menutupi kasus keracunan, dan tetap diam demi keberlangsungan proyek.
MBG dengan demikian bukan hanya krisis nutrisi, tetapi juga krisis tata kelola, krisis moral, dan krisis kepercayaan bahkan menuju krisis kemanusiaan.
Berisiko Berakhir Menjadi Bencana

Jika dibiarkan, MBG akan tercatat dalam sejarah sebagai policy catastrophe (Beck, 1992). Kebijakan yang dilahirkan dengan retorika seolah mulia, tetapi justru menimbulkan bencana sosial.
Karena itu, satu-satunya jalan rasional adalah menghentikan program dalam bentuknya sekarang, lalu merancang ulang dengan visi baru. Desain ulang ini harus berangkat dari filosofi kasih sayang (caring), bukan paksaan (control); perlu partisipasi, bukan kendali.
Empat lapisan kunci harus ditata: pertama, memahami dunia anak dan psikologi makan mereka, dengan menempatkan anak sebagai subyek aktif yang didengar aspirasinya.
Kedua, membangun ekosistem sekolah yang mengintegrasikan edukasi gizi, pengelolaan dapur sehat, hingga penanganan limbah makanan.
Ketiga, memberdayakan UMKM lokal, dapur komunitas, dan ahli gizi sebagai mitra utama, bukan vendor instan. Keempat, menghubungkan sekolah dengan produksi petani lokal dalam kerangka ekosistem pangan sehat yang berkelanjutan.
Keempat lapisan ini dibangun dalam kerangka ekosistem pangan sehat sekolah berbasis inovasi, sains dan partisipasi masyarakat.
Program makan sekolah harus ditransformasikan dari proyek politik menjadi proyek pengasuhan. Ibu-ibu, guru, komunitas lokal, dan ilmuwan lintas disiplin harus dilibatkan penuh.
Diversitas Indonesia harus dihargai, bukan diseragamkan dalam menu homogen. Militer dan polisi harus ditarik keluar dari program; paksaan dan tekanan diganti dengan partisipasi dan inovasi.
Tata kelola nasional harus bersandar pada sistem berbasis data, dashboard evaluasi, serta pengawasan transparan. Tanpa sains, kegagalan program bukanlah soal “jika”, tetapi soal “kapan.”
Baca Juga: Keracunan Massal MBG, Negara Pilih Reformasi Sistem atau Jaga Status Quo Cuan SPPG?
Pada akhirnya, makan sekolah adalah cermin kemanusiaan kita. Bagaimana kita memberi makan anak-anak akan menentukan wajah masa depan bangsa.
MBG hari ini bukan hanya gagal memberi nutrisi namun juga gagal memberi rasa aman dan kepercayaan.
Tak sesuai namanya: bergizi belum tentu malah menimbulkan kasus keracunan, gratis juga tidak karena menggunakan dana fantastis dari APBN, dari pajak rakyat.
Akhirnya, alih-alih menyediakan nutrisi yang dijanjikan, yang muncul justru manipulasi. Dari janji mulia, yang tersisa hanyalah pengkhianatan, dalam bentuk merendahkan kemuliaan anak dan sekolah.
Tidak ada rasa empati, bahwa di balik makanan untuk anak, ada titipan doa dari orang tuanya, agar anaknya tumbuh kembang secara sehat dan patut.
Untuk menghindari krisis lebih dalam, jalan satu-satunya adalah mengembalikan makan sekolah pada esensinya: memuliakan anak-anak, menjaga kesehatan mereka, dan menumbuhkan generasi dengan penuh cinta, sains, dan keadilan sosial.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance