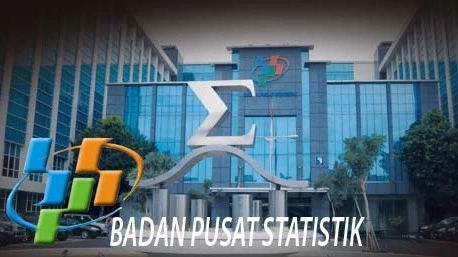Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), alumni KRA 37 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), kini menjadi Ketua Rukun Warga (RW) 16 Kelurahan Sekeloa, Bandung dan aktif di Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC).
Politik ekonomi mengajarkan bahwa kebijakan publik tidak hanya tentang perencanaan yang ambisius, tetapi lebih tentang kelangsungan hidup (sustainability) dalam menghadapi realitas anggaran yang terbatas.
Perumahan rakyat dan angkutan umum, sebagai dua sektor yang sangat bergantung pada intervensi negara, adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim fiskal.
Proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi contoh nyata bagaimana visi besar politik harus berhadapan dengan neraca keuangan yang ketat.
Dalam skenario di mana kedua proyek ini dalam tahap penyelesaian namun dibayang-bayangi hambatan fiskal sangat ketat, sementara operasi dan pemeliharaan aset (yang sudah jadi) harus berjalan, politik ekonominya memasuki fase paling krusial dan berisiko.
Ketika anggaran pemerintah menyusut secara signifikan, prioritas politik dan ekonomi mengalami ujian berat. Konflik kepentingan antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah menjadi semakin tajam.
Pemerintah terperangkap dalam dilema: menghentikan proyek berarti mengubur investasi yang sudah ditanam dan merusak reputasi politik, melanjutkannya berarti mengalihkan anggaran dari sektor-sektor kritis seperti kesehatan dan pendidikan, sementara membiayai operasional aset yang sudah berdiri adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari.
Nasib dan Lanjutan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Asumsi: segmen Jakarta-Bandung telah beroperasi, namun pembangunan segmen Bandung-Surabaya tersendat akibat kurangnya pendanaan.
Stasiun-stasiun yang sudah dibangun membutuhkan biaya perawatan tinggi, sementara pendapatan operasional segmen pertama belum mencukupi untuk membiayai kelanjutan proyek.
Dalam situasi ini, politik ekonomi proyek berubah drastis:
Tekanan Utang dan Negosiasi Ulang yang Rumit
Pemerintah Indonesia akan berada dalam posisi tawar yang sangat lemah terhadap kreditur, dalam hal ini terutama Exim Bank of China (?).
Untuk mendapat dana penyelesaian atau restrukturisasi utang, pemerintah mungkin harus menyetujui syarat-syarat yang lebih berat, misalnya penjaminan oleh aset strategis lainnya atau intervensi yang lebih besar dalam tata kelola operasional.
Ini merupakan bentuk baru dari ketergantungan fiskal yang berpotensi mengikis kedaulatan ekonomi.
Politik Menaikkan Tarif yang Berlebihan
Untuk menutupi biaya operasi yang membara dan menunjukkan 'komitmen komersial' kepada investor, pemerintah akan berada di bawah tekanan besar untuk menaikkan tarif kereta cepat secara signifikan dan mengurangi frekuensi moda kereta api lainnya pada koridor yang sama.
Kebijakan ini sangat politis karena akan mengubah sifat layanan dari "angkutan massal" menjadi "angkutan elit" seperti yang sudah terjadi — layanan kereta api antar kota bukan untuk rakyat lagi.
Kereta cepat perlahan akan mengingkari janji awalnya untuk mendukung mobilitas publik yang efisien. Demonstrasi dan penolakan publik akan menjadi risiko politik yang nyata.
Mengorbankan Rute dan Integrasi

Opsi paling pragmatis—namun memalukan secara politik—adalah mengurangi cakupan proyek.
Pemerintah mungkin memutuskan hanya menyelesaikan segmen hingga Solo atau Malang, dan meninggalkan rencana integrasi penuh dengan kota satelit.
Ini akan memangkas manfaat ekonomi keseluruhan proyek dan menciptakan "jalan setapak" yang tidak optimal.
Mendorong Private Involvement dengan Iming-iming Manis
Solusi yang sering diambil adalah mempercepat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau bahkan menjual sebagian saham aset yang sudah dibangun (misalnya stasiun atau depot) kepada investor swasta.
Politik ekonominya, pemerintah terpaksa menukar aset strategis jangka panjang dengan likuiditas tunai jangka pendek untuk menyelamatkan proyek.
Swasta akan meminta konsesi operasi yang menguntungkan, yang sekali lagi berpotensi menaikkan tarif dan mengurangi kontrol publik.
Nasib dan Lanjutan IKN di Bawah Tekanan Fiskal
Asumsi: Pembangunan infrastruktur dasar (istana, jalan, jaringan listrik dan air) sudah 80% selesai. Beberapa gedung pemerintahan sudah berdiri namun kosong.
Biaya operasi untuk menjaga dan mengamankan aset-aset yang sudah terbangun (mencegah penjarahan, pemeliharaan rutin) mulai membebani APBN. Situasi IKN bahkan lebih pelik karena sifat proyeknya yang sangat bergantung anggaran pemerintah:
Stigma Kota Hantu dan Reputasi Politik
 Risiko terbesar adalah IKN menjelma menjadi "kota hantu" dengan bangunan megah tapi sepi. Baca ”Jangan jadikan IKN menjadi kota hantu.”
Risiko terbesar adalah IKN menjelma menjadi "kota hantu" dengan bangunan megah tapi sepi. Baca ”Jangan jadikan IKN menjadi kota hantu.”Biaya operasi untuk menjaga keamanan dan pemeliharaan kawasan yang luas dan fasilitas yang sudah terbangun namun tidak berpenghuni akan menjadi beban fiskal yang sia-sia dan sangat memalukan secara politik.
Pemerintah saat ini dan sebelumnya terpaksa memundurkan jadwal pemindahan secara massal atau hanya memindahkan sebagian kecil kementerian secara simbolis, atau dimulai dengan pindahnya Kantor Wakil Presiden saja (?)
Krisis Perumahan bagi PNS
Kebijakan perumahan bagi PNS yang akan pindah menjadi kacau. Jika anggaran perumahan pemerintah tersendat, PNS dihadapkan pada pilihan sulit: tinggal di fasilitas sementara yang tidak layak di IKN atau menolak untuk pindah.
Ini akan melumpuhkan tujuan utama proyek. Politik ekonominya bergeser dari menyediakan perumahan yang layak menjadi sekadar menyediakan "tempat berteduh".
Pelepasan Aset ke Swasta secara Darurat
Untuk menarik modal swasta yang sangat dibutuhkan, pemerintah akan menggoda investor dengan insentif yang sangat agresif, seperti hak pengelolaan (konsesi) yang sangat lama, keringanan pajak total, atau bahkan penjualan tanah di kawasan strategis dengan harga "fire sale."
Langkah ini bisa memicu kritik bahwa negara menyia-nyiakan aset bangsa untuk menyelamatkan proyek yang salah perencanaan.
Pembiayaan Operasional yang Menggerus Sektor Lain
Pemerintah akan berusaha mati-matian mencari celah anggaran untuk membiayai operasional dasar IKN. Ini berpotensi menggerus anggaran belanja untuk sektor-sektor vital lain di daerah-daerah existing.
Dana alokasi umum (DAU) untuk kabupaten/kota lain bisa dikurangi, atau proyek infrastruktur di tempat lain dihentikan. Ini akan menciptakan ketimpangan baru dan gejolak sosial politik.
Titik Temu: Pilihan Pahit dalam Politik Ekonomi
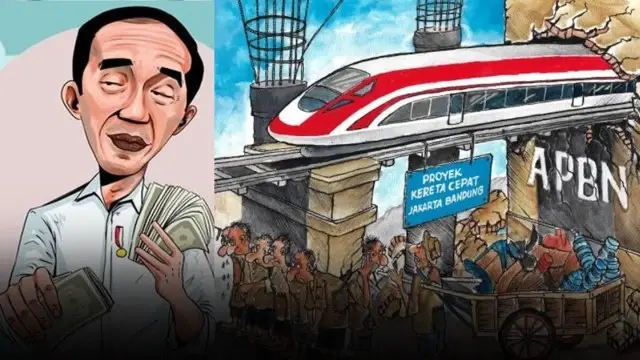
Dalam kondisi fiskal ketat, politik ekonomi perumahan dan transportasi tidak lagi tentang menciptakan yang ideal, tetapi tentang memilih prioritas yang paling tidak buruk.
Untuk Kereta Cepat, pilihannya adalah antara menaikkan tarif (melukai rakyat), menambah utang (melukai kedaulatan fiskal), atau mengorbankan integrasi (melukai efisiensi proyek).
Untuk IKN, pilihannya adalah antara memaksakan pemindahan dengan kondisi seadanya (melukai birokrat dan pelayanan publik), menjual aset ke swasta (melukai aset jangka panjang negara), atau mengakui kegagalan dan menunda indefinitely (melukai reputasi politik).
Skenario hambatan fiskal ini menyoroti kelemahan mendasar dalam politik ekonomi proyek-proyek mega: kurangnya perencanaan pendanaan jangka panjang untuk fase operasional.
Sebuah proyek dinyatakan "selesai" ketika fisiknya berdiri, padahal justru pada fase operasilah biaya yang sebenarnya berjalan.
Kedua kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah proyek tak diukur pada saat pencanangan atau groundbreaking, tetapi pada kemampuannya untuk beroperasi secara berkelanjutan secara finansial dan fungsional puluhan tahun ke depan.
Politik ekonomi yang bertanggung jawab harus memprioritaskan kelayakan operasional (operational feasibility) di atas legacy dan ambisi pembangunan fisik.
Baca Juga: Crossfire Pembangunan Indonesia: Salah Arah, Modal Habis
Khusus kereta cepat niat dan goal setting mengapa kita ingin memiliki kereta cepat Jakarta-Surabaya harus terungkap lugas dan jelas, bukan sekedar “pride” dan “ingin punya.”
Mencuri teknologi, misalnya, baru merinci strategi yang jitu untuk mencapai itu!
Tanpa itu, proyek-proyek megah seperti Kereta Cepat dan IKN berisiko menjadi monumen yang indah dipandang, tetapi menjadi beban fiskal dan politik yang menyengsarakan bagi generasi yang akan datang..***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.