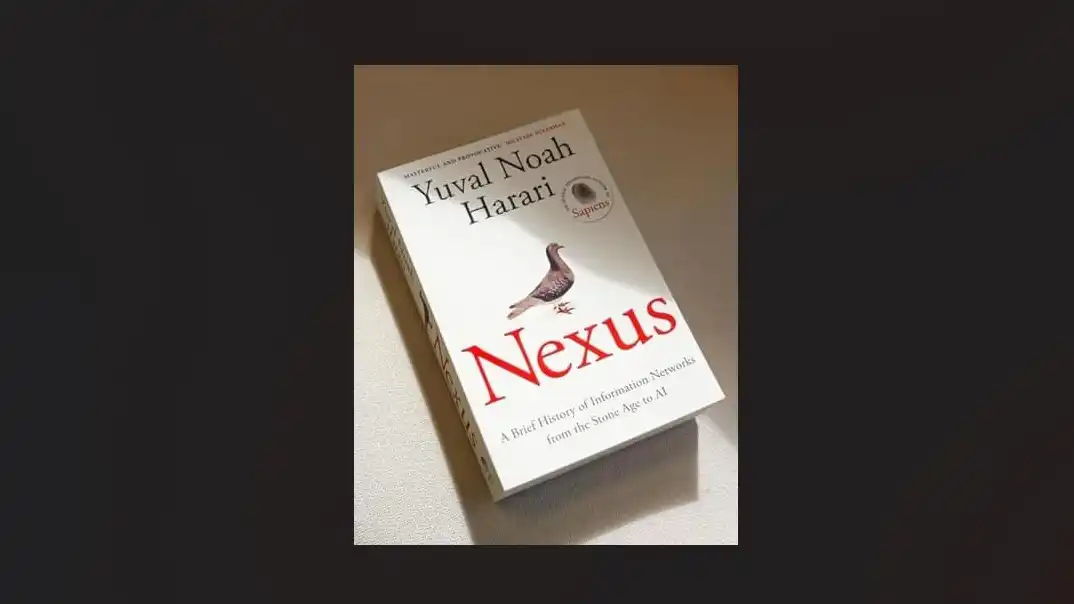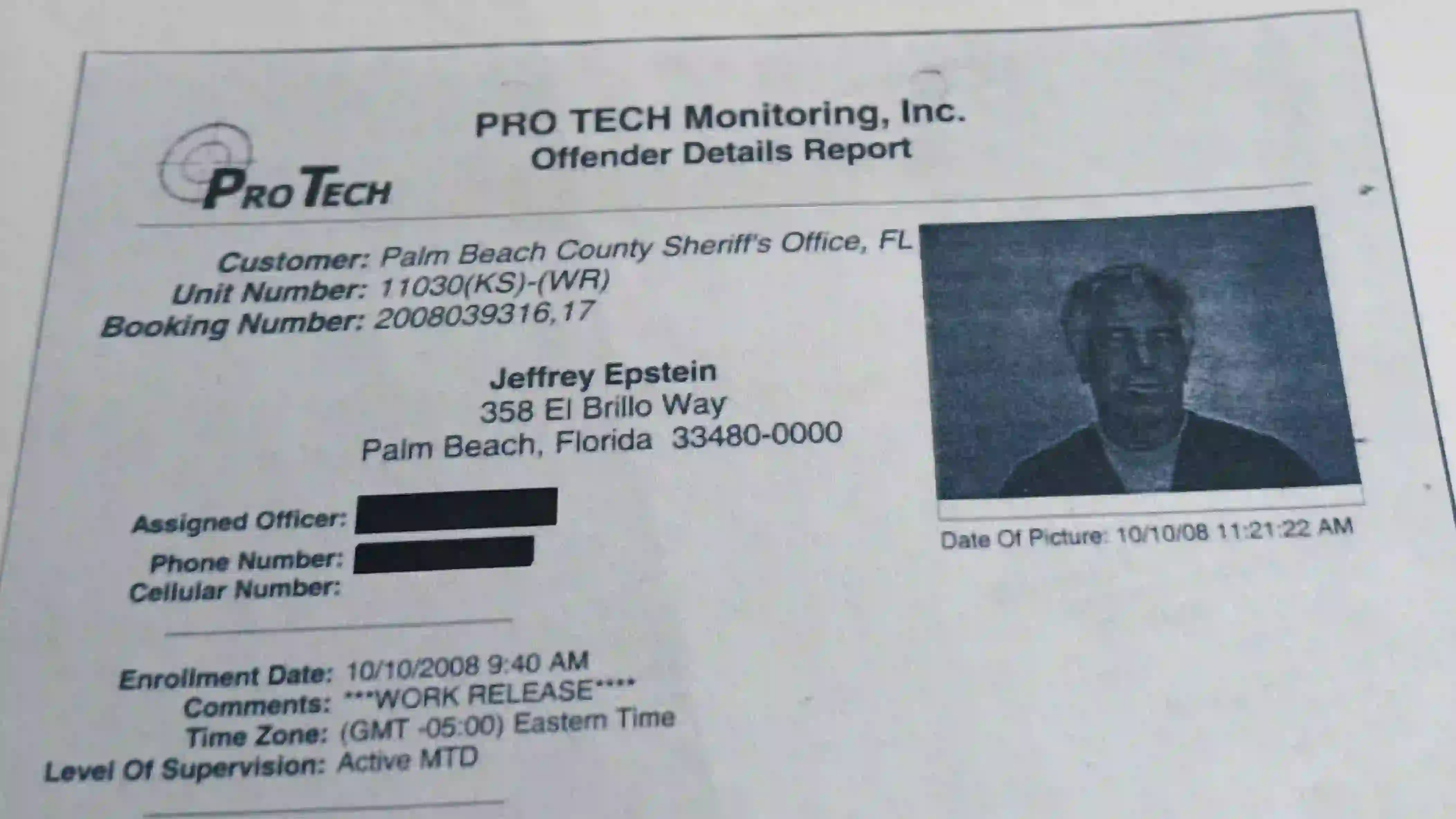Oleh Pipit Aprilia Rahapit, jurnalis yang fokus menekuni kebijakan publik, kini sedang menempuh studi pasca-sarjana Bidang Komunikasi Politik.
Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump bukan sekadar keputusan geopolitik, melainkan fenomena unik dari sudut pandang komunikasi politik kontemporer.
Dalam hitungan hari, kebijakan yang awalnya memicu resistensi berubah menjadi narasi tentang “kemaslahatan bersama” dan “misi perdamaian global.” Pergeseran yang terlalu cepat untuk disebut alamiah.
Keputusan Prabowo Subianto memasukkan Indonesia ke dalam BoP, sungguh bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan founding fathers Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan.
Prabowo menjauhkan sikap konsisten Indonesia sejak awal kemerdekaan, ketika pemerintah dan rakyat secara tegas menentang pembagian Palestina melalui Resolusi PBB tahun 1947 serta menolak segala bentuk penjajahan Israel.
Sikap ini berakar kuat pada prinsip anti-penjajahan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus menjadi landasan moral dan politik bagi dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Palestina serta solidaritas bersama negara-negara Arab.
Sejak 1947, Indonesia melalui Radio Republik Indonesia (RRI) telah menyuarakan penolakan atas pembagian wilayah Palestina dan menyatakan keberpihakan pada perjuangan bangsa Arab.
Solidaritas tersebut dipandang sebagai bagian dari perjuangan global melawan kolonialisme, sejalan dengan pengalaman historis Indonesia sendiri.
Pada tahun 1962, Presiden Soekarno menegaskan selama kemerdekaan Palestina belum terwujud, Indonesia akan tetap menentang penjajahan Israel, yang tercermin dari keputusan mengeluarkan Israel dari ajang Asian Games 1962 di Jakarta.
Merawat Konsistensi

Hingga kini, konsistensi politik luar negeri Indonesia tetap terlihat dalam dukungan terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka serta dalam sikap tidak mengakui kedaulatan Israel.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui diplomasi aktif di berbagai forum internasional dan pemberian bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Namun kini Indonesia malah masuk dalam BoP, bahkan Indonesia terkonfirmasi akan mencicil biaya masuk senilai total Rp17 triliun. Di titik inilah teori "Manufacturing Consent" dari Edward S. Herman dan Noam Chomsky menemukan relevansinya.
Dalam Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), mereka menjelaskan bahwa kontrol politik di demokrasi modern tak lagi bergantung pada represi terbuka, melainkan pada pengelolaan opini publik melalui “filter” informasi.
Persetujuan tidak selalu lahir dari deliberasi rasional, melainkan diproduksi melalui struktur komunikasi yang membentuk persepsi tentang apa yang masuk akal dan dapat diterima.
Keputusan bergabung dengan BoP memunculkan pertanyaan substantif: di mana proses deliberasi publik? Mengapa komitmen dibuat sebelum diskusi terbuka?
Namun alih-alih menjawab pertanyaan ini secara langsung, pemerintah menggelar pertemuan dengan pimpinan ormas Islam besar. Dalam kerangka Herman dan Chomsky, langkah ini dapat dibaca sebagai aktivasi filter legitimasi.
Ketika tokoh agama berbasis massa luas menyatakan kebijakan itu sejalan dengan “kemaslahatan umat,” muncullah tameng moral. Kritik terkait aspek geopolitik dan kedaulatan secara halus diposisikan sebagai "kurang peka terhadap nilai perdamaian."
Kooptasi Moral

Di sinilah terjadi kooptasi moral: bukan dengan membungkam kritik, tetapi dengan membungkus kebijakan dalam bahasa etika dan religiusitas yang sulit ditolak secara emosional.
Keesokan harinya, hadir para mantan menteri luar negeri dan diplomat senior. Dalam teori komunikasi politik, ini dapat dibaca sebagai symbolic alignment penyelarasan simbolik antara kebijakan politik dan figur-figur berotoritas.
Herman dan Chomsky menyebut peran ini sebagai bagian dari mekanisme legitimasi elit: menghadirkan pakar untuk menciptakan kesan bahwa kebijakan telah melalui proses rasional dan teknokratis.
Bahkan jika para tokoh tersebut tidak menyatakan dukungan eksplisit, kehadiran mereka sudah cukup untuk membangun persepsi publik tentang adanya konsensus elite.
Padahal, jika keterlibatan itu bersifat post-factum, maka yang terjadi bukan deliberasi, melainkan validasi setelah keputusan final dibuat.
Pernyataan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut hanyalah “agenda rutin” menunjukkan strategi yang dalam literatur komunikasi krisis disebut sebagai normalization strategy.
Dengan menurunkan kadar urgensi, pemerintah mengubah persepsi publik dari situasi krisis menjadi rutinitas administratif.
Ini sejalan dengan konsep agenda-setting dalam teori komunikasi: bukan mengatakan kepada publik apa yang harus dipikirkan, melainkan menentukan isu mana yang dianggap penting.
Ketika fokus publik digeser dari “mengapa kita bergabung?” ke “bagaimana kita memaksimalkan manfaatnya?”, maka medan perdebatan telah direstrukturisasi.
Tak Ada Sensor, Hanya Pengondisian Ruang Publik

Dalam perspektif Jürgen Habermas, legitimasi kebijakan publik seharusnya lahir dari public sphere yang memungkinkan diskursus rasional dan partisipatif.
Sementara itu, Robert A. Dahl dalam konsep polyarchy menekankan pentingnya partisipasi efektif dan kompetisi gagasan yang terbuka.
Namun dalam kasus BoP, deliberasi tampak terjadi setelah keputusan, bukan sebelumnya. Demokrasi secara prosedural tetap berjalan tidak ada sensor terbuka tetapi kualitas deliberatifnya menyempit.
Kritik tidak dibungkam; ia dikelilingi legitimasi simbolik hingga kehilangan daya dorongnya. Inilah paradoks demokrasi modern: kebebasan tetap ada, tetapi makna ruang publik dikelola.
Di era digital, proses manufacturing consent bekerja lebih cepat. Algoritma media sosial memperkuat narasi yang didukung figur otoritatif.
Visual pertemuan elite, kutipan religius, dan bahasa diplomatik yang menenangkan membentuk persepsi stabilitas. Persetujuan terbentuk melalui repetisi dan simbol, bukan melalui pemahaman mendalam atas konsekuensi geopolitik.
Apa yang terjadi bukanlah pembungkaman, melainkan saturasi simbolik. Apakah BoP secara strategis menguntungkan Indonesia? Itu debat yang sah. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pola komunikasinya.
Baca Juga: Dilema "Antek Asing": Kedaulatan Nasional atau Jualan Politik Pragmatis?
Jika dalam 48 jam resistensi dapat berubah menjadi permakluman melalui orkestrasi legitimasi moral, teknokratis, dan simbolik, maka kita perlu mengakui bahwa teori Herman dan Chomsky bukan sekadar kritik terhadap media Barat tahun 1980-an.
Ia hidup dalam praktik politik hari ini.
Demokrasi tidak runtuh dengan suara keras. Ia dapat melemah secara sunyi ketika publik merasa telah setuju, tanpa pernah benar-benar diajak mempertanyakan.
Selain itu mungkin di situlah letak persoalan terbesarnya: bukan pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada cara persetujuan terhadapnya diproduksi.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.