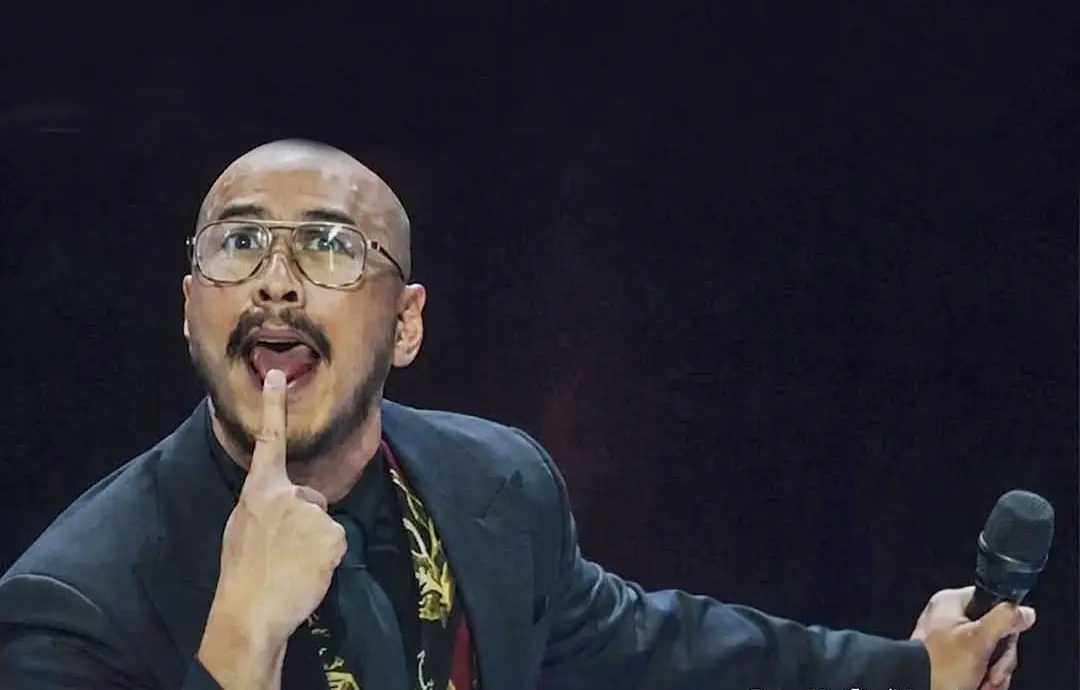Jakarta, TheStance – Era digital melahirkan paradoks sosial yang mengkhawatirkan. Di tengah upaya pemerintah menekan angka perkawinan anak, media sosial justru menjadi panggung bagi narasi yang mengglorifikasi pernikahan usia dini.
Tanpa ijazah, keterampilan yang kurang memadai, dan dibayangi risiko stunting, pelaku pernikahan dini menjadi bagian dari persoalan di tengah tingginya angka pengangguran dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah.
Berdasarkan data United Nations Children’s Fund, atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara keseluruhan di dunia ada 650 juta anak yang menjadi korban pernikahan dini. Di Indonesia, angkanya mencapai 25,5 juta anak.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, provinsi dengan anak yang mengalami pernikahan dini terbanyak adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 14,96%, disusul Papua Selatan (14,4%), Sulawesi Barat (10,71%), dan Kalimantan Barat (10,05%).
Namun demikian, secara secara rata-rata angka pernikahan dini (di bawah usia 18 tahun) telah menyentuh titik terendah di Indonesia pada angka 5,9% di tahun 2024. Ironisnya, sebuah video pernikahan dini di Lombok Tengah mendadak viral.
Unit Pusat Perlindungan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Tengah memanggil mereka, sepasang remaja SMY (14 tahun) dan SR (17 tahun), untuk dimintai keterangan. Rupanya, mempelai perempuan masih berstatus siswi SMP.
Mereka tak memahami risiko pernikahan dini mulai dari ancaman kesehatan seperti stunting anak dan risiko kematian saat melahirkan, hingga masalah sosial seperti perceraian akibat ketidaksiapan mental.
Batas Minimal Usia Menikah

Secara hukum, Indonesia mewajibkan batas usia minimal 19 tahun untuk kedua calon mempelai melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menyebutkan perlunya segera memangkas angka kasus pernikahan dini demi merealisasikan keadilan sosial yang lebih merata di tanah air.
"Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan harus mampu direalisasikan untuk memangkas kesenjangan jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi saat ini," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini, Selasa (27/1/2026).
Tingginya angka pernikahan dini di sejumlah daerah, khususnya Indonesia Timur, dipicu permasalahan kompleks meliputi faktor budaya, geografis, dan ekonomi.
Laporan UNICEF dalam Child Marriage and Education: Data Brief menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor protektif paling kuat terhadap pernikahan anak.
Anak perempuan yang tetap bersekolah di tingkat menengah memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk menikah dini jika dibandingkan dengan mereka yang putus sekolah.
Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, catatan UNICEF itu harus menjadi dasar bertindak dalam upaya memangkas pernikahan dini.
Dia berharap prestasi turunnya rerata angka pernikahan dini pada 2024 dapat terus diperkuat dengan penerapan kebijakan konsisten dan didukung pihak-pihak terkait.
Perlu Nalar Kritis

Dosen Psikologi Universitas Brawijaya (UB) Naila Kamaliya menilai generasi muda akan terjebak dalam delusi yang merugikan masa depan mereka jika tidak menggunakan nalar kritis.
Angka pernikahan dini tahun 2024 memang turun signifikan, dari 1.577.255 pada tahun 2023 menjadi 1.478.302. Namun, Naila menyoroti adanya kesenjangan antara data lapangan dengan persepsi publik yang dibentuk oleh algoritma media sosial.
Munculnya konten-konten digital yang membungkus pernikahan dini dengan estetika romantisme dinilai sebagai sebuah distorsi. Narasi ini sering kali mengaburkan tanggung jawab besar di balik sebuah ikatan legal.
“Fenomena saat ini bukan sekadar peningkatan jumlah pernikahan, melainkan bagaimana pernikahan dini dipromosikan seolah-olah menjadi solusi bagi berbagai masalah hidup,” ujar Naila, dari laman resmi Universitas Brawijaya (UB).
Menurut dia, kampanye usia minimum pernikahan yang digalakkan Badan Koordinas Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pemerintah bukan sekadar aturan administratif, melainkan perlindungan terhadap kesejahteraan mental.
Di beberapa wilayah, kebijakan konseling psikologis pranikah bagi calon pengantin di bawah umur kini menjadi instrumen krusial untuk menguji kesiapan sosial dan mental mereka berumah tangga.
Pasalnya, pernikahan dini bukan sekadar "pindah rumah", melainkan pertaruhan terhadap kualitas hidup jangka panjang. Naila menggarisbawahi tiga risiko sistemik jika pernikahan dipaksakan tanpa kesiapan matang, yaitu:
Ketidakstabilan Domestik: Lonjakan angka perceraian akibat ketidakmampuan resolusi konflik.
Defisit Pengasuhan: Ketidaksiapan pola asuh (parenting) yang berdampak pada tumbuh kembang anak.
Krisis Kesejahteraan: Penurunan kualitas psikologis keluarga secara menyeluruh.
Baca Juga: Ancaman Child Grooming dan Lemahnya Sistem Perlindungan Anak
Isu lain yang tidak kalah berbahaya adalah penyebaran pandangan sinis terhadap bangku perkuliahan. Narasi "kuliah tidak menjamin sukses" sering disalahartikan sebagai "kuliah tidak penting".
Naila menilai klaim tersebut berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan akibat rendahnya motivasi belajar. Padahal, nilai sebuah gelar bukan sekadar soal prospek gaji, melainkan pembentukan struktur berpikir.
Perguruan tinggi adalah kawah candradimuka untuk mengasah ketajaman kognitif, terutama kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi.
Lalu, kecerdasan interpersonal, sebagai keterampilan sosial dalam ekosistem yang beragam. Serta perlunya mengasah resiliensi, yakni kesiapan individu dalam menghadapi ketidakpastian tantangan global.
“Pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan memutus rantai kemiskinan,” tegas Naila.
Akademisi psikologi ini mengajak kaum muda untuk membedah kembali prioritas hidup mereka. Ia menekankan bahwa kedewasaan seseorang diuji dari caranya mengambil keputusan, bukan dari seberapa cepat mereka mengikuti tren viral.
“Menikah adalah pilihan, kuliah juga pilihan, tetapi belajar adalah keharusan. Setiap keputusan perlu disertai refleksi diri, kesiapan mental, dan dukungan keluarga,” pungkasnya.
Naila menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi jangkar utama. Tanpa fondasi pendidikan dan kesehatan mental yang kokoh, masa depan yang sehat secara sosial hanyalah sebuah angan-angan di tengah riuhnya arus informasi digital. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance