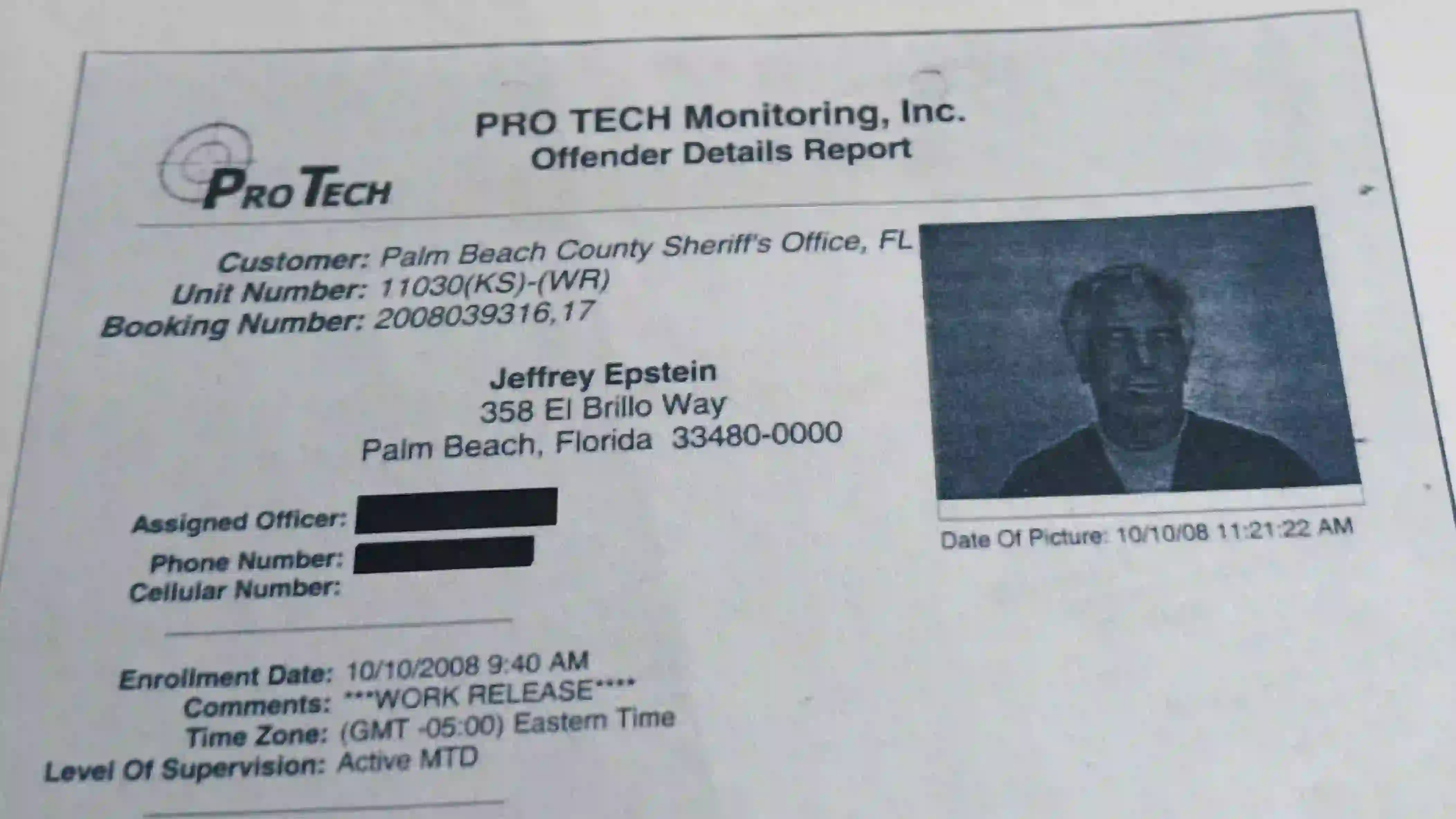Oleh Edwin Partogi Pasaribu, aktivis Kontras yang menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 dan Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024. Pernah bergabung di Tim Investigasi lapangan Penembakan Intan Jaya (2002) dan viral setelah berperan penting menjaga saksi kunci kasus Fredy Sambo, dia kini aktif menjadi praktisi hukum di Public Virtue Research Institute dan Dewan Pakar TheStance.
Bila Bung Tomo dalam Pertempuran Surabaya 1945 menyerukan perjuangan hingga titik darah penghabisan, tentu semua orang mafhum karena situasi saat itu membutuhkan pengorbanan dan semangat juang rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.
Namun, bila ucapan serupa disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo tentu hal itu terasa janggal. Berjuang untuk apa? Atas ancaman keamanan apa? Darah siapa yang akan dihabisi?
Di sisi lain, jangan sampai slogan itu terasa hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Yang mengkhawatirkan adalah bila retorika heroik itu malah berpotensi menjauhkan Polri dari mandat konstitusionalnya.
Pernyataan Kapolri itu terucap pada rapat kerja dengan Komisi III DPR (27/1), sebagai respons atas wacana menempatkan Polri di bawah kementerian khusus.
Menurutnya menempatkan Polri di bawah Kementerian akan melemahkan Polri, negara dan presiden. Bahkan, Listyo menyampaikan bila ditunjuk sebagai Menteri Kepolisian, ia memilih lebih baik jadi petani saja.
Ada apa juga dengan profesi petani? Pernyataan ini terkesan merendahkan profesi petani dengan menjadikannya simbol “kemunduran/hukuman.” Padahal, petani adalah profesi terhormat yang menopang kedaulatan pangan.
Pada bagian penutup dari penjelasannya di DPR tersebut, Listyo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperjuangkan posisi Polri langsung di bawah Presiden, sampai titik darah penghabisan.
Namun, bukan hanya pernyataan Kapolri yang terasa janggal, tepuk tangan dan sorak dari pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengapresiasi sikap Kapolri itu juga terasa ganjil.
Seharusnya DPR mengkritisi retorika ekstrem aparat keamanan, bukan malah melegitimasi slogan konfrontatif tersebut. Hal ini malah menunjukkan sistem pengawasan yang lemah ketika berhadapan dengan institusi koersif negara.
Posisi Polri dalam Negara

Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
Maknanya, Polri adalah alat negara bukan alat kekuasaan. Fungsi Polri adalah pelayanan publik dan penegakan hukum, bukan fungsi politik.
Secara eksplisit konstitusi tidak menentukan secara rigid posisi struktural Polri di bawah presiden atau kementerian. Konstitusi hanya berfokus pada fungsi dan prinsip kerja Polri, tidak pada desain kelembagaan secara detail.
Meski Ketetapan MPR VI/2000 (TAP) menyatakan Polri di bawah Presiden, harus dipahami bahwa TAP ini lahir dalam konteks transisi reformasi untuk memisahkan Polri dari TNI, mengakhiri dwifungsi ABRI dan menegaskan Polri sebagai kekuatan sipil.
TAP tersebut bersifat transisional dan korektif, bukan konstitusi mini yang menetapkan desain kelembagaan permanen.
Dalam konteks demokrasi dan hukum tata negara, kepolisian berada di bawah kendali otoritas sipil yang demokratis (civilian control). Artinya akuntabilitas kepada otoritas sipil, bukan kepada dirinya sendiri.
Pengawasan politik dan administratif, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun organisasi masyarakat sipil independen. Dan larangan otonomi institusional absolut, karena berpotensi melahirkan state within the state.
Terlepas dari gagasan Polri berada di bawah Kementerian layak diperdebatkan, yang harus disadari adalah: Polri tak boleh anti perubahan. Polri tak boleh lupa pemisahan dari ABRI pada 1 April 1999 merupakan proses sejarah, buah dari gerakan reformasi.
Posisi Struktural Polri dan Profesionalisme

Bila saat ini ada tuntutan reformasi Polri, hal ini tak lepas karena polisi merupakan cerminan tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, ketertiban dan ketenteraman, yang mendukung produktivitas yang menyejahterakan warganya.
Wacana penempatan Polri tetap di bawah Presiden atau di bawah Kementerian, merupakan pilihan kebijakan tata kelola pemerintahan (public administration), bukan persoalan eksistensi konstitusional.
Konstitusi tidak melarang Polri berada di bawah Kementerian. Banyak negara demokrasi yang mapan memilih menempatkan kepolisian di bawah kementerian, tanpa mengurangi profesionalisme mereka.
Harus dipahami, ancaman terhadap Polri selama ini bukan dari perubahan struktur, melainkan dari politisasi kewenangan, lemahnya akuntabilitas, dan tumpang tindih fungsi sipil–militer, serta penempatan anggota Polri di luar organisasi kepolisian.
Oleh karenanya, menyamakan penataan kelembagaan dengan “pelemahan” atau “penghancuran” Polri adalah argumen emosional, bukan konstitusional.
Dalam konteks negara hukum, prioritas utama kepolisian adalah profesionalisme, bukan posisi struktural dalam kolom pemerintahan.
Profesionalisme Polri diukur dari independensi operasional dalam penegakan hukum, kepatuhan pada hak azasi manusia (HAM) dan due process of law, netralitas politik, akuntabilitas dan transparansi publik.
Sebab, struktur kelembagaan hanya alat (means), bukan tujuan (end). Jika Polri profesional, akuntabel, tunduk pada hukum, maka di bawah presiden atau kementerian sipil tidak mengubah esensi fungsinya.
Sebaliknya, bersikeras posisi struktural tanpa pembenahan profesionalisme dapat berisiko memperkuat budaya impunitas, memperlebar jarak dengan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik.
Perjuangan hingga Titik Darah Penghabisan

Retorika “perjuangan sampai titik darah penghabisan” jangan sampai menciptakan dikotomi kami vs mereka. Hal ini malah mengesankan sikap konfrontatif terhadap kritik, dan agenda perubahan.
Selain itu, retorika tersebut seolah menjadi pembenar penggunaan kekuatan berlebih. Plus, mengaburkan akuntabilitas.
Mari flashback ketika Kapolri Bimantoro melakukan perlawanan karna diganti Chaeruddin Ismail oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001.
Bimantoro menolak pencopotan itu dengan dalih tak sesuai dengan Ketetapan MPR VI/2000 (18 Agustus 2000), yang mensyaratkan pengangkatan Kapolri harus mendapat persetujuan DPR.
Padahal sebelumnya, Jenderal Polisi Rusdihardjo, juga dicopot pada 23 September 2000 dan langsung digantikan Komjen Bimantoro tanpa melalui proses di DPR.
Tindakan Bimantoro ini tidak dapat dibenarkan karena Kapolri adalah bawahan Presiden secara administratif dan politik. Tidak adanya persetujuan DPR tidak mengubah Kapolri menjadi pejabat independen.
Perlawanan ini mencederai civilian control dan menciptakan preseden buruk institusi koersif melawan otoritas sipil.
Sekalipun contoh di atas tidak apple to apple pada konteks ini, namun pada prinsipnya Kapolri tidak boleh mengeklaim legitimasi politik sendiri dan merasa sebagai lembaga independen.
Polri Hendak Berkorban untuk Siapa?

Bila slogan retorik “sampai titik darah penghabisan” ini dimaknai sebagai bentuk pengorbanan aparat negara, lalu itu pengorbanan untuk siapa?
Bukankah tugas Polri melindungi dan mengayomi rakyat? Bukan untuk mempertahankan kewenangan, jabatan, atau otonomi institusional.
Tidak ada institusi negara yang dibenarkan menumpahkan “darah” simbolik maupun nyata untuk kepentingannya sendiri, apalagi dengan mengorbankan prinsip demokrasi dan negara hukum.
Perjuangan Polri harus difokuskan dalam menjaga integritas profesi.
Perjuangan itu dapat tercermin dari sikap yang tak alergi terhadap kritik publik, kesediaan tunduk pada pengawasan, serta patuh pada hukum dan menghormati hak asasi manusia, bahkan ketika hal itu membatasi kewenangan internal sendiri.
Perjuangan hingga titik darah penghabisan bagi Polri harus dimaknai sebagai puncak pengabdian etis, melindungi warga tanpa diskriminasi, menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih, serta secara sadar menjauhi politisasi kekuasaan.
Harapannya, Polri tetap menjadi penjaga hukum, bukan alat kekuasaan.
Baca Juga: Polemik "Dwifungsi Polisi" & Putusan MK (1): Polisi Tak Sepenuhnya Salah
Kita tentu berharap Polri tidak melakukan perlawanan terhadap tuntutan perubahan. Sebagaimana kita menaruh harapan bahwa Polri memiliki kedewasaan melakukan pembenahan, koreksi, dan pengawasan.
Keteguhan profesional justru tampak ketika Polri mampu menahan diri dari godaan retorika kekuasaan dan memilih setia pada hukum, etika, serta kepentingan publik.
Dalam negara demokratis, perjuangan sejati aparat bukan melawan rakyat, melainkan berdiri bersama rakyat, bahkan ketika pilihan itu menuntut pengorbanan tertinggi demi keadilan dan kemanusiaan.
Sebab kita percaya, polisi yang manusiawi—berpikir, berempati, dan bertanggung jawab—jauh lebih berharga bagi demokrasi daripada aparat yang patuh secara mekanis, kaku, dan kehilangan nurani layaknya robocop.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance