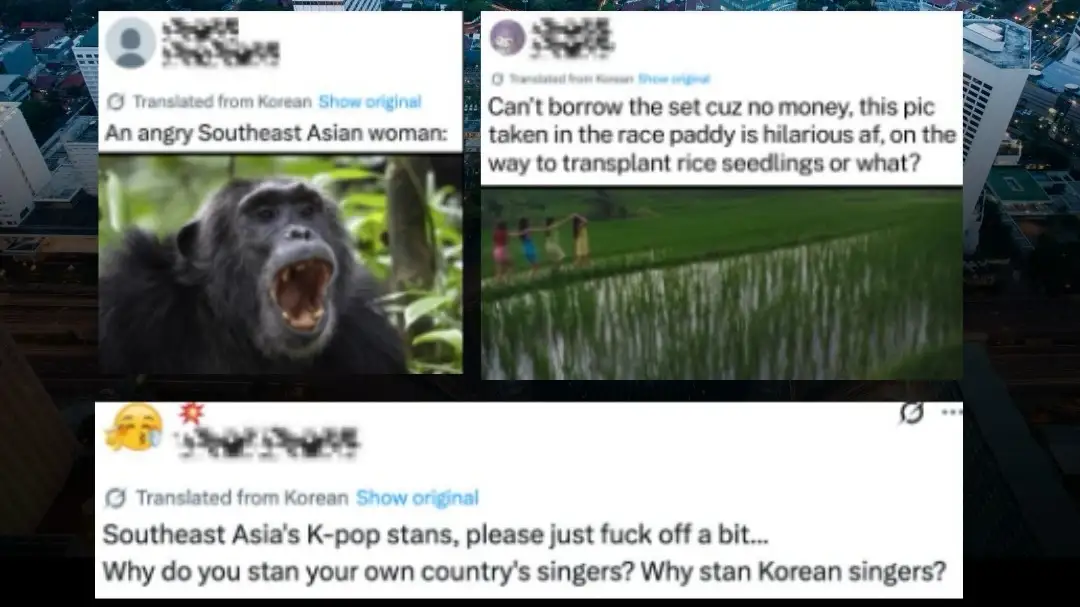Oleh Pius Lustrilanang: aktivis yang terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra, memperoleh gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jenderal Soedirman dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.
Perdebatan mengenai kemungkinan pengembalian Pilkada ke mekanisme tidak langsung melalui DPRD kembali mencuat dan segera memantik reaksi publik.
Isu ini bukan sekadar soal prosedur elektoral, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana relasi antara partisipasi warga dan kewenangan negara dipahami, dirumuskan, dan dijalankan dalam praktik demokrasi Indonesia kontemporer.
Pada Rabu, 7 Januari 2026, LSI Denny JA merilis hasil survei nasional yang langsung menjadi rujukan utama perdebatan. Angkanya tegas: 66,1% responden menyatakan tidak setuju jika Pilkada dilakukan melalui DPRD.
Hanya 28,6% yang menyatakan setuju, sementara sisanya tidak menjawab. Penolakan ini muncul hampir di semua segmen sosial, dengan intensitas paling tinggi di kalangan generasi muda.
Rincian generasi memperlihatkan sinyal politik yang tidak bisa diabaikan. Sebanyak 84% Gen Z menolak, disusul 71,4% generasi milenial, 60% Gen X, dan 63% generasi baby boomer.
Artinya, ini bukan penolakan sektoral atau emosional sesaat, melainkan kecenderungan lintas usia—dengan tekanan terkuat datang dari generasi yang akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia ke depan.
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multi-stage random sampling, margin of error ±2,9%, dan pengumpulan data pada Oktober 2025.
Bukan Opini Spontan

Secara metodologis, temuan ini layak dibaca sebagai potret sikap publik yang relatif stabil, bukan sekadar opini spontan atau respons sesaat terhadap wacana politik jangka pendek.
Namun alih-alih dibaca sebagai peringatan dini, hasil survei justru memicu respons defensif dari sebagian elite.
Survei dianggap mengganggu kewenangan, disalahpahami sebagai tekanan politik, atau dikesampingkan karena dianggap tidak menentukan arah kebijakan.
Di sinilah persoalan sesungguhnya muncul: bukan pada angka surveinya, melainkan pada cara kekuasaan memahami, memaknai, dan merespons konsep legitimasi itu sendiri.
Dalam praktik politik, kerap muncul keyakinan bahwa selama kebijakan sah secara hukum, maka persoalan selesai.
Undang-undang disahkan, prosedur dijalankan, lembaga bekerja. Inilah yang dapat disebut sebagai ilusi legitimasi formal—anggapan bahwa legalitas semata sudah cukup untuk menopang kekuasaan dan memastikan kepatuhan warga negara.
Padahal, sejak Max Weber menulis Economy and Society (1922), ilmu politik telah membedakan secara tegas antara kekuasaan yang sah dan kekuasaan yang diterima.
Kekuasaan tidak hanya ditaati karena aturan, tetapi karena diyakini layak ditaati. Kepatuhan sosial lahir dari kepercayaan, pengakuan, dan rasa keadilan, bukan semata dari prosedur administratif yang bersifat formal.
Penguasa dalam Ilusi Legitimasi
 Ilusi legitimasi formal muncul ketika penguasa merasa tidak lagi perlu mendengar suara publik karena kewenangan sudah aman secara konstitusional.
Ilusi legitimasi formal muncul ketika penguasa merasa tidak lagi perlu mendengar suara publik karena kewenangan sudah aman secara konstitusional.
Kritik dipandang sebagai gangguan stabilitas, penolakan dianggap ketidaktahuan, dan survei dibaca sebagai ancaman politik.
Padahal, angka 66,1% penolakan bukan berarti publik sedang memveto konstitusi. Ia menunjukkan adanya jarak emosional dan moral antara kebijakan negara dan pengalaman warga sehari-hari yang mulai melebar.
Ketika jarak ini diabaikan, negara memang tetap bisa memerintah.
Namun kemampuannya untuk memimpin—mengajak, meyakinkan, dan memperoleh persetujuan batin—perlahan terkikis. Kekuasaan menjadi sah, tetapi kehilangan kehangatan politik, daya persuasi, dan legitimasi substantif di mata publik.
Kesalahan umum elite adalah membaca survei seolah publik sedang menilai kebijakan secara teknis dan rinci.
Padahal, survei opini publik lebih sering menangkap rasa keadilan, pengalaman historis, dan makna simbolik yang melekat pada sebuah kebijakan.
Sejak Gabriel Almond dan Sidney Verba memperkenalkan konsep civic culture (1963), kita tahu bahwa sikap politik warga dibentuk oleh pengalaman kolektif dan memori sosial, bukan semata oleh argumentasi administratif negara.
Suara Warga Kian Jauh dari Kekuasaan
 Dalam konteks ini, frasa “Pilkada lewat DPRD” membawa beban makna yang kuat: jarak antara rakyat dan pengambil keputusan, dominasi elite politik, serta ingatan masa lalu ketika suara warga terasa jauh dari ruang kekuasaan.
Dalam konteks ini, frasa “Pilkada lewat DPRD” membawa beban makna yang kuat: jarak antara rakyat dan pengambil keputusan, dominasi elite politik, serta ingatan masa lalu ketika suara warga terasa jauh dari ruang kekuasaan.
Penolakan publik bukanlah ekspresi ketidaktahuan teknis, melainkan reaksi normatif terhadap simbol kekuasaan dan arah relasi negara–warga.
Fakta bahwa penolakan paling tinggi datang dari Gen Z memberi sinyal penting. Generasi ini tumbuh dengan pengalaman partisipasi digital yang intens dan terbuka.
Bagi mereka, didengar bukan bonus, melainkan hak dasar. Ketika arah kebijakan dibaca sebagai penyempitan ruang itu, resistensi muncul secara spontan dan relatif seragam.
Dalam Between Facts and Norms (1992), Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi lahir ketika keputusan institusional bertemu penerimaan publik melalui komunikasi yang masuk akal.
Ketika komunikasi gagal, legitimasi menyusut—meskipun prosedur tetap sah. Di sinilah survei berfungsi sebagai alat ukur awal daya tahan legitimasi politik dan kualitas relasi antara negara dan warga.
Baca Juga: Penolakan Gen Z atas Pilkada DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi
Survei tidak pernah menjatuhkan kekuasaan. Yang sering melemahkan kekuasaan justru keyakinan bahwa prosedur sudah cukup sehingga suara publik tak lagi perlu didengar.
Survei LSI seharusnya dibaca sebagai cermin: apakah arah kebijakan masih dipahami sebagai jalan bersama, atau justru dirasakan sebagai kemunduran partisipasi.
Kekuasaan yang matang tidak alergi pada cermin—ia berani bercermin sebelum jarak dengan masyarakat menjadi terlalu jauh dan sulit dijembatani.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.