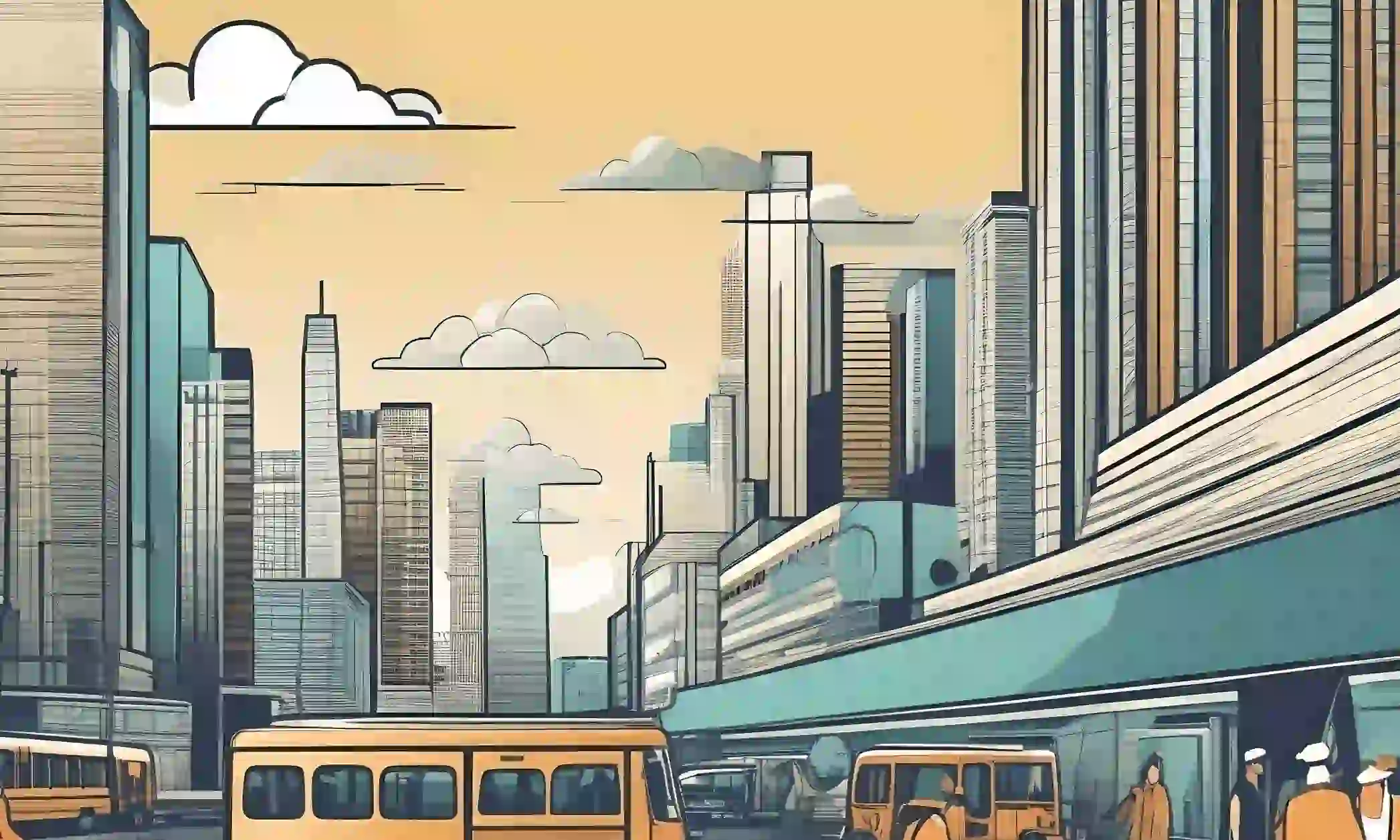Oleh GWS, lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang pernah didapuk menjadi direktur utama sebuah BUMN dan kini memimpin sebuah perusahaan teknologi. Aktif menuangkan tulisan dan pemikirannya tentang isu keindonesiaan, kebangsaan, dan kemajuan negara, meski dengan nama samaran.
Coba, bayangkan sebentar: Anda adalah Si Kabayan yang baru saja bilang ke Iteung, "Cing, jual sawah kita. Abdi hoyong ka China, rék ningali kumaha aranjeunna robah nagara tani jadi pabrik dunia."
Iteung melongo. "Sawah warisan ti buyut? Rék dijual keur naon?"
Kabayan menunjukkan artikel tentang "Economic Complexity Index China" yang naik ke peringkat 21 global dengan skor 1.16. "Eta, aranjeunna ti nagara tani kawas urang, ayeuna jadi eksportir sagala rupa. Urang kudu diajar."
Iteung menggeleng kepala. Dalam hatinya bergumam:
"Geus jadi naon si Kabayan ieu? Hayang jual sawah pikeun nempo pabrik? Teu ka wareg ku ningali pabrik Korea jeung Vietnam teh?" (Sudah jadi apa si Kabayan ini? Mau jual sawah untuk lihat pabrik? Tidak puas lihat pabrik Korea dan Vietnam?)
Tapi Kabayan bersikeras. Di ujung amplop undangan tertulis:
"Datanglah melihat bagaimana kami mengubah 1,4 miliar orang dari petani miskin menjadi pekerja pabrik yang memproduksi US$3,7 triliun nilai tambah manufaktur—lebih besar dari gabungan AS, Korea Selatan, Jerman, dan Inggris."
Di pesawat menuju Beijing, Kabayan merenung sambil manyun di ketinggian 35.000 kaki. "Ironis," pikirnya, "urang jual sawah untuk belajar dari negara yang dulu sama-sama petani. Sekarang mereka bikin pesawat, kita masih nanam padi."
Tahun 1980, China masih produksi baja 36 juta ton dengan teknologi primitif. Sekarang? Mereka produser baja terbesar dunia, menyumbang 86% peningkatan produksi baja global.
Yang lebih nyesek: industri kimia China sekarang bernilai US$1,5 triliun—hampir 40% dari pendapatan industri kimia global. Research & Development (R&D) mereka di sektor kimia naik dari 22% total global (2012) jadi 34% (2022).
Sementara kita? Masih impor pupuk untuk sawah yang baru aja dijual Kabayan.
Deng Xiaoping dan Sihir "Reform and Opening"

Sesampainya di Beijing, Kabayan diajak ke Museum Reformasi & Keterbukaan yang didedikasikan untuk Deng Xiaoping. Guide-nya, Profesor Yuan, ekonom lulusan Harvard yang belajar langsung teori Hausmann, mulai bercerita tentang transformasi 1978.
"Deng Xiaoping itu seperti Kabayan yang tiba-tiba sadar kalau tidur di sawah tidak akan mengubah sawah jadi pabrik," ujar sang profesor dengan senyum simpul.
Tahun 1979, China menghadapi "ketidakseimbangan serius" dalam proporsi ekonomi: pertanian vs industri, industri ringan vs berat, bahan baku vs energi. Tapi mereka tidak ngeyel dengan ideologi.
Mereka ngomong sederhana: 实事求是 (shì shì qiú shì)—cari kebenaran dari fakta. Konferensi Kerja Pusat April 1979 mengajukan 12 prinsip untuk menyesuaikan hubungan proporsional ekonomi.
Bukan seminar yang menghasilkan MoU kosong, tapi roadmap konkret: tingkatkan pertanian, kembangkan industri tekstil dan ringan, perkuat produksi batu bara, listrik, minyak, transportasi, dan bahan bangunan.
Practical banget, tidak seperti rapat-rapat kita yang menghasilkan buzzword dan jargon.
Yang bikin Kabayan merinding adalah strategi "Made in China 2025" yang diluncurkan Perdana Menteri Li Keqiang tahun 2015.
Bukan cuma slogan, tapi rencana terukur: tingkatkan konten domestik dari bahan inti jadi 40% pada 2020 dan 70% pada 2025. Target yang ngeri-ngeri sedap—ambisi tinggi tapi realistis.
"Bandingkan dengan Indonesia Emas 2045," kata si profesor sambil nyengir. "Mereka punya target spesifik dengan timeline jelas. Kita punya mimpi besar tanpa roadmap konkret."
Transformasi Sektoral yang Bikin Nyali Ciut
 China tidak bicara tentang "potensi besar" atau "negara maritim terbesar." Mereka bicara tentang "konten domestik 70%" dan "nilai tambah manufaktur $3,7 triliun."
China tidak bicara tentang "potensi besar" atau "negara maritim terbesar." Mereka bicara tentang "konten domestik 70%" dan "nilai tambah manufaktur $3,7 triliun."
Kabayan ngakak getir: "Kita punya visi 2045 yang abstrak, mereka punya visi 2025 yang konkret. Kita planning 20 tahun ke depan, mereka execution plan untuk 10 tahun."
Profesor itu kemudian menjelaskan evolusi product space China yang mind-blowing. Dari manufaktur tekstil sederhana tahun 1980-an, mereka secara sistematis bergerak ke produk-produk kompleks: elektronik, mesin, teknologi tinggi.
Seperti monkey jumping dalam teori Hausmann—dari pohon ke pohon dalam product space forest.
Era Primitif (1980): China produksi 36 juta ton baja dengan teknologi ngawur—konsumsi air 35,9 m³ per ton (sekarang standar dunia cuma 3-4 m³), efisiensi daur ulang air cuma 61,2%.
"Waktu itu mereka seperti tukang pandai besi tradisional yang tiba-tiba diminta bikin pesawat," kata si profesor.
Era Transformasi (1990-2010): Melalui program ambisius, China mengimpor teknologi dari Jepang dan Eropa, tapi tidak cuma copy-paste. Mereka modifikasi dan improvisasi.
Hasilnya: produksi melonjak dari 100 juta ton (1996) jadi 570 juta ton (2009)—bahkan saat krisis finansial global!
Era Dominasi (2010-sekarang): China sekarang menyumbang 86% peningkatan produksi baja dunia dan menguasai 70% konsumsi global.
Yang ngeri: mereka tidak cuma jadi produsen terbesar, tapi juga pengekspor teknologi. Perusahaan baja Eropa yang dulu mengajari China sekarang beli teknologi dari China.
Kabayan menggaruk kepala: "Kita kapan ya jadi murid yang baik?"
Industri Kimia: Revolusi R&D yang Menakjubkan
 Fase Substitusi Impor (1980-2000): China mulai mengimpor teknologi dan peralatan produksi kimia dari negara maju, fokus pada bahan kimia untuk pertanian dan industri dasar. Masih jadi follower, belum leader.
Fase Substitusi Impor (1980-2000): China mulai mengimpor teknologi dan peralatan produksi kimia dari negara maju, fokus pada bahan kimia untuk pertanian dan industri dasar. Masih jadi follower, belum leader.
Fase Inovasi (2000-2020): Investasi R&D kimia China naik drastis. Dari 22% total R&D kimia global (2012) jadi 34% (2022). Itu bukan cuma angka—itu bukti China mengubah diri dari kopian jadi kreator.
Fase Market Leadership (2020-sekarang): Industri kimia China bernilai $1,5 triliun—hampir 40% pendapatan industri kimia global.
Mereka tidak cuma memproduksi bahan kimia dasar, tapi juga specialty chemicals dan advanced materials untuk teknologi tinggi. Perusahaan kimia Jerman dan Amerika yang dulu dominan sekarang harus bersaing ketat dengan perusahaan China.
"Mereka berhasil mengubah posisi dari price taker jadi price maker," jelas si profesor. "Dulu mereka terima harga yang ditetapkan pasar, sekarang mereka yang menentukan harga pasar."
Era Assembling (1980-2000): China cuma jadi tempat perakitan mobil asing. Volkswagen, General Motors, Toyota datang untuk memanfaatkan tenaga kerja murah. China dapat upah, tapi tidak dapat teknologi.
Era Joint Venture (2000-2015): Pemerintah China paksa perusahaan asing buat joint venture dengan perusahaan lokal. Syaratnya: technology transfer. Pelan-pelan, perusahaan China belajar cara bikin mobil yang bener.
Era Electric Revolution (2015-sekarang): China tidak cuma jadi pasar mobil terbesar dunia dalam penjualan dan kepemilikan, tapi juga game changer dalam electric vehicle.
Baca Juga: Perang Mobil Listrik Uni Eropa versus China, Indonesia Dapat Apa?
BYD sekarang saingan serius Tesla. CATL menguasai 37% pasar baterai mobil listrik global. Mereka tidak cuma assembly lagi, tapi innovating.
Yang bikin Kabayan melongo: "Mereka loncat dari jadi tukang rakit mobil jadi ahli bikin baterai mobil masa depan. Sementara kita... "
Industri Perkapalan: Prediksi yang Jadi Kenyataan

The Bold Prediction (2009): Perdana Menteri Zhu Rongji dengan percaya diri bilang China akan jadi pembuat kapal terdepan di dunia pada 2015.
Waktu itu banyak yang skeptis—soalnya industri perkapalan didominasi Korea Selatan, Jepang, dan Eropa sejak puluhan tahun.
Strategic Execution (2009-2015): China tidak cuma bicara, tapi execute.
"Rencana Penyesuaian dan Revitalisasi Industri Perkapalan" diluncurkan sebagai roadmap konkret. Investasi masif dalam teknologi, pelatihan SDM, dan pembangunan galangan kapal modern.
Mission Accomplished (2015-sekarang): Done! China sekarang dominan dalam shipbuilding global. Mereka tidak cuma bikin kapal konvensional, tapi juga kapal dengan teknologi green and smart.
Galangan kapal di Scotland dan Jerman yang dulu legendaris sekarang kebagian order sisa.
Yang paling impressive: China melakukan "pergeseran sektor menuju perkapalan yang hijau dan cerdas"—mereka tidak cuma mengikuti tren, tapi menciptakan tren baru dalam industri perkapalan dunia.
Kabayan ngelus dada: "Mereka bilang mau jadi nomor satu dalam 6 tahun, dan beneran tercapai. Kita bilang mau jadi Indonesia Emas 2045... 20 tahun lagi masih entah gimana."***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.