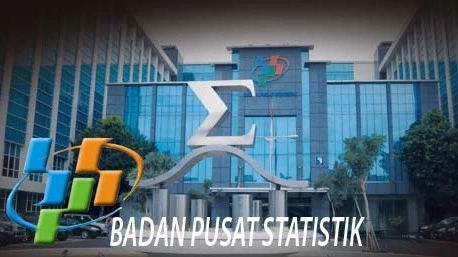Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).
Gebrakan pertama Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan baru bagi perekonomian nasional yang sedang menghadapi tekanan, baik secara domestik maupun global.
Kebijakan Menkeu Purbaya yang paling direspons publik adalah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, dana SAL tersimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).
Pemindahan dana SAL dari BI ke bank umum dimaksudkan untuk menambah likuiditas bank. Likuiditas berlebih di bank BUMN akan mendorong bank BUMN menyalurkan kredit dalam rangka menggerakkan sektor riil.
Menkeu Purbaya secara eksplisit menyebutkan bahwa kebijakan menambah likuiditas ke sistem perekonomian didasarkan pada pandangan Milton Friedman, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 1976.
Gagasan utama Friedman yang terkenal dengan Friedman Quantity Theory of Money menekankan pada pentingnya mengelola jumlah uang beredar (JUB) untuk menggerakkan sektor riil (sektor produksi).
Ekonom Friedman yang menjadi rujukan Menkeu Purbaya termasuk dalam kelompok monetaris. Formula utama dari kelompok monetaris adalah keseimbangan antara JUB dan kecepatan perpindahan uang dengan harga dan output.
Dalam hal ini, penempatan dana SAL ke bank BMUN menambah likuiditas bank sehingga memberikan insentif bagi bank BUMN untuk menyalurkan kredit dan berdampak pada peningkatan JUB.
Dalam jangka pendek, peningkatan JUB secara langsung ditransmisikan ke sektor riil dalam bentuk peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi.
Quick Win Strategy
 Gebrakan Menkeu Purbaya adalah quick win yang hasilnya segera dapat dirasakan dalam menggerakkan sektor riil, paling tidak dalam 3–6 bulan ke depan.
Gebrakan Menkeu Purbaya adalah quick win yang hasilnya segera dapat dirasakan dalam menggerakkan sektor riil, paling tidak dalam 3–6 bulan ke depan.
Hal ini sejalan dengan pandangan kelompok monetaris bahwa dalam jangka pendek, perubahan JUB langsung berdampak pada peningkatan output karena velocity of money (kecepatan perpindahan uang) dan harga bersifat kaku atau tak sensitif terhadap perubahan JUB.
Sebagai Menkeu baru, dalam jangka pendek, Purbaya harus mencari cara untuk segera menggerakkan sektor riil. Faktanya, terdapat dana SAL yang menganggur karena tidak dapat disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor riil.
Gebrakan Purbaya yang didasarkan pada pikiran Friedman, kelompok monetaris, juga tidak akan efektif dalam jangka panjang.
Kelompok monetaris menganut prinsip neutrality of money, yaitu penambahan likuiditas ke dalam perekonomian tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi malah menyebabkan kenaikan harga (inflasi) dalam jangka panjang.
Merujuk pada great depression tahun 1930-an, kelompok monetaris Friedman menyalahkan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed) sebagai pemicu krisis besar.
Pada saat The Fed memperketat pasokan uang, dalam istilah Menkeu Purbaya, mematikan mesin pertumbuhan dengan menurunkan likuiditas. Seharusnya, The Fed meningkatkan likuiditas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Moneter Lebih Berdampak Ketimbang Fiskal

Kelompok monetaris, Friedman, meyakini kebijakan moneter (baik ekspansif maupun kontraktif) adalah instrumen paling efektif untuk mempengaruhi perekonomian dibandingkan kebijakan fiskal (mengutak atik pajak dan belanja negara).
Friedman memperkenalkan K-Percent Rule dalam mempengaruhi sektor riil, di mana bank sentral seharusnya menjaga pertumbuhan JUB sebesar k-persen sehingga terdapat lebih banyak uang dalam perekonomian (likuiditas meningkat).
Peningkatan likuiditas perekonomian menurunkan suku bunga. Hal ini akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan kerja di sektor riil.
Sejalan dengan K-Percent Rule dari Friedman, dalam konteks perekonomian Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%–8% dengan menjaga inflasi 2,5%, pertumbuhan JUB paling tidak harus terjaga sekitar 8,5%–10,5% secara tahunan (year on year) dari saat ini hanya sekitar 7%.
Tantangan terbesar yang dihadapi Menkeu Purbaya dengan pendekatan monetaris Friedman adalah fakta bahwa hubungan antara inflasi dengan JUB bersifat tak langsung, yang menyebabkan kegagalan pendekatan Friedman mengendalikan inflasi tahun 1980-an.
Selain itu, terdapat fakta bahwa permintaan uang sangat fluktuatif bahkan dalam triwulanan. Juga terdapat time lag (jeda waktu) yang panjang hingga perubahan JUB mempengaruhi sektor riil. Fakta-fakta ini membuat monetarisme kehilangan kredibilitas.
Fenomena ini juga dapat terjadi terkait gebrakan Menkeu Purbaya memindahkan dana SAL Rp200 triliun dari BI ke bank BUMN. Bank BUMN membutuhkan jeda waktu (time lag) untuk menyalurkan kelebihan likuiditas menjadi kredit ke sektor riil.
Baca Juga: Risiko di Balik Gebrakan Menkeu Purbaya Mendorong Kebijakan Ekonomi Ekspansif
Faktanya, saat ini, bank-bank besar tidak bermasalah dari sisi likuiditas, tercermin pada loan to deposit ratio (LDR) yang masih sekitar 85% dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang LDR dapat mencapai maksimum 95%.
Selain itu, terdapat undisbursed loan (kredit tidak dicairkan) sebesar Rp2.372,11 triliun di perbankan nasional.
Solusinya, penggunaan kelebihan likuiditas dalam bentuk kredit di bank-bank BUMN yang mendapatkan penempatan dana SAL pemerintah tidak akan efektif jika menggunakan mekanisme pasar.
Penyaluran kredit bank BUMN harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan terfokus pada sektor tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.
Akhirnya, sebagai quick win, penempatan dana SAL Rp200 triliun tidak akan maksimal mendorong pertumbuhan jika suku bunga minimumnya 4% sesuai permintaan pemerintah.
Jika ditambah dengan net profit margin dan biaya operasional bank sebesar 3% maka suku bunga pinjaman menjadi 7% yang masuk kategori tinggi.
Ada baiknya, Menkeu Purbaya juga mendengar peringatan ekonom asal Swedia, Gunnar Myrdal, peraih hadiah nobel ekonomi tahun 1974, dua tahun lebih cepat dari Milton Friedman.
Menurut dia, permasalahan ekonomi sangat kompleks dan terkait dengan aspek sosial dan institusional. Aspek institusional mencakup sistem hukum, politik, dan budaya yang eksklusif serta ekstraktif. Termasuk transaction cost yang sangat tinggi.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.