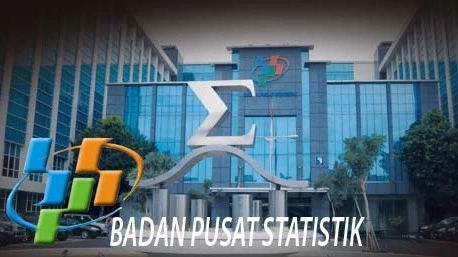Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), alumni KRA 37 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), kini menjadi Ketua Rukun Warga (RW) 16 Kelurahan Sekeloa, Bandung dan aktif di Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC).
Setelah delapan dekade merdeka, pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia justru kian kompleks dan terus memakan korban.
Salah satu akar masalahnya adalah praktik open dumping (pembuangan terbuka) yang sudah lama dilarang oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta dipertegas oleh PP No. 81 Tahun 2012.
Regulasi tersebut mengultimatum pemerintah daerah agar menutup tempat pembuangan akhir (TPA) open dumping dan beralih ke sanitary landfill atau teknologi ramah lingkungan lainnya paling lambat tahun 2013.
Namun, kenyataannya hingga kini mayoritas TPA masih beroperasi dengan sistem open dumping. Hal ini menimbulkan pencemaran, masalah kesehatan, hingga konflik sosial dengan warga sekitar.
Lebih jauh lagi, kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan, tarik-menarik kepentingan politik dan dominasi paradigma ekonomi linear (ambil–pakai–buang).
Dengan demikian, sampah bukan sekadar persoalan teknis dan lingkungan semata, tetapi dibalik itu adalah arena pertarungan politik - ekonomi yang menentukan distribusi sumber daya, manfaat, dan dampak.
Berikut ini analisis komprehensifnya.
Aktor kunci dan konflik kepentingan

Pemimpin Politik (Kepala Daerah/ Pemerintah)
Kepentingan: Mencapai target kinerja visibilitas tinggi (misalnya pembangunan insinerator atau TPA modern) untuk legitimasi politik.
Dilema: Tekanan antara memilih solusi cepat; berbiaya tinggi (proyek megah) vs solusi partisipatif; berkelanjutan (berbasis komunitas)
Kekuasaan: Mengontrol anggaran (APBD), regulasi, dan kebijakan izin operasional.
Perusahaan Swasta/Bisnis /Pengembang
Kepentingan: Lebih mengiklankan produk akhir dan mengejar sales melalui kontrak pengelolaan sampah skala besar (misalnya Waste-to-Energy/PLTSa, TPA regional)
Strategi: Lobi kebijakan untuk memenangkan proyek KPBU (Public-Private Partnership) jangka panjang, walau sangat langka karena prosedur KPBU belum robust
Dampak: Berpotensi meminggirkan pemulung dan UMKM daur ulang
Pemulung dan Komunitas Lokal
Kepentingan: Akses terhadap sampah bernilai ekonomi untuk mata pencaharian
Ketergantungan: Sektor informal ini menyumbang ~30% daur ulang nasional, tetapi sering diabaikan dalam kebijakan
Kerentanan: Terancam oleh kebijakan sentralisasi sampah (e.g., penutupan TPA ilegal, insinerator)
Masyarakat Sipil dan LSM
Kepentingan: Mendorong keadilan lingkungan (environmental justice) dan partisipasi publik
Peran: Advokasi kebijakan inklusif dan pengawasan implementasi.
Kebijakan Sampah: Dinamika Politik Ekonomi

Sentralisasi vs. Desentralisasi
Sentralisasi (misal: pembangunan insinerator/TPA besar—regional lintas kota/kabupaten, yang dianggap "modern " dan efisien secara politis, tetapi berisiko tinggi secara finansial dan lingkungan. Namun cenderung dipilih karena visibilitasnya.
Desentralisasi (misal, bank sampah, TPST komunitas). TPA di tingkat menengah (kecamatan) dengan kapasitas insenerator 12 ton-24 ton perhari. Lebih partisipatif dan berkelanjutan, tetapi kurang menarik secara politis karena skala kecil.
Regulasi dan Implementasi
UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah memandatkan pengurangan sampah dilakukan di sumber (reduce, reuse, recycle), juga penutupan TPA open dumping secara bertahap, dan pernah ditargetkan tuntas pada 2013.
Meskipun telah ada larangan dan sanksi, praktik open dumping masih terjadi di beberapa daerah. Keinginan untuk mendorong peralihan ke sistem yang lebih baik seperti sanitary landfill (lahan urug saniter) atau controlled landfill (lahan urug terkendali), dan sistem waste-to-xyz masih terkendala hingga saat ini.
Implementasi dan penegakan hukum sangatlah lemah karena keterbatasan anggaran, tekanan industri untuk mempertahankan model business-as-usual (misalnya: produsen plastik) dan peraturan daerah (perda) pengelolaan sampah yang bervariasi antardaerah tergantung kepemimpinan lokal dan kapasitas fiskal.
Politik Anggaran
Alokasi APBD untuk sampah sering diprioritaskan untuk pengumpulan dan transportasi (60-70% anggaran), pengolahan akhir (20-30%) dan bukannya untuk pencegahan di sumber.
Anggaran untuk program reduce-reuse-recycle biasanya kurang dari 10%.
Model Ekonomi: Linear vs Sirkular
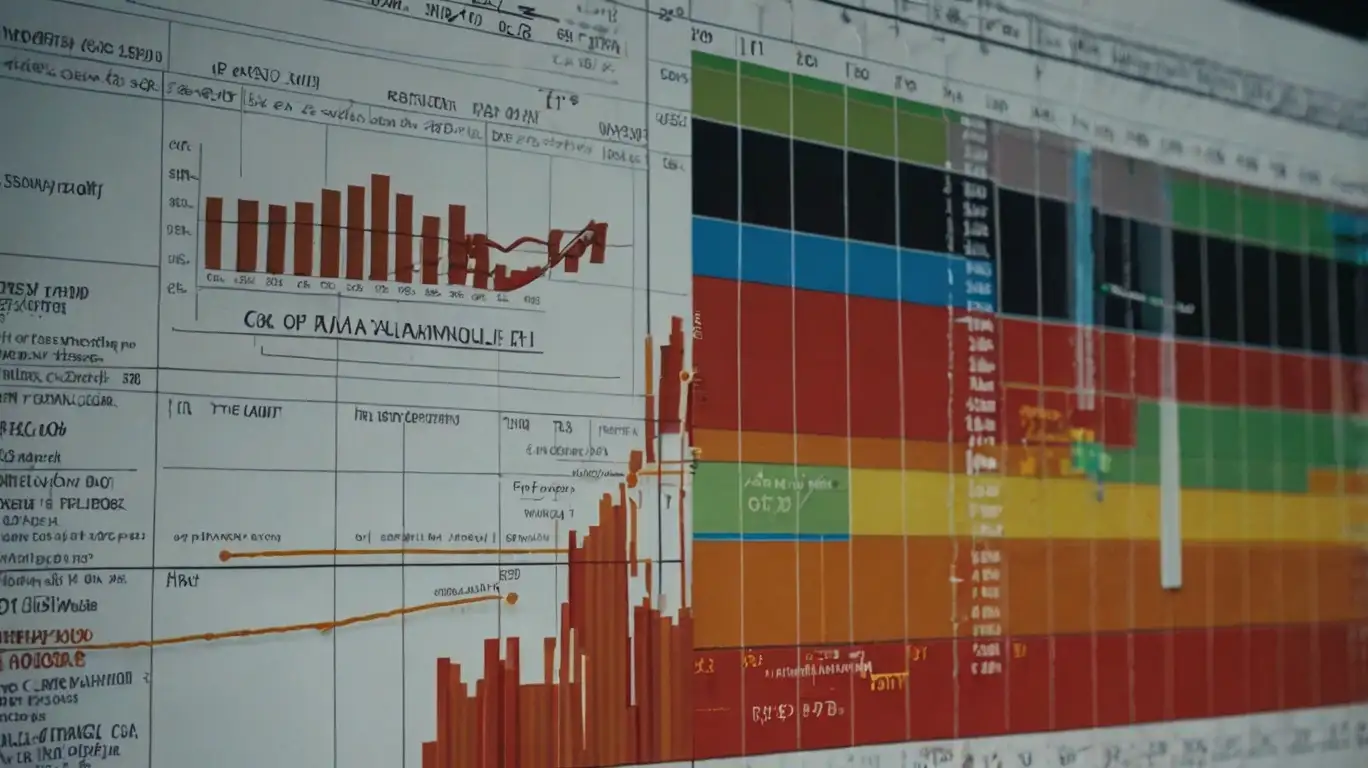
Ekonomi Linear (Dominan Saat Ini)
Prinsip: Take-make-dispose (ambil-gunakan-buang)
Aktor yang diuntungkan: Perusahaan produsen kemasan, pengelola TPA/insinerator
Dampak: Eksploitasi sumber daya dan polusi
Ekonomi Sirkular (Alternatif Berkelanjutan)
Prinsip: Sampah dianggap sebagai sumber daya. Bukan semata Sampah
Strategi: Extended Producer Responsibility (EPR) yakni memaksa produsen bertanggung jawab atas kemasan, memberikan insentif ekonomi untuk daur ulang dan komposting, integrasi pemulung dalam sistem formal platform digital
Penghalang: Korporasi menolak EPR karena menambah biaya.
Strategi Transformatif Menuju Keadilan Sampah

Kebijakan Inklusif
Legitimasi pemulung, mengintegrasikan mereka melalui koperasi dan akses pendanaan dengan bantuan platform digital iuran sampah.
Peran serta masyarakat: Desain kebijakan partisipatif (misalnya musrenbang khusus sampah).
Pemda dan Pemerintah Pusat memberlakukan regulasi kumpul dan olah sampah serta alokasi tipping fee yang wajar, bila ada kebutuhan investasi teknologi pemusnahan sampah.
Instrumen Ekonomi
Pajak/kemasan plastik untuk mendanai program daur ulang, berikan subsidi hijau untuk bank sampah dan UMKM daur ulang. Terbitkan green bonds untuk infrastruktur sampah berkelanjutan
Kepemimpinan Politik
Pemimpin perlu berani hadapi lobi korporasi dan pilih solusi berkelanjutan.
Studi Kasus: Politik Ekonomi Sampah di Jakarta dan Bandung

Di Jakarta, kebijakan insinerator (PLTSa) dipromosikan sebagai solusi sampah, tetapi ditolak masyarakat karena risiko polusi. Selain itu juga kental dengan kepentingan bisnis dan proyek mercusuar.
TPA Bantargebang mencerminkan kegagalan kebijakan sentralistik, menimbulkan konflik dengan warga sekitar akibat polusi dan overload.
Di Bandung, hasil diskusi sampah Bandung menunjukkan bahwa solusi pengelolaan sampah berkelanjutan sudah tersedia, tetapi tidak berjalan dengan optimal.
Penyebabnya adalah sistem birokrasi yang tak mau berubah, konflik kepentingan, dan dominasi aktor informal.
Sampah sebagai Arena Politik

Pengelolaan sampah adalah cerminan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.
Kebijakan yang berkeadilan harus mendesentralisasi pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan dengan peran Kelurahan dan RW sedapat mungkin menggerakkan sosialisasi zero-waste di RW masing-masing, termasuk toko, warung, restoran, dan pabrik.
Koperasi Merah Putih RW/ Kelurahan menghimpun iuran sampah dari tiap kepala keluarga melalui platform digital yang dikelola secara mandiri atau secara khusus dapat berupa Badan Pengelola Sampah Mandiri (BPSM).
BPSM melaksanakan dan bertanggung jawab mengumpulkan, mengolah sampah menjadi produk antara dan mengirim residunya untuk dimusnahkan atau dijadikan produk akhir di TPA Kecamatan oleh unit Pengelola Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Teknologi pemusnahan sampah yang dipakai harus berupa teknologi lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, karena memiliki kapasitas kecil atau menengah.
PSM sedapat mungkin mendorong dan mengembangkan rantai ekonomi sirkular dengan regulasi kuat.
Baca Juga: Dari Sampah Kota ke Sampah Nurani: Renungan Idulfitri di Tengah Krisis
Tantangan terbesarnya kini terletak pada kemauan komunal untuk melawan kekuatan korporasi maupun pengembang teknologi dan politik proyek yang abai terhadap keberlanjutan dan kemandirian lokal.
Dengan pendekatan politik-ekonomi ini, sampah tidak lagi dilihat sebagai masalah teknis, tetapi sebagai isue demokrasi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Selamat hari Kemerdekaan. Merdeka!***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.