
Oleh Zezen Zaenal Mutaqin, Kepala Program Magister dan Dosen di Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan minat akademis hukum internasional, hak asasi manusia, hukum humaniter, hukum Islam serta studi Islam secara umum. Meraih gelar Magister Hukum dari University of Melbourne, School of Law, dan gelar Doktor Ilmu Hukum (S.J.D) dari UCLA School of Law, dia menuangkan gagasan dan pemikirannya di blog.
Percayakah anda bahwa hukum Internasional yang dirumuskan oleh para pemikir Eropa seperti Hugo Grotius "berasal" dari Indonesia?
Kemarin saya berbicara di sebuah forum kajian yang diadakan oleh lembaga baru di kampus UIII. Nama lembaganya: Indonesian Institute for Foreign Affairs (IIFA).
Pada diskusi yang digelar pertama kali itu saya diminta menjadi pembicara bersama Pak Abdul Qadir Jailani, Dirjen Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri.
Fokus diskusi saya pada pencarian akar sejarah kontribusi Nusantara/Indonesia pada pembentukan hukum internasional abad ke 17: apakah Indonesia mempunyai peran, atau pengaruh, dalam pembentukan norma hukum internasional awal?
Sekilas pertanyaan itu aneh karena bukankah Indonesia baru merdeka pada 1945 dan karena itu pada abad 17 negara-bangsa bernama Indonesia belum lahir? Betul, dan karena itu kata Nusantara menjadi penting. Ia adalah cikal-bakal kita, Indonesia.
Mahasiswa di fakultas hukum biasanya belajar sejarah awal pembentukan hukum internasional.
Di kelas kita diajari bahwa hukum Internasional awal dirumuskan oleh para sarjana di Eropa pada abad ke 17. Ada dua mazhab: Mazhab Spanyol dan Mazhab Belanda.
Mazhab Spanyol dipelopori para sarjana dari Universitas Samalanca. Tokoh utamanya: Francisco de Vitoria, Fransisco Suarez dan Balthazar Ayala. Mereka mashyur disebut sebagai Mazhab Samalanca.
Sementara itu, Mazhab Belanda selalu disematkan pada pemikir legendaris abad ke 17, Hugo Grotius. Namanya dikenal bukan hanya oleh sarjana hukum, tapi oleh sejarawan pada umumnya. Ia dikenal sebagai peletak dasar hukum internasional.
Pelajaran Out of The Book
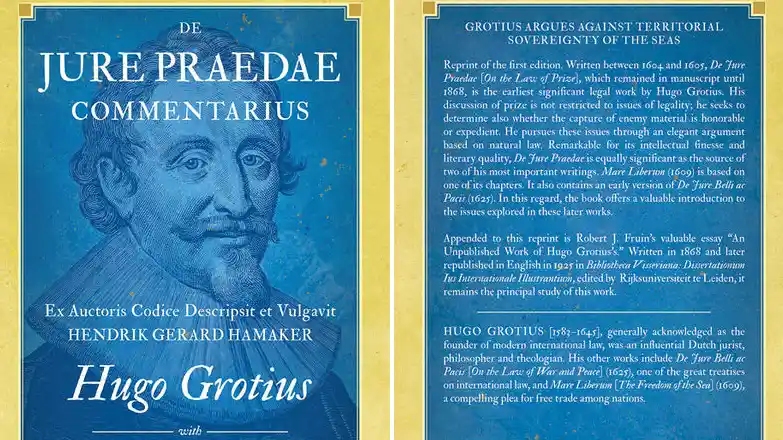
Itu yang dipelajari di kelas. Yang tidak dipelajari di kelas, mungkin karena terlalu tinggi, adalah detilnya yang justru sangat menarik: bahwa pembentukan hukum internasional itu sangat dekat dengan sejarah dan tradisi kita di Nusantara!
Tak banyak yang tahu bahwa dua buku penting Grotius, Free Sea (Lautan Bebas) dan The Law of Prize and Booty/De Jure Praedae (Hukum Pampasan Perang) awalnya adalah pledoi, naskah pembelaan, atas kasus penting di Nusantara.
Naskah yang disebut 'apologia' itu ditulis atas permintaan VOC pada 1604 karena sengketa hukum Belanda dengan Portugis.
Sengketanya sendiri bermula karena kasus Santa Catarina. Locus delicti-nya di perairan Johor--antara Riau dan Singapura sekarang. Santa Catarina adalah kapal laut kargo milik Portugis yang biasa berlayar dari Jepang, Korea, China dan Malaka.
Kapal itu diserang dan ditawan di perairan Johor pada 1603 oleh pasukan Sultan Alau'ddin Ri'ayat Syah yang berkoalisi dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pimpinan oleh Jacob van Heemskerck.
Kapal itu jadi pampasan perang dan lantas diberikan oleh Sultan kepada VOC dan dibawa ke Amsterdam. Muatannya luar biasa berharga ketika dilelang: seharga lebih dari 3.5 juta gulden, setara penghasilan British East India Company setahun di Sabah.
Portugis menuduh Belanda melakukan pelanggaran dan karena itu melakukan diplomasi dan upaya hukum membela haknya. Kasus itu disidangkan pada 1604 di Amsterdam Admiralty Court, semacam pengadilan urusan maritim di Amsterdam waktu itu.
Dalam konteks ini VOC meminta profesor muda di Leiden bernama Hogo Grotius untuk menulis pledoi yang disebut apologia. Profesor itu baru 20 tahun usianya. Pledoi yang ditulisnya sangat akademik dan teoritis karena ditulis dengan riset mendalam.
Dibukukan setelah Kemenangan VOC
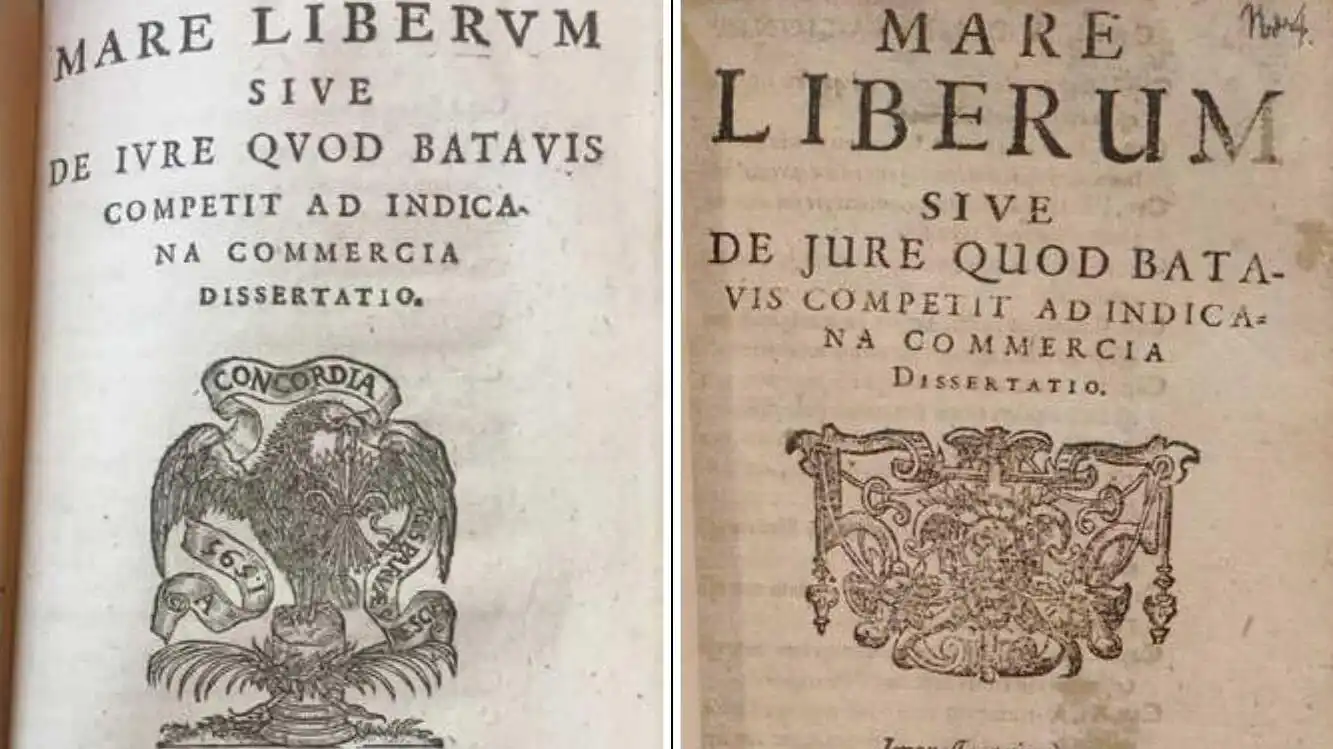 Bagian pendahuluan pledoi itu diterbitkan menjadi Mare Liberum, atau Free Sea pada 1609, tak lama setelah VOC dan Belanda memenangkan kasus Santa Catarina.
Bagian pendahuluan pledoi itu diterbitkan menjadi Mare Liberum, atau Free Sea pada 1609, tak lama setelah VOC dan Belanda memenangkan kasus Santa Catarina.
Sementara sebagian besar bab dalam pledoi itu baru terbit pada abad ke 19 setelah dokumennya ditemukan oleh Universitas Leiden dalam sebuah lelang. Naskah ini terbit dengan judul The Law of Prize and Booty atau De Jure Praedae dalam versi Latin.
Di antara kita banyak yang tidak sadar bahwa ketika VOC mulai datang ke Nusantara pada 1602, Belanda bukanlah negara merdeka. Ia masih menjadi bagian dari imperium Iberia Spanyol.
Belanda mengobarkan revolusi untuk merdeka dari Spanyol sejak 1568. Pada 1581 mereka secara terbuka menolak kedaulatan Spanyol atas dirinya dan menyatakan merdeka. Apa yang dikenal sebagai Act of Abjuration itu tentu tidak disetujui Spanyol.
Kita tahu, Belanda dan beberapa negara di Eropa Utara terus berkonflik dan berperang dengan Spanyol hingga 1648. Tahun itu penting pagi pada sejarawan karena saat itulah konsep dan entitas nation-state (negara-bangsa) lahir.
Itulah tahun lahirnya Perjanjian Westphalia. Belanda baru merdeka secara resmi dari Spanyol pada 1648.
Jadi perebutan kapal Kargo Santa Catarina di Johor itu adalah kepanjangan dari konflik di Eropa. Dan kasus Santa Catarina ini menjadi penting dalam hukum internasional karena menjadi tonggak beberapa teori besar:
Tak ada monopoli lautan, kebolehan membela diri (self defense) dengan kekuatan bersenjata, dan prinsip kedaulatan yang harus didasarkan pada hukum alam, bukan pada teologi Kristiani.
Saya ingin sedikit mengupas hal terakhir. Dalam buku De Jure Paedae, Grotius berargumen bahwa klaim Portugis atas kepemilikan East Indies atau Nusantara berdasar doktrin Terra Nulius tidak valid secara hukum.
Terra Nulius adalah doktrin kuno Romawi yang jadi dasar bagi setiap pencaplokan tanah dan kolonialisme.
Doktrin ini memandang bawah wilayah di luar dunia Kristen bisa dimiliki siapapun yang pertama kali menemukannya. Bahkan jika tanah itu sudah dihuni dan diperintah entitas berdaulat seperti Sultan dan Raja, sepanjang mereka bukan penganut Kristiani.
Grotius berargumen bahwa kedaulatan tidak didapatkan dari teologi Kristiani tapi dari hukum alam. Karena itu kedaulatan di luar dunia Kekeristenan harus diakui.
Para Sultan di Nusantara adalah entitas politik yang berdaulat. Karena itu modalitas hubungan tidak bisa didasarkan atas model kepemilikan (appropriation), tapi harus atas dasar kesepakatan dan kontrak (perjanjian atau treaty).
Untuk membuktikan itu, hampir lebih sepertiga isi buku de Jure Praedae mengelaborasi perjanjian-perjanjian Portugis dan Belanda dengan para Sultan Aceh, Banten, Johor, Jawa, Ternate dan lain-lain.
Baca Juga: Membaca Ulang Kartini
Ketika membaca buku Grotius, kita seperti membaca sejarah hukum perjanjian Nusantara!
Tak aneh jika sejarawan menyangsikan bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun. Sebagian besar modalitas dalam 200 tahun awal kehadiran Belanda adalah modalitas perjanjian dagang dan monopoli komoditas.
Memang Belanda lantas serakah pada 100 tahun terakhir. Ia berubah dari mitra dagang menjadi penjajah. Tapi terlepas dari fakta itu, Grotius dicatat sejarah sebagai sarjana yang mendorong pelepasan hukum dari teologi. Sekularisasi.
Ia yang memulai mengukuhkan pentingnya perjanjian dalam hukum internasional (treaty). Dan karena itu ia dianggap menjadi bapak hukum internasional.
Pertanyaan yang menggelayuti saya sekarang: di mana kita bisa menemukan dokumen-dokumen perjanjian antara para Sultan dengan Kesultanan lain atau dengan Portugis dan Belanda?
Jika kita bisa menemukannya, ini bisa menjadi objek studi yang sangat menarik bagi penulisan ulang sejarah hukum internasional.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStanceID.







