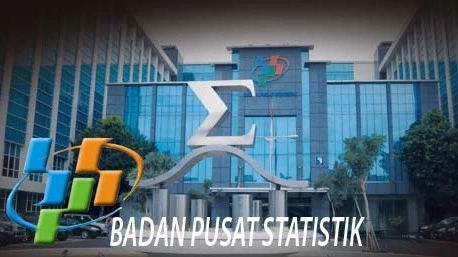Oleh GWS, lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang pernah didapuk menjadi direktur utama sebuah BUMN dan kini memimpin sebuah perusahaan teknologi. Aktif menuangkan tulisan dan pemikirannya tentang isu keindonesiaan, kebangsaan, dan kemajuan negara, meski dengan nama samaran.
"Yang paling ironis dari rejeki nomplok minyak: sebagian besar petrodolar Indonesia akhirnya berakhir di bank-bank Barat," Nyi Iteung menampilkan diagram alur.
Indonesia menyimpan pendapatan minyak di Chase Manhattan, Citibank, Bank of America—dengan tingkat bunga 2-3%. Bank kemudian meminjamkan uang ini kembali ke negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—dengan tingkat bunga 8-12%.
Margin intermediasi klasik yang sangat besar. Indonesia sebagai eksportir minyak malah menjadi peminjam bersih dari petrodolar sendiri.
"Ini yang disebut para ekonom sebagai 'daur ulang petrodolar'—tetapi Indonesia berada pada posisi terburuk dalam rantai nilai. Kita memproduksi minyak, namun lembaga keuangan Baratlah yang memperoleh sebagian besar nilai tambah."
David Rockefeller kemudian mengakui: 'Daur ulang petrodolar adalah salah satu bisnis paling menguntungkan dalam sejarah perbankan. Negara-negara berkembang memberi kami surplus mereka, dan kami meminjamkannya kembali kepada mereka dengan margin yang besar.'
Baca Juga: Geneva Auction & The New Order Foundation (1): Refleksi Jelang HUT Kemerdekaan RI
1962: Indonesia jadi anggota pendiri OPEC. 1970an: kartel minyak di puncak kekuasaan-nya, dengan Indonesia sebagai pemain penting. Subroto bahkan jadi Sekretaris Jenderal OPEC 1988-1994. Secara pemahaman: kesuksesan besar untuk Indonesia.
"Tapi dampak ekonominya lebih kompleks. Keanggotaan OPEC memberi Indonesia pengaruh dalam politik energi global, tapi juga menjadikan Indonesia tersandera oleh volatilitas harga minyak. Dutch Disease mulai mengintai: pendapatan ekspor minyak menguat rupiah, membuat ekspor nonmigas kurang kompetitif."
Korea Selatan, yang tidak punya minyak tapi berhasil mendaur ulang petrodolar dengan cemerlang, berhasil membangun industri berat dan kemampuan teknologi yang berkelanjutan. Indonesia dengan rejeki nomplok dari minyak malah jadi lebih bergantung pada ekspor komoditas.
“Malaysia, dengan cadangan minyak yang jauh lebih kecil, berhasil menggunakan pendapatan minyak untuk diversifikasi yang sistematis: Petronas menjadi perusahaan energi global, industri minyak sawit menjadi pemimpin dunia, perakitan elektronik menjadi kontributor signifikan. Indonesia dengan cadangan minyak 10x lipat Malaysia kebanyakan menyia-nyiakan peluang.”
Japanese Model vs Indonesian Reality
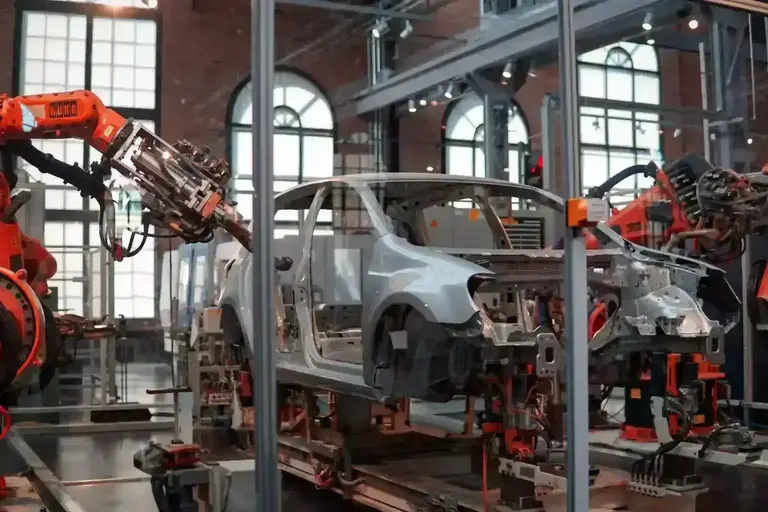
"Era yang sama, Jepang melakukan keajaiban ekonomi yang bisa jadi pelajaran bagi Indonesia,” Nyi Iteung menampilkan analisis komparatif.
Perkembangan ekonomi Jepang pascaperang: investasi asing selektif dengan transfer teknologi wajib, perlindungan terhadap industri dalam negeri selama fase pembelajaran, promosi ekspor yang agresif setelah industri kompetitif.
MITI (Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional) Jepang memiliki visi strategis jelas: dari manufaktur padat karya → industri berat padat modal → industri bernilai tinggi padat teknologi. Jangka waktu: 30 tahun dengan implementasi konsisten.
“Indonesia dengan keunggulan sumber daya alam seharusnya bisa melakukan hal yang sama, namun kebijakannya terfragmentasi dan berorientasi jangka pendek. Rejeki nomplok dari minyak digunakan untuk proyek konsumsi dan prestise, bukan untuk peningkatan industri yang sistematis.”
Yang paling menyakitkan: Indonesia sebenarnya punya basis industri yang menjanjikan pada tahun 1970an.
Krakatau Steel, Pindad, IPTN Habibie adalah upaya awal untuk industrialisasi berat. Tapi tidak mendapat dukungan yang konsisten karena para teknokrat lebih memilih pembangunan berbasis pasar.
“Di balik semua rejeki nomplok minyak dan investasi asing, mulai terbentuk struktur yang akan menentukan perekonomian Indonesia selama beberapa dekade: kapitalisme kroni,” Nyi Iteung menampilkan diagram jaringan yang kompleks.
Keluarga Soeharto dan rekan dekatnya mendapat akses istimewa terhadap kontrak pemerintah, izin impor, dan peluang usaha patungan.
The Crony Capitalism Foundation

"Liem Sioe Liong (Sudono Salim) membangun Salim Group melalui kemitraan eksklusif dengan keluarga Soeharto. Bob Hasan mendapat konsesi penebangan monopoli. Tommy Soeharto masuk ke industri otomotif dengan perlindungan yang berlebihan."
Yang menjadikan ini lebih dari sekedar korupsi: ini disusun sebagai model 'negara pembangunan', di mana pemerintah memilih pemenang untuk juara nasional. Inspirasi dari Korea Selatan dan Jepang, tapi eksekusinya dirusak oleh hubungan pribadi.
“Chaebol Korea seperti Samsung dan LG berkembang melalui dukungan pemerintah tetapi juga kompetisi internasional. Konglomerat Indonesia berkembang melalui perlindungan pemerintah tanpa persyaratan kinerja yang memadai.”
"1975: Krisis Pertamina adalah tanda peringatan yang seharusnya menjadi peringatan bagi masalah struktural," Nyi Iteung membuka file investigasi. "Pertamina, perusahaan minyak negara, mengakumulasikan utang sebesar USD 10 miliar—jumlah yang sangat besar untuk ukuran saat ini—melalui pinjaman di luar anggaran dan investasi spekulatif."
“Ibnu Sutowo, CEO Pertamina, menjalankan perusahaan seperti kerajaan pribadi: pinjaman untuk spekulasi real estate, investasi di bisnis non-inti, gaya hidup yang boros. Kasus klasik salah urus perusahaan milik negara.”
“Pemerintah memberikan dana talangan kepada Pertamina dengan uang pajak dan pinjaman baru, namun tidak melakukan reformasi mendasar dalam tata kelola BUMN. Preseden berbahaya: BUMN dapat mengambil risiko berlebihan dengan jaminan pemerintah yang implisit.”
“Yang lebih problematis: krisis ini tidak memicu tinjauan komprehensif terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia melanjutkan pendekatan yang sama: pendapatan minyak untuk belanja pemerintah, bukan untuk investasi produktif.”
Environmental and Social Costs: The Untold Story

“Sebagai analis yang bertanggung jawab, saya tidak bisa mengabaikan biaya lingkungan dan sosial dari model pembangunan ini,” Nyi Iteung menampilkan citra satelit Papua sebelum dan sesudah penambangan.
Operasi Freeport di Papua menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif: penggundulan hutan, pencemaran air, penggusuran masyarakat adat.
Perkiraan biaya restorasi lingkungan: US$50+ miliar—jumlah yang melebihi total manfaat ekonomi yang diterima Indonesia dari operasi Freeport. Investasi nilai sekarang bersih negatif untuk Indonesia dalam jangka panjang.
Ekstraksi minyak di Sumatera dan Kalimantan juga menimbulkan kerugian lingkungan besar: tumpahan minyak, emisi gas, degradasi hutan. Kerugian sosial: penggusuran masyarakat, terganggunya mata pencaharian tradisional dan dampak kesehatan.
“Yang tragis: Indonesia tidak memiliki peraturan lingkungan hidup atau persyaratan penilaian dampak sosial yang kuat untuk industri ekstraktif skala besar. Perusahaan beroperasi dengan pengawasan dan akuntabilitas yang minimal.”
“Sebagai eksperimen pemikiran final, mari kita membayangkan jalur pembangunan alternatif yang bisa diambil Indonesia 1967-1975,” Nyi Iteung menampilkan analisis skenario.
Opsi 1: Model Norwegia—rejeki nomplok dari minyak untuk dana kekayaan negara dan diversifikasi ekonomi bertahap.
“Dengan rejeki nomplok dari minyak sebesar US$200 miliar, dana kekayaan negara Indonesia bisa bangun yang kini bernilai US$2+ triliun—menjadikan dana kekayaan negara Indonesia terbesar secara global, lebih besar dari dana kekayaan Norwegia.”
Opsi 2: Model Malaysia—industrialisasi selektif dengan pendapatan sumber daya alam sebagai katalis. Gunakan uang minyak untuk pengembangan industri berat, investasi pendidikan, akuisisi teknologi.
Opsi 3: Model Botswana—pembagian pendapatan sumber daya alam dengan tata kelola yang transparan. Setiap warga negara mendapat manfaat langsung dari ekstraksi sumber daya alam melalui pendapatan dasar atau pembangunan infrastruktur.
“Pemeriksaan realitas: semua opsi ini sulit secara politik karena memerlukan institusi yang kuat, pemikiran jangka panjang, dan ketahanan terhadap tekanan politik jangka pendek. Indonesia pada tahun 1970an tidak memiliki kapasitas institusional untuk menerapkan strategi jangka panjang yang kompleks.”
Geneva Legacy: Foundation of Structural Problems
 “Konferensi Jenewa 1967 dan kebijakan-kebijakan berikutnya 1967-1975 membentuk pola struktural yang menentukan perekonomian Indonesia hingga saat ini,” Nyi Iteung menutup analisisnya dengan timeline yang komprehensif.
“Konferensi Jenewa 1967 dan kebijakan-kebijakan berikutnya 1967-1975 membentuk pola struktural yang menentukan perekonomian Indonesia hingga saat ini,” Nyi Iteung menutup analisisnya dengan timeline yang komprehensif.
Investasi asing dengan transfer teknologi minimal, ekstraksi sumber daya alam dengan persyaratan yang tidak menguntungkan, kesalahan pengelolaan rejeki nomplok minyak, munculnya kapitalisme kroni.
"50+ tahun kemudian, kita masih menghadapi konsekuensinya."
Kutukan sumber daya: Indonesia masih sangat bergantung ekspor komoditas tanpa pengolahan yang memberi nilai tambah signifikan. Polanya sama: ekspor bahan mentah, impor barang manufaktur.
Ketergantungan teknologi: Sektor manufaktur masih didominasi oleh perusahaan asing atau operasi perakitan dengan kandungan lokal yang terbatas. Konsumen Indonesia, bukan produsen, dari teknologi maju.
"Lembaga yang lemah: Struktur pemerintahan masih rentan terhadap perburuan rente dan korupsi. Penerimaan sumber daya alam masih belum optimal untuk pembangunan jangka panjang.
“Degradasi lingkungan: warisan industri ekstraktif berupa masalah lingkungan yang mahal untuk diperbaiki dan berdampak pada masyarakat dari generasi ke generasi.”
Epilog: The Auction House Remains Open
 “Sebagai analis investasi yang telah mengaudit transaksi terbesar dalam sejarah Indonesia, kesimpulan saya serius,” Nyi Iteung menutup laptopnya dengan ekspresi campur aduk antara frustrasi dan harapan.
“Sebagai analis investasi yang telah mengaudit transaksi terbesar dalam sejarah Indonesia, kesimpulan saya serius,” Nyi Iteung menutup laptopnya dengan ekspresi campur aduk antara frustrasi dan harapan.
Konferensi Jenewa 1967 bukan sekadar peristiwa bersejarah—konferensi ini menjadi acuan bagaimana Indonesia berinteraksi dengan modal global.
Template itu: Indonesia menyediakan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, perusahaan asing menyediakan teknologi dan akses pasar, distribusi manfaat sangat menguntungkan perusahaan asing.
Hingga 50+ tahun kemudian, template ini masih aktif dalam ekonomi digital: Indonesia menyediakan pasar dan data, platform asing menyediakan teknologi, sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri.
Yang paling tragis: Indonesia sebenarnya melakukan negosiasi dari posisi yang kuat pada 1967-1975. Rejeki nomplok dari minyak, sumber daya alam yang besar, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik.
Namun keterampilan negosiasi dan kapasitas kelembagaan tidak memadai untuk mencapai kesepakatan yang adil.
“Rumah lelang yang didirikan di Jenewa tahun 1967 tetap terbuka. Shopee, TikTok, Grab—mereka membeli ekonomi digital Indonesia dengan metodologi yang sama yang digunakan David Rockefeller untuk membeli sektor perbankan Indonesia."
Produk berbeda, proses sama: akses pasar untuk teknologi, dengan keuntungan yang sebagian besar mengalir ke luar negeri.
Pelajaran untuk Era Digital
 Indonesia harus belajar dari 50+ tahun kesepakatan yang tidak menguntungkan. Data adalah minyak baru, platform adalah perusahaan pertambangan baru, algoritma adalah teknologi ekstraksi baru.
Indonesia harus belajar dari 50+ tahun kesepakatan yang tidak menguntungkan. Data adalah minyak baru, platform adalah perusahaan pertambangan baru, algoritma adalah teknologi ekstraksi baru.
Namun posisi negosiasi Indonesia jauh lebih kuat saat ini: 270 juta konsumen digital, ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di ASEAN, populasi generasi muda yang berpendidikan.
“Pertanyaan untuk para pemimpin hari ini: Apakah kita akan mengulangi kesalahan seperti yang terjadi pada Jenewa 1967, atau akhirnya belajar bagaimana menegosiasikan kesepakatan yang adil yang menjaga kedaulatan Indonesia sambil mendapatkan manfaat dari integrasi global?”
Nyi Iteung menatap peta Indonesia di dinding yang penuh dengan pin yang menandai lokasi penanaman modal asing.
"Trilogi ini berakhir, tapi ceritanya terus berlanjut. Setiap generasi punya peluang untuk memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya. 2025-2045 adalah jendela untuk membatalkan warisan Jenewa dan membangun kedaulatan ekonomi Indonesia dalam ekonomi digital global."
Pasien selamat, para dokter menjalankan tugasnya, pelelangan pun terjadi. Kini saatnya generasi sekarang membeli kembali negara kita—secara digital, ekonomis, dan filosofis.
Bukan melalui revolusi, melainkan melalui negosiasi yang lebih baik, institusi yang lebih kuat, dan strategi yang lebih cerdas.
The auction house is still open. The question is: are we bidders or are we still being auctioned?***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance