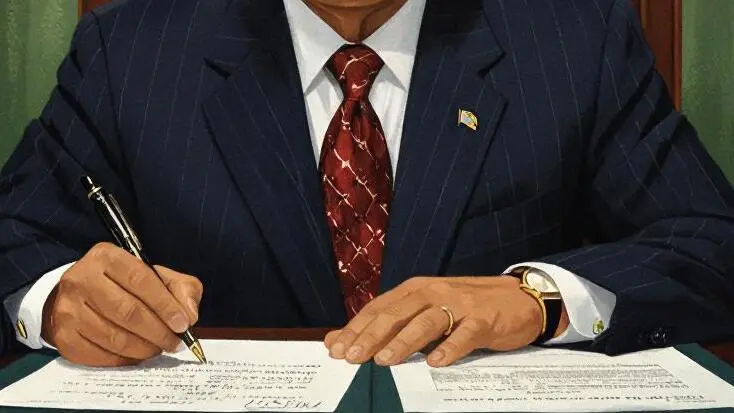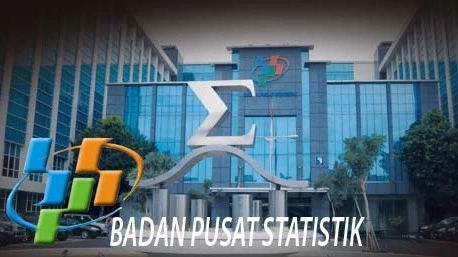Oleh GWS, lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang pernah didapuk menjadi direktur utama sebuah BUMN dan kini memimpin sebuah perusahaan teknologi. Aktif menuangkan tulisan dan pemikirannya tentang isu keindonesiaan, kebangsaan, dan kemajuan negara, meski dengan nama samaran.
Di ruang kerja yang dipenuhi kontrak investasi asing tebal berjilid-jilid dan peta sebaran perusahaan multinasional di Indonesia, Nyi Iteung duduk dengan ekspresi seorang analis investasi yang sedang membedah Structured Deals paling kontroversial.
Di hadapannya terbentang flowchart kepemilikan perusahaan, perjanjian royalti, dan proyeksi arus kas yang menunjukkan bagaimana kekayaan alam Indonesia mengalir keluar selama puluhan tahun.
"Dangukeun," katanya sambil membuka laptop yang menampilkan citra satelit tambang Freeport di Papua, "Episode I kita membedah bagaimana pasien hampir mati dalam pertumpahan darah geopolitik. Episode II bagaimana dokter-dokter Berkeley menyelamatkan nyawa dengan operasi aneh. Hari ini, Episode III—final dari trilogi: bagaimana pasien yang sudah diselamatkan kemudian dijual di rumah lelang paling canggih dalam sejarah kapitalisme."
"Konferensi Jenewa November 1967—di sana lah Indonesia secara literal dilelang kepada penawar tertinggi. Bukan dengan palu lelang dan teriakan juru lelang, tapi dengan presentasi PowerPoint, model keuangan, dan wine & dine yang elegan. Kolonisasi ekonomi paling beradab dalam sejarah manusia."
Nyi Iteung menghela napas panjang.
"Sebagai analis investasi dengan pengalaman 30 tahun, saya akan mempelajari bagaimana Indonesia mendapat kesepakatan terburuk dalam sejarah kontrak sumber daya alam—kesepakatan yang masih menghantui kita hingga hari ini di era kolonialisme digital."
Geneva Conference—"The Most Expensive Wine & Dine in History"
 "2-3 November 1967, Hotel President Wilson, Jenewa," Nyi Iteung membuka folder tebal bertulisan "CONFIDENTIAL".
"2-3 November 1967, Hotel President Wilson, Jenewa," Nyi Iteung membuka folder tebal bertulisan "CONFIDENTIAL".
Time-Life Corporation mensponsori konferensi yang secara resmi bertitel 'To Aid in the Rebuilding of a Nation'. "Kedengarannya bersifat kemanusiaan, bukan? Kenyataan: perpecahan perusahaan terbesar di negara berkembang di era pasca-kolonial."
Yang hadir: David Rockefeller (Chase Manhattan), Henry Ford II (Ford Motor), eksekutif puncak dari General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, US Steel, International Paper Corporation. Ditambah perwakilan dari pemerintah Indonesia: Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Radius Prawiro.
"John Pilger dalam laporan investigasinya mengungkap apa yang terjadi: 'Dalam tiga hari, mereka merancang pengambilalihan Indonesia. Para kapitalis paling berkuasa di dunia membagi-bagi ekonomi Indonesia sektor demi sektor.'"
Dialog imajiner antara David Rockefeller dengan delegasi Indonesia, konferensi hari pertama:
Rockefeller: "Gentlemen, we appreciate President Suharto's commitment to creating favorable investment climate. What we need is clarity on sectoral opportunities."
Ali Wardhana: "Mr. Rockefeller, Indonesia welcomes foreign investment that brings technology transfer and employment opportunities."
Rockefeller: "Excellent. Let's discuss specifics. Chase Manhattan is interested in banking sector. We'd like majority control to ensure international standards."
Mohammad Sadli: "We can arrange joint ventures with state banks..."
Rockefeller: "Joint ventures are... limiting. We prefer full operational control for efficiency reasons."
Day Two: The Great Carve-Up

“Hari kedua: bisnis sebenarnya dimulai,” Nyi Iteung menampilkan diagram yang menunjukkan pembagian.
Mereka secara harfiah membagi Indonesia ke dalam lima sesi paralel: pertambangan di satu ruang, jasa di ruang lain, industri ringan di ruang ketiga, perbankan & keuangan di ruang keempat, infrastruktur di ruang kelima.
"Di ruang penambangan: Freeport McMoRan ngobrol dengan Forbes Wilson tentang deposit tembaga Papua. Henry Kissinger (belum jadi Menteri Luar Negeri, masih profesor Harvard) hadir sebagai 'konsultan akademis'—secara kebetulan, dia kemudian menjadi anggota dewan Freeport."
Di banking room: Chase Manhattan, First National City Bank (sekarang Citibank), dan Bank of America diskusi tentang penetrasi pasar keuangan Indonesia.
Di ruang industri: General Motors, Ford, dan pabrikan Jepang merencanakan pabrik perakitan otomotif di Indonesia.
"Yang paling mencengangkan: mereka bahkan sudah punya peta rinci sumber daya alam Indonesia yang lebih lengkap dari yang dimiliki pemerintah Indonesia sendiri. Survei geologi, perkiraan cadangan minyak, deposit mineral—perusahaan-perusahaan AS punya data yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia."
"Mari kita memperbesar kesepakatan paling ikonik: kontrak Freeport-McMoRan untuk penambangan Papua," Nyi Iteung membuka kontrak setebal 200 halaman.
Ditandatangani April 1967—hanya 6 bulan setelah Soeharto resmi berkuasa. "Waktunya yang... menarik."
Freeport Deal: Master Class in Resource Extraction
 Persyaratan kontrak yang benar-benar mengejutkan untuk ukuran modern: Freeport mendapat hak eksklusif 30 tahun untuk wilayah 100.000 hektar di Papua, tarif royalti hanya 1,5% dari pendapatan kotor (standar internasional 5-10%), tarif pajak perusahaan 35% (bisa lebih rendah dengan insentif), repatriasi keuntungan tidak terbatas, tidak ada persyaratan kandungan lokal, tidak ada kewajiban transfer teknologi.
Persyaratan kontrak yang benar-benar mengejutkan untuk ukuran modern: Freeport mendapat hak eksklusif 30 tahun untuk wilayah 100.000 hektar di Papua, tarif royalti hanya 1,5% dari pendapatan kotor (standar internasional 5-10%), tarif pajak perusahaan 35% (bisa lebih rendah dengan insentif), repatriasi keuntungan tidak terbatas, tidak ada persyaratan kandungan lokal, tidak ada kewajiban transfer teknologi.
"Yang paling gila: Indonesia bahkan menanggung biaya pembangunan infrastruktur—jalan raya, pelabuhan, bandara—yang terutama menguntungkan operasi Freeport. Kasus klasik di mana negara tuan rumah mensubsidi ekstraksi asing."
Forbes Wilson, CEO Freeport, kemudian mengakui dalam memoarnya: 'Itu adalah kesepakatan abad ini. Kami mendapatkan semua yang kami minta, ditambah hal-hal yang bahkan tidak berani kami minta.'
Dialog imajiner antara Forbes Wilson dengan Mohammad Sadli, April 1967:
Wilson: "Minister Sadli, we're prepared to invest significant capital in Papua mining operations. But we need guarantees..."
Sadli: "What kind of guarantees, Mr. Wilson?"
Wilson: "Political stability, unlimited profit repatriation, protection from nationalization, minimal royalty rates during investment recovery period..."
Sadli: "These terms seem... quite favorable to your company."
Wilson: "Minister, we're taking enormous risks in unstable region. These terms reflect risk-adjusted returns. Without them, no investment."
Sadli: "And if we agree, what does Indonesia get?"
Wilson: "Jobs, technology transfer, foreign exchange earnings, and of course, substantial royalty payments once we reach full production."
Numbers Game: What Indonesia Really Got vs What They Gave

"Setelah 50+ tahun beroperasinya Freeport, mari kita mengaudit hasil sebenarnya," Nyi Iteung menampilkan analisis spreadsheet.
Total nilai produksi 1973-2023: sekitar US$150 miliar. Bagian Indonesia melalui royalti, pajak, dan biaya: sekitar US$20 miliar. Investasi infrastruktur Indonesia untuk mendukung Freeport: US$15 miliar.
Manfaat bersih untuk Indonesia: US$5 miliar selama 50 tahun. Itu berarti US$100 juta per tahun untuk tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Pemegang saham Freeport menerima: US$130 miliar.
Sebagai perbandingan: Statoil Norwegia dari minyak Laut Utara memberikan 78% keuntungan kepada pemerintah Norwegia. Penambangan berlian Botswana memberikan 50% keuntungan kepada pemerintah melalui usaha patungan Debswana.
Indonesia dari Freeport: 13% keuntungan.
"Bahkan lebih tragis lagi: biaya pembersihan lingkungan di Papua diperkirakan mencapai US$50+ miliar—lebih besar dari total manfaat yang diterima Indonesia. Kasus klasik: keuntungan yang diprivatisasi, biaya yang disosialisasikan."
Oil Windfall: The Greatest Missed Opportunity

“1973-1979: krisis minyak memberikan rejeki nomplok terbesar bagi Indonesia dalam sejarah,” Nyi Iteung menampilkan grafik harga minyak.
Harga minyak naik dari US$3 per barel menjadi US$35—meningkat 1.000%+ dalam 6 tahun. Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan menengah atas hampir dalam semalam.
"Total rejeki nomplok dari minyak pada tahun 1973-1982: sekitar US$200 miliar dalam nilai uang saat ini. Jumlah yang cukup untuk membangun dana kekayaan negara terbesar di dunia, atau mengubah Indonesia menjadi Korea Selatan Asia Tenggara."
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia menunjukkan: 40% untuk proyek bergengsi (Monas, Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah/TMII, mega infrastruktur), 25% untuk pengadaan militer.
Adapun 20% untuk perluasan birokrasi, 10% untuk usaha kroni kapitalis, menyisakan hanya 5% untuk investasi produktif dan pengembangan sumber daya manusia.
"Kehilangan peluang yang membuat saya menangis sebagai analis: Singapura dengan rejeki nomplok dari minyak jauh lebih kecil berhasil membangun Temasek Holdings yang sekarang bernilai US$400+ miliar. Norwegia membangun Dana Pensiun Pemerintah Global senilai US$1,4 triliun. Abu Dhabi membangun dana kekayaan negara yang terdiversifikasi ke seluruh dunia."
Dialog imajinasi antara Soeharto dengan teknokrat, 1975:
Soeharto : “Pak Widjojo, uang minyak mengalir deras. Apa rencana penggunaannya?”
Widjojo: "Pak, kita bisa gunakan untuk mempercepat pembangunan: infrastruktur, pendidikan, industrialisasi..."
Ali Wardhana: "Saya menyarankan sebagian berinvestasi untuk dana stabilisasi, mengantisipasi volatilitas harga minyak."
Soeharto: "Rakyat perlu melihat hasil pembangunan yang konkret. Bangun monumen, jalan raya, proyek pameran yang mengecewakan."
Widjojo : “Pak, monumen tidak menghasilkan return. Lebih baik berinvestasi di aset produktif…”
Soeharto: "Widjojo, politik itu berbeda dengan ekonomi. Rakyat perlu merasa bangga dengan prestasi pembangunan yang kasat mata."***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance