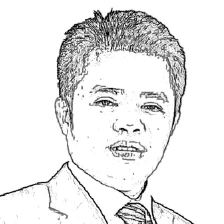
Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).
Fenomena all-time high (ATH) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan depresiasi nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat (AS) menarik untuk dianalisis.
IHSG beberapa kali mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah sejak 15 Agustus 2025 menjadi 8.017 dan pada saat yang sama, nilai tukar rupiah per dolar AS terdepresiasi hingga awal tahun 2026.
Nilai tukar rupiah per dolar AS pada 14 Agustus 2025 tercatat sangat kuat, yaitu sebesar Rp16.170/dolar AS lalu melemah menjadi Rp16.770,7 pada 25 September 2025 (Trading Economics, 2026).
Tren pelemahan rupiah dan penguatan IHSG berlanjut hingga Selasa (13/1/2026). Kurs rupiah menyentuh titik terendah sejak 8 April 2025, yaitu sekitar Rp16.875/dolar AS.
Sebaliknya, IHSG mengalami tren penguatan, yaitu dari level terendah sebesar 5.675 pada 8 April 2025 dan tertinggi sebesar 8.954 pada 8 Januari 2026.
Fenomena ini melahirkan pertanyaan, mengapa nilai tukar rupiah per dolar AS melemah pada saat IHSG menguat? Dalam beberapa kasus keduanya memiliki pergerakan yang searah.
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal untuk membalikkan arah pelemahan rupiah?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, ada baiknya merujuk pada ekonom senior Jeffrey A. Frankel dari Kennedy School of Government, Harvard University yang memperkenalkan komsep “portofolio balance approach models”.
Kecenderungan Investor Global Rebalancing Aset
 Pendekatan Frankel menyebutkan bahwa pada saat terjadi tekanan, investor global akan melakukan rebalancing atau rekalkulasi kepemilikan aset keuangannya dan cenderung lebih memilih aset keuangan yang menawarkan tingkat pengembalian tertinggi.
Pendekatan Frankel menyebutkan bahwa pada saat terjadi tekanan, investor global akan melakukan rebalancing atau rekalkulasi kepemilikan aset keuangannya dan cenderung lebih memilih aset keuangan yang menawarkan tingkat pengembalian tertinggi.
Setiap aset dinyatakan dalam mata uang lokal di mana investor global dianggap memiliki perilaku home country bias (mendahulukan aset keuangan negaranya sendiri).
Lebih jauh, aset keuangan domestik dan luar negeri tidak bersubtitusi secara sempurna (imperfect substitute).
Dalam regim nilai tukar mengambang bebas, kenaikan harga aset di suatu negara, misalnya IHSG, akan mendorong investor global membeli saham di negara bersangkutan.
Hal di atas mendorong aliran modal masuk ke suatu negara (capital inflow) yang menyebabkan mata uang negara bersangkutan terapresiasi (menguat).
Sebaliknya, pada saat harga aset keuangan turun membuat investor global mengalihkan investasinya ke negara lain. Terjadi aliran modal keluar (capital outflow) yang menyebabkan mata uang negara bersangkutan terdepresiasi (melemah).
Secara faktual, perkembangan harga saham tidak harus selalu searah dengan perkembangan nilai tukar rupiah per dolar AS. Hal ini berkaitan dengan peran investor asing di pasar modal Indonesia yang cenderung mengalami penurunan.
Saat ini investor asing hanya menguasai 40–43,6% kepemilikan saham pada 2025, turun dari 46,5% tahun 2024. Mereka umumnya cenderung hanya membeli saham blue-chip berkapitalisasi besar seperti BRI, BNI, Bank BCA, Bank Mandiri dll.
IHSG Naik, Blue Chip Mengapa Turun?

Sebagai ilustrasi, pada periode Juli–September 2025, IHSG menguat sebesar 16,4% dari posisi 6.923 menjadi 8.061. Menariknya, pada periode yang sama, saham-saham blue-chip yang berkapitalisasi besar justru mengalami penurunan.
Sebaliknya, saham-saham non blue-chip yang berkapitalisasi kecil justru mengalami kenaikan harga dan aktif ditransaksikan di pasar saham. Hal ini melahirkan isu keberadaan “saham gorengan” oleh investor lokal yang mendongkrak IHSG.
Faktanya, terdapat tiga saham berkapitalisasi kecil yang aktif ditransaksikan di pasar saham Indonesia sehingga harganya meningkat yaitu PT DCI Indonesia Tbk (DCII), PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA), dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT).
Jika harga saham ketiga perusahaan tersebut di atas dikeluarkan dari penghitungan IHSG, maka sejatinya IHSG hanya sekitar 7.340 bukan 8.116,2 (Kompas, 23/11/2025).
Sementara, tren depresiasi rupiah per dolar AS terjadi sejak tahun lalu dan secara khusus dalam beberapa hari terakhir, yaitu dari Rp16.685/dolar AS (2/1/2026) menjadi Rp16.840/dolar AS (9/1/2026).
Bahkan, depresiasi rupiah per dolar AS saat ini cenderung menuju ke posisi terlemah rupiah per dolar AS dalam setahun terakhir sebesar Rp17.071 (8/4/2025).
Depresiasi rupiah dipicu sentimen negatif terhadap mata uang rupiah sebagai respon investor global terhadap meningkatnya risiko perekonomian global akibat penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS pada Sabtu (3/1/2026).
Pada saat terjadi turbulensi dalam perekonomian global, investor global beralih memegang safe-haven currency atau safe-haven asset, yaitu aset yang nilainya stabil dan bahkan meningkat meskipun terjadi tekanan.
Posisi Dolar AS Sebagai Safe Haven
 Salah satu mata uang yang selama ini dianggap sebagai safe-haven currency adalah dolar AS. Peralihan ke safe-haven currency oleh investor global tercermin pada peningkatan US Dollar Index (DXY) dari 98,42 (2/1/2026) menjadi 99,12 (9/1/2026).
Salah satu mata uang yang selama ini dianggap sebagai safe-haven currency adalah dolar AS. Peralihan ke safe-haven currency oleh investor global tercermin pada peningkatan US Dollar Index (DXY) dari 98,42 (2/1/2026) menjadi 99,12 (9/1/2026).
Peningkatan DXY mencerminkan penguatan mata uang dollar AS terhadap enam mata uang utama dunia, yaitu Euro, Yen Jepang, Poundsterling Inggris, Dollar Kanada, Krona Swedia dan Swiss Franc.
Penguatan mata uang dollar AS terhadap mata uang utama dunia juga berdampak pada penguatan mata uang Dolar AS terhadap mata uang Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia di mana investor mengalihkan kepemilikan asetnya dari rupiah ke dollar AS.
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas fiskal dan moneter?” Langkah pertama, otoritas moneter dan fiskal harus bisa meyakinkan pelaku pasar bahwa prospek perekonomian nasional sangat baik.
Hal ini tercermin pada kondisi fundamental rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2025 yang diperkirakan sekitar 5,45% dan perkiraan inflasi yang rendah sekitar 2,92% pada 2025 secara tahunan (year-on-year).
Selain itu, suku bunga riil yang tinggi tercermin pada policy rate dalam hal ini BI rate yang masih jauh di atas inflasi, dan lainnya.
Baca Juga: Risiko Perekonomian Global Akibat Penangkapan Nicolas Maduro
Langkah kedua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal harus lebih baik sehingga memberikan keyakinan kepada investor bahwa arah perekonomian nasional masih sesuai dengan target pemerintah, terutama berkaitan dengan angka defisit fiskal yang sudah mendekati batas atas sesuai ketentuan konstitusi sebesar 3%.
Akhirnya, pemerintah perlu meyakinkan para investor bahwa meskipun defisit fiskal meningkat tetapi tidak mengurangi kemampuan pemerintah membayar cicilan utang dan bunganya yang tercermin pada Debt Service Ratio (DSR) yang berada di sekitar batas aman 30% dan menjaga BI rate tetap menarik bagi investor untuk menjamin stabilitas rupiah per dolar AS.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.







