
Oleh GWS, lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang pernah didapuk menjadi direktur utama sebuah BUMN dan kini memimpin sebuah perusahaan teknologi. Aktif menuangkan tulisan dan pemikirannya tentang isu keindonesiaan, kebangsaan, dan kemajuan negara, meski dengan nama samaran.
Yang membuat mindmap Kabayan semakin kompleks adalah garis-garis penghubung antara keempat pilar tersebut. Semuanya saling terkait dalam lingkaran setan yang sulit diputus, sekaligus menjadi alasan mengapa harus diperbaiki secara bersamaan:
Pendidikan buruk → SDM tidak kompeten → Meritokrasi rusak → Pemimpin inkompeten melindungi pendidikan buruk
Meritokrasi rusak → Pejabat tidak kapabel → KKN merajalela → Oligarki menguat → Oligarki mengontrol rekrutmen pejabat
KKN merajalela → Sumber daya tersedot → Investasi pendidikan minim → Pendidikan semakin buruk
Oligarki menguat → Mengendalikan politik → Media dikendalikan → Meritokrasi diabaikan → Korupsi dilindungi
"Inilah mengapa terapi parsial selalu gagal," kata Bung Hatta sambil menunjuk diagram lingkaran setan.
"Setiap upaya memperbaiki satu pilar akan dilawan oleh tiga pilar lainnya. Seperti hydra dalam mitologi Yunani—potong satu kepala, tumbuh dua kepala baru."
Baca Juga: Si Kabayan Bertapa di Ciptagelar (2): Refleksi Jelang HUT Kemerdekaan RI
Pada malam terakhir pertemuannya dengan para leluhur bangsa, Kabayan duduk terdiam menatapi mindmap yang telah selesai. Diagram itu seperti potret rontgen penyakit kronis yang menggerogoti tubuh bangsa.
"Bung, bagaimana cara memutus lingkaran setan ini?" tanya Kabayan pada keempat founding fathers.
Mereka saling berpandangan sejenak. Ki Hadjar yang menjawab lebih dulu:
"Harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa sistem yang ada sudah tidak berkelanjutan. Indonesia harus sadar bahwa kekayaan sejati bukan dari mengeruk alam, tetapi dari membangun kemampuan manusia."
Bung Hatta menambahkan: "Perlu gerakan moral yang masif untuk mengembalikan integritas dalam kehidupan berbangsa. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah karakter bangsa."
Djuanda meneruskan: "Sistem meritokrasi harus dipaksa untuk ditegakkan, meski akan ada perlawanan dari yang diuntungkan sistem lama. Seperti Korea yang nekat melawan konglomerat, Indonesia harus berani melawan oligarki."
Soekarno menutup dengan nada penuh semangat: "Yang paling penting adalah membangun kembali semangat nasionalisme ekonomi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak mau selamanya jadi kuli di negeri sendiri!"
Epilog: Kebangkitan atau Mimpi?
 Ketika fajar menyingsing di Ciptagelar, Kabayan terbangun sendiri di bawah pohon Saninten. Para leluhur bangsa sudah tidak tampak, tetapi mindmap di tanah masih terlihat jelas—atau mungkin Kabayan yang menggambarnya dalam tidur?
Ketika fajar menyingsing di Ciptagelar, Kabayan terbangun sendiri di bawah pohon Saninten. Para leluhur bangsa sudah tidak tampak, tetapi mindmap di tanah masih terlihat jelas—atau mungkin Kabayan yang menggambarnya dalam tidur?
Ia menatap diagram kompleks yang menunjukkan empat akar masalah Indonesia: pendidikan yang salah arah, meritokrasi yang rusak, integritas yang terkikis, dan oligarki yang menguat.
Semuanya terhubung dalam lingkaran setan yang menjelaskan mengapa Indonesia terjebak dalam ruang produk kompleksitas rendah.
Yang lebih penting, diagram itu juga menunjukkan mengapa keempat masalah itu harus diselesaikan secara bersamaan—seperti mengobati penyakit sistemik yang memerlukan terapi holistik.
Kabayan duduk terdiam, merasakan beban berat di dadanya. Sebentar saja, godaan itu datang—godaan untuk melupakan semua ini.
Ia bisa saja pulang ke Jakarta, memanfaatkan gelar Harvard untuk mendapat posisi nyaman di konsultan multinasional atau BUMN. Gaji besar, rumah mewah, anak sekolah internasional.
Mengapa harus repot-repot memikirkan bangsa yang sepertinya tidak mau berubah?
"Mudah saja," bisiknya pada diri sendiri. "Jadi seperti yang lain. Ambil keuntungan dari sistem yang rusak, daripada capek-capek memperbaikinya."
Monolog Kebimbangan

Tapi kemudian wajah-wajah para founding fathers kembali muncul dalam ingatannya. Bung Hatta yang menjual motor untuk biaya proklamasi. Soekarno yang hidup sederhana meski bisa kaya raya.
Ki Hadjar yang memilih mendidik bangsa daripada menjadi pejabat kolonial. Mereka semua punya pilihan mudah, tapi mereka memilih yang sulit.
Kabayan menggeleng keras. "Tidak. Jika aku mengambil jalan mudah, aku sama saja dengan bagian dari masalah."
Abah yang kebetulan lewat melihat Kabayan duduk termangu. "Kumaha, Kang? Parantos nampi jawaban?" (Bagaimana, Bang? Sudah mendapat jawaban?)
Kabayan mengangguk sambil melipat kertas berisi mindmap. "Sudah, Bah. Sekarang saya tahu penyakitnya. Tinggal mencari obatnya."
"Meski obatnya pahit?"
"Najan obatna pait (meski obatnya pahit)," jawab Kabayan mantap, kali ini dengan keyakinan yang sudah melewati ujian godaan.
Kabayan bersiap-siap pulang ke Jakarta dengan bekal pemahaman baru. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah—memutus lingkaran setan yang sudah mengakar puluhan tahun membutuhkan keberanian dan pengorbanan.
Refleksi tentang Harga Transformasi
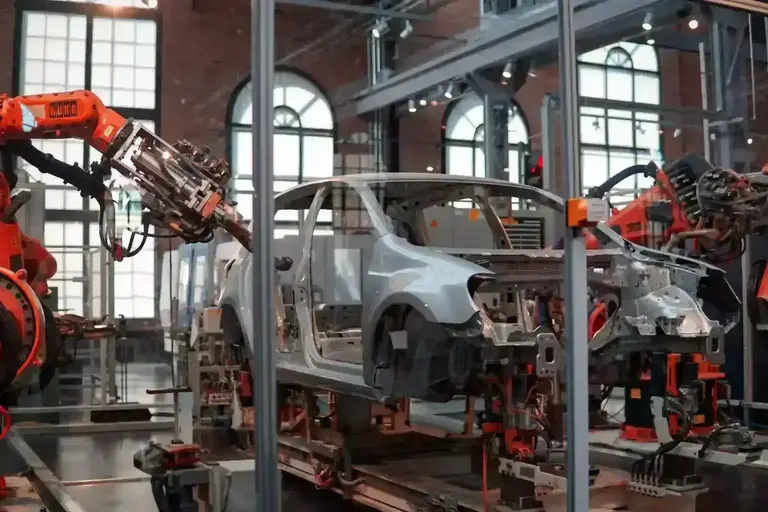
Tetapi, seperti kata para leluhur bangsa dalam mimpinya: tidak ada bangsa yang maju tanpa melalui transformasi yang menyakitkan dan menyeluruh.
Namun, dalam perjalanan pulang, Kabayan juga merenungkan peringatan yang tersirat dari diskusi dengan para founding fathers. Setiap bangsa membayar harga sesuai sejarahnya, tapi tidak semua harga layak dibayar.
Korea mengorbankan demokrasi untuk pembangunan, tapi kemudian berhasil mengembalikannya dengan lebih kuat. Vietnam mengorbankan kesejahteraan jangka pendek, tapi tetap mempertahankan kohesi sosial.
China mengorbankan kebebasan, tapi tetap menjaga martabat budayanya.
"Kita harus memilih harga yang membuat bangsa ini tetap manusiawi," gumam Kabayan. "Transformasi yang brutal memang perlu, tapi jangan sampai kita kehilangan jiwa bangsa yang gotong royong dan bermartabat."
Pertanyaan sekarang: apakah rakyat Indonesia siap menghadapi transformasi yang menyakitkan namun holistik demi masa depan yang lebih baik? Ataukah mereka akan terus terjebak dalam fantasi pembangunan tanpa perubahan menyakitkan?
Call to Action Personal
 Mungkin kita bukan Kabayan yang bisa jual sawah untuk kuliah di Harvard. Mungkin kita bukan Bung Hatta yang bisa memimpin revolusi. Tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut menyangga ilusi.
Mungkin kita bukan Kabayan yang bisa jual sawah untuk kuliah di Harvard. Mungkin kita bukan Bung Hatta yang bisa memimpin revolusi. Tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut menyangga ilusi.
Kita bisa mulai dari lingkaran terkecil—dengan berkata tidak pada korupsi kecil, pada privilege tanpa kompetensi, pada pendidikan yang malas berpikir.
Kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari oligarki kecil-kecilan di kantor, di kampus, di RT-RW. Kita bisa memilih untuk tidak mewariskan budaya "asal bapak senang" kepada anak-anak kita.
Seperti kata orang Sunda yang diingat Kabayan: "Lamun hoyong meunang, kudu wani rugi heula" (Kalau mau menang, harus berani rugi dulu).
Mungkin sudah saatnya Indonesia berani rugi dalam jangka pendek—dan berani merombak total keempat pilar kegagalan secara bersamaan—demi kemenangan jangka panjang.
Tetapi apakah kita punya keberanian seperti Kabayan yang rela menjual sawah demi mencari jawaban? Apakah kita punya keberanian untuk membayar harga transformasi yang tetap mempertahankan kemanusiaan kita?
Ataukah kita akan terus nyaman dengan ilusi bahwa bisa maju tanpa mengorbankan apa-apa—seperti orang yang berharap bisa sehat tanpa mau operasi tumor ganas yang menggerogoti tubuhnya?
Republik ini menunggu bukan pemimpin sempurna, tapi warga yang berhenti pura-pura lupa.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.







