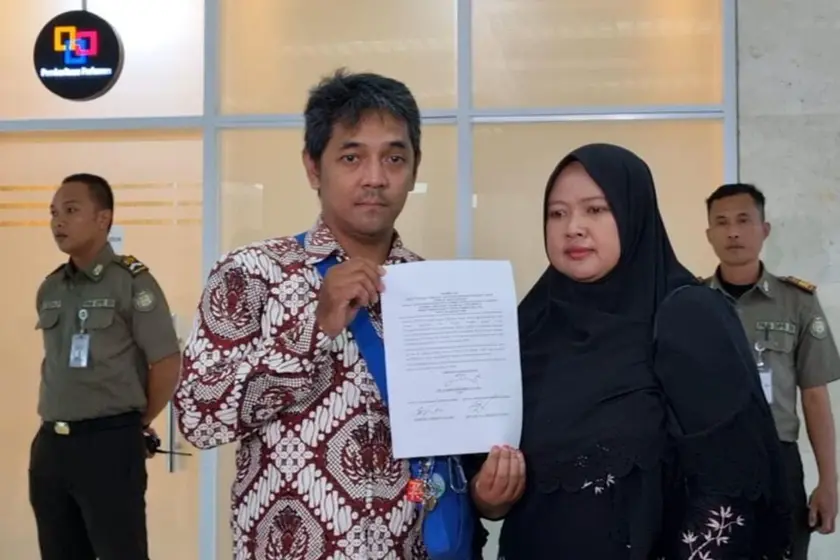Jakarta, TheStanceID - Presiden Joko Widodo menghitung hari. Jelang sebulan sebelum masa jabatannya berakhir, pria yang akrab dipanggil Jokowi ini melakukan safari peresmian smelter berbagai bahan mentah mineral di tengah kencangnya angin kritikan terkait deindustrialisasi.
Terbaru, Jokowi meresmikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Smelter bauksit tersebut dikelola PT Borneo Alumina Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.
Sebelumnya, Jokowi telah meresmikan dua mega proyek smelter tembaga baru di Indonesia, Senin (23/9/2024). Keduanya adalah smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan smelter punya PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.
Jokowi rela terbang berbeda pulau dalam dua hari ini demi upacara seremoni yang identik dengan program hilirisasi nasional. Dalam berbagai kesempatan, ia memang menyatakan keinginannya agar kelak Indonesia bisa menjadi negara industri.
“`Pembangunan smelter ini adalah usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri untuk mengolah sumber dayanya sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden dalam peresmian Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa (24/9/2024).
Bahkan, ia menegaskan untuk stop ekspor bahan-bahan mentah. “Olah sendiri karena nilai tambahnya akan kita peroleh untuk masyarakat dan itu kelihatan sekali,” jelas Jokowi.
Setop Tradisi 400 Tahun
Kepala Negara juga bercerita bahwa Indonesia mengekspor bahan mentah selama 400 tahun atau sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu kebanyakan bahan mentah yang diekspor adalah hasil bumi seperti rempah-rempah, gula, dan hasil tambang.
Menurut Jokowi, negara pengekspor bahan mentah seharusnya sudah menjadi negara maju. Namun ironisnya, Indonesia masih menjadi negara berkembang padahal negara-negara maju sudah “kecanduan” impor bahan mentah dari Indonesia.
“Tak heran saat kita ingin melakukan hilirisasi pada 4 tahun lalu pasti diganggu, pasti mereka tidak rela dan tidak mau,” katanya. “Tapi untungnya ada geopolitik global, COVID-19, dan resesi ekonomi sehingga negara maju sibuk dengan masalah yang mereka hadapi. Sibuk dengan problem-problem yang harus mereka selesaikan dan melupakan kita,” cerita Jokowi.
 Berdasarkan catatan TheStanceID, Indonesia memulai industrialisasi pada 2020 lalu dengan menyetop ekspor nikel. Saat itu, Uni Eropa ‘tidak terima’ dan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Berdasarkan catatan TheStanceID, Indonesia memulai industrialisasi pada 2020 lalu dengan menyetop ekspor nikel. Saat itu, Uni Eropa ‘tidak terima’ dan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Tidak kapok, Indonesia kembali menyetop ekspor bahan mentah untuk bauksit dan tembaga. Jokowi memang benar-benar memanfaatkan momentum untuk membangun industri dan smelter dari mineral-mineral yang dimiliki Indonesia.
Smelter diharapkan menjadi game changer karena beberapa peran krusial. Pertama, bisa meningkatkan nilai tambah mineral. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Ketiga, membantu meningkatkan pendapatan negara.
Jokowi mengklaim lompatan penerimaan negara dari ekspor bahan jadi itu sudah terlihat. Nikel misalnya, sebelum 2020 nilai ekspor (bahan mentah) US$1,4 miliar-US$2 miliar, dan tahun lalu nilai ekspornya sudah melambung mencapai US$34,8 miliar.
Begitu juga dengan hilirisasi tembaga dari smelter PT Freeport Indonesia yang ditargetkan meraup Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara. Potensi angka tersebut berasal dari dividen, royalti, pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor, dan lain-lain.
Belum Berujung Reindustrialisasi
Membangun smelter bukanlah hal yang mudah. Perusahaan perlu merogoh kocek dalam-dalam.
TheStanceID mencatat, untuk Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) saja, perseroan mengalokasikan belanja modal sekitar Rp16 triliun. Bahkan, Amman Mineral mengeluarkan dana hingga Rp21 triliun dan Freeport rela mengeluarkan dana hingga Rp56 triliun.
Sekadar tahu saja, smelter Freeport Indonesia ini memiliki desain jalur tunggal terbesar di dunia karena mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas hampir 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga 600 ribu - 700 ribu ton per tahun.
Sementara itu, smelter Amman bisa menghasilkan 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas batangan, 55 ton perak batangan, dan 850 ribu ton asam sulfat.
Namun, rupanya hilirisasi tambang saja belum cukup untuk memperkuat sektor manufaktur Indonesia, untuk melakukan apa yang ekonom sebut sebagai re-industrialisasi. Pertumbuhan industri pengolahan barang tambang terjadi berbarengan dengan turunnya industri pengolahan lain, misalnya tekstil.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non-migas pada 2015 tercatat sebesar 6,52%. Sempat menguat ke angka 7,08% (2019), kontribusi sektor ini anjlok ke level 5,97% pada 2023.
Nilai tambah manufaktur pun menurun di era Presiden Jokowi. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) menyebut kondisi ini sebagai tanda-tanda deindustrialisasi dini, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%.
Deindustrialisasi adalah suatu kondisi perekonomian dimana sektor pengolahan (industri) tidak dapat lagi berperan sebagai mesin utama pendorong ekonomi negara. Gejalanya dilihat dari penurunan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Sepanjang era Presiden Megawati hingga Presiden Jokowi, sektor manufaktur di Indonesia secara konsisten menyusut dan tumbuh di bawah laju pertumbuhan PDB nasional," ungkap LPEM dalam keterangan resmi yang dirilis pada awal tahun ini.

Dalam laporan Proyeksi Kuartal I-2024, LPEM UI mencatat rata-rata nilai tambah manufaktur di era Jokowi adalah sekitar 39,12% (2014-2020), jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati yang sebesar 43,94% dan Presiden SBY sebesar 41,64%.
Bukan Deindustrialisasi, tapi Bermasalah
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah telah terjadi deindustrialisasi. Dia menyebut, sektor manufaktur tetap tangguh meski memang ada masalah. Basisnya adalah data Bank Dunia tentang Negara Terbaik dalam hal Penciptaan Nilai Tambah.
"Meski dalam lima tahun terakhir, manufaktur nasional banyak diterpa masalah, banyak menghadapi tantangan luar biasa. Kadang-kadang berat, tapi sangat berat. Mulai dari pandemi, masalah geopolitik, dan lain sebagainya," kata Agus seperti dikutip Inilah.
Dia mengutip data World Bank pada 2023 yang menempatkan Indonesia di posisi 12 Top Manufacturing Countries by Value Added di dunia. Nilai tambah industri manufaktur di Indonesia mencapai US$255 miliar, atau setara Rp4.080 triliun (kurs Rp16.000/US$).
Pak Menteri betul bahwa angka nilai tambah sektor manufaktur Indonesia berada di urutan 12 besar dunia. Namun yang beliau mungkin lupa, porsi atau peranannya terhadap PDB terus menurun yakni dari 21,1% pada (2014) menjadi hanya 18,7% (2023), menurut data Tradingeconomics.
Turunnya peran manufaktur terhadap PDB inilah yang disebut: deindustrialisasi.
Secara eksplisit Jokowi mengakui perjuangan hilirisasi memang tidak mudah, dan bukanlah capaian yang belum bisa dibanggakan dari aspek industrialisasi. Dia berharap upaya ini dilakukan dan diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang.
“Ini akan menjadi jejak-jejak dimulainya industrialisasi di negara kita Indonesia,” tutup dia. (spi)